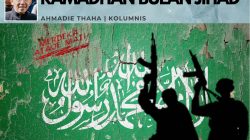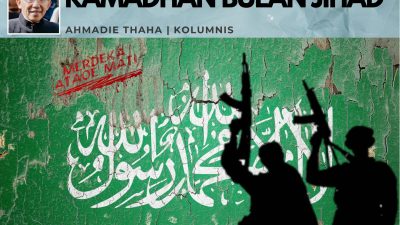Catatan Cak AT
Saya selalu membayangkan demonstrasi tanpa alat komunikasi itu seperti arisan tanpa grup WhatsApp: niat berkumpul ada, emosi membara, tapi alamat rumah siapa pun jadi misteri. Pesan tak sampai, gambar tidak terkirim, video tak pernah menembus kamar sebelah.
Nafsu menjatuhkan pemerintahan Iran memang bisa menyala sampai ubun-ubun. Segala cara dipakai penguasa Amerika Serikat dan Israel untuk menaklukkan Persia. Mereka sudah mencoba menyerang dengan peluru dan bom, mengerahkan mata-mata, semuanya gagal.
Kali ini, mereka menggerakkan massa untuk berdemo di berbagai pelosok negeri para Mullah itu. Tetapi tanpa jaringan, tanpa komunikasi, tanpa perangkat internet, nafsu itu cuma jadi panas kepala yang menguap di udara malam.
Maka ketika media Barat serempak mengabarkan “Iran mematikan internet,” saya tersenyum tipis — senyum orang yang tahu bahwa yang terjadi tidak sesederhana saklar listrik.
Di tengah hiruk-pikuk itu, saya teringat satu ayat al-Qur’an yang sering terdengar klasik, tetapi justru terasa paling mutakhir di zaman kabel optik dan satelit.
Bunyi ayat: _“Wa a‘iddu lahum mā istaṭa‘tum min quwwah wa min ribāṭil-khayl…”_ — “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka segala kekuatan yang kamu sanggupi, dan dari ikatan kuda-kuda perang…” (QS. al-Anfāl: 60).
Dalam bahasa hari ini, ayat itu seperti pesan singkat lintas abad: jangan pernah berhadapan dengan musuh dalam keadaan telanjang strategi.
Para mufassir sejak dulu menjelaskan bahwa _“quwwah”_ dalam ayat itu bukan sekadar otot dan senjata. Nabi sendiri menafsirkan _quwwah_ sebagai kemampuan yang paling efektif pada zamannya. Ibnu Katsir menekankan bahwa yang diperintahkan bukan jenis alat tertentu, melainkan prinsip kesiapan maksimal sesuai perkembangan teknologi.
Adapun _“ribāṭ al-khayl”_ — kuda-kuda yang ditambatkan di garis depan — bukanlah romantika padang pasir, melainkan simbol kesiapsiagaan logistik dan militer: kendaraan tercepat, sistem paling mutakhir, alat paling siap pakai pada masanya.
Jika hari ini kuda digantikan oleh drone, satelit, siber, dan spektrum frekuensi, maka semangat ayat itu tidak berkurang setitik pun. Ia justru menemukan bentuk barunya.
Karena itu, ketika para pemimpin Iran berulang kali menyatakan bahwa mereka “siap melayani siapa pun yang akan menyerang,” saya tidak membacanya sebagai retorika emosional belaka. Saya membacanya sebagai tafsir politik atas perintah ilahi: kesiapan bukan pilihan, melainkan kewajiban.
Siap bukan hanya di parade militer, tetapi juga di ruang tak kasatmata tempat perang hari ini berlangsung — di jaringan, di orbit, di udara yang dipenuhi gelombang.
Maka, sebelum kita sampai pada kisah tentang Starlink yang konon jadi andalan pemerintah AS yang tak tertaklukkan, penting dicatat: bagi Iran, kesiapan bukan slogan, melainkan laku strategis.
Ayat tentang _ribāṭ al-khayl_ telah lama berpindah kandang — dari kuda ke kabel, dari pedang ke spektrum. Dan di medan teknologi, mereka datang bukan sebagai penonton yang terpukau, melainkan sebagai pemain yang sudah menyiapkan peralatannya.
Dengan kesiapan penuh, Iran tidak memilih mematikan internet, sebab ia teknologi komunikasi canggih. Internet di Iran tetap hidup — tetapi hidup selektif, hidup bertarget. Sebagian warga tetap bisa mengakses internet, sebagian wilayah tetap bernapas mengakses dunia.
Yang dibekukan oleh penguasa Iran adalah akses internet pada simpul-simpul tertentu: titik demonstrasi, jalur koordinasi, dan kanal-kanal yang selama ini menjadi tulang punggung komunikasi para aktivis dan, konon, jejaring asing.
Narasi _“shutdown total”_ yang dimainkan media Barat memang terdengar heroik: dramatis, mudah dicerna, dan cocok dengan imajinasi tentang negara otoriter. Padahal yang terjadi jauh lebih canggih: bukan pemadaman, melainkan pembedahan jaringan.
Saya punya kenangan personal dengan Iran yang membuat saya sulit menelan cerita karikatural tentang negeri itu. Bertahun lalu, saya mengikuti kursus internet di sana, atas undangan pemerintah Iran melalui Kemenag. Kang Affandi Mochtar (alm), Sekretaris Ditjen Pendis, yang menugasi saya.
Yang saya temui bukan negeri gelap teknologi, melainkan sebuah ekosistem yang paham betul bagaimana jaringan bekerja — dan, lebih penting lagi, bagaimana jaringan bisa dilumpuhkan. Iran bukan penonton dalam teater digital; ia operator panggung.
Maka ketika pada Januari 2026 beredar kisah tentang “runtuhnya mitos kekokohan Starlink” di tangan militer Iran, saya tidak terkejut, hanya tertegun oleh detailnya. Nyatanya, upaya AS untuk menundukkan Iran dibikin keok lagi sama mereka.
Malam itu, para musuh di AS dan Israel kaget. Grafik lalu lintas data di Iran yang dipantau NetBlocks dan Cloudflare anjlok tajam. Aplikasi Starlink di tangan para pengguna ilegal — yang selama ini diselundupkan ribuan unit ke Iran — berhenti di satu kata tragis: _Searching…_. Macet di situ.
Para analis keamanan siber mencatat lonjakan _packet loss_ — yakni hilangnya paket data dalam transmisi — hingga puluhan persen. Internet satelit Starlink yang digadang-gadang kebal sensor ternyata tersandera di bumi Iran, bukan di langit.
Di sinilah ironi teknologi bekerja. Starlink, dengan ribuan satelit orbit rendah, memang sulit “dijatuhkan” secara kinetik. Tetapi Iran paham, terminalnya di darat membutuhkan dua hal: koneksi ke satelit dan sinyal GPS untuk mengunci posisi.
Sinyal GPS — yang dipancarkan dari satelit ke bumi berjarak ribuan kilometer — secara alami lemah. Garda Revolusi Iran paham betul kelemahan ini. Maka mereka mengerahkan _mobile jammers_ ke titik-titik sensitif, membanjiri frekuensi di permukaan bumi sana dengan kebisingan radio.
Hasilnya nyaris puitis. Antena Starlink dipaksa berputar-putar seperti kompas di kutub magnet: buta arah, mencari sinyal yang ada namun tak bisa disentuh. Internet itu ada di atas sana, tetapi aksesnya di bumi dibakar gelombang elektromagnetik.
Para analis menunjuk pada pengalaman Rusia di Ukraina dan dukungan infrastruktur Tiongkok sebagai sumber pengetahuan yang “diadaptasi” Iran. Strateginya elegan sekaligus dingin: ganggu GPS milik Amerika, sementara sistem sendiri tetap berjalan lewat BeiDou dan GLONASS.
Ini bukan sekadar pemblokiran; ini _area denial_ digital — menutup musuh, membuka diri. Keesokan harinya, pemerintah mengaktifkan internet berbasis _white list_: jaringan menyala bagi kantor pemerintahan, media negara, dan institusi resmi; gelap bagi mereka yang bergantung pada Starlink.
Dunia luar menyebut tindakan Iran itu represi. Tetapi dari sudut pandang teknik, ini adalah manajemen spektrum. Kalau boleh disebut, perang spektrum.
Puncaknya datang ketika bukan hanya internet yang dibisukan, melainkan juga telepon kabel. Tanpa data, tanpa seluler, tanpa _landline_, Iran menjelma kotak hitam raksasa.
Di dalam kesunyian itu, media negara membangun narasi “agen asing”—perang psikologis klasik: membingkai tindakan keras sebagai penyelamatan nasional. Urutannya nyaris manual strategi: butakan mata (internet), putuskan lidah (telepon), lalu bergerak tanpa saksi.
Di California, tim SpaceX milik Elon Musk dikabarkan bekerja lembur membereskan jaringan Starlink. Cuitan jumawa mereka, _“the beams are on,”_ terasa seperti _punchline_ yang tertelan.
Ada yang menarik: keberhasilan ini menunjukkan bahwa perang bukan semata soal otot militer, melainkan kecerdikan membaca titik lemah teknologi.
Negara-negara lain tak jarang menutup BTS, memotong kabel, atau mematikan ISP untuk membatasi akses warganya. Iran melangkah lebih jauh: menguasai spektrum.
Di masa depan, kekuasaan tak hanya diukur dari jumlah peluru, tetapi dari kemampuan mengendalikan — dan merusak — frekuensi di atas kepala rakyatnya. Demokrasi digital yang selama ini dielu-elukan mendadak tampak rapuh di hadapan _jammer_ yang diproduksi massal.
Di sinilah satire menemukan rumahnya. Sementara di Teheran, perang elektromagnetik menentukan hidup-matinya koneksi, di negeri kita terdengar kalimat lugu seorang jenderal saat meninjau banjir: “Kami bagikan Starlink kepada korban bencana, tapi nanti kuotanya, tidak tahu siapa yang bayar.”
Kalimat itu lebih jujur daripada seribu seminar transformasi digital. Kita memuja perangkat, lupa pada ekosistem; mengagungkan sinyal, lupa pada tata kelola. Kita berharap langit menyelamatkan bumi, sementara di tempat lain, bumi justru memukul langit.
Dari Persia, saya belajar satu hal yang terasa paradoks: teknologi paling canggih tetap tunduk pada niat politik dan kecerdasan strategis.
Dari Indonesia, saya belajar hal lain yang tak kalah penting: tanpa kejelasan tata kelola, teknologi hanya menjadi mainan mahal—menghibur di poster, gamang di lapangan.
Di antara dua kutub itu, kita dihadapkan pada pertanyaan yang jarang kita ajukan: apakah koneksi kita selama ini benar-benar alat pembebasan, atau sekadar perpanjangan dari cara lama berkuasa?
Mungkin di sinilah hikmahnya. Di Teheran, angka-angka _packet loss_ menjadi bahasa kekuasaan. Di sini, kebingungan soal “siapa yang bayar kuota” menjelma metafora tata kelola.
Yang satu menunjukkan betapa negara bisa mengendalikan teknologi; yang lain mengingatkan betapa teknologi bisa mengendalikan kita ketika kita tak siap mengelolanya.
Tragedi informasi di satu tempat, komedi kebijakan di tempat lain. Keduanya mengajak kita berhenti memuja gawai dan mulai memikirkan makna.
Karena pada akhirnya, jaringan bukan sekadar kabel, satelit, atau spektrum. Ia adalah relasi kuasa, etika, dan pilihan politik.
Di dunia yang semakin terhubung, kebebasan bukanlah soal sinyal yang selalu ada, melainkan tentang siapa yang memegang saklar — dan apakah kita paham konsekuensinya ketika lampu menyala, atau ketika ia sengaja diredupkan.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 16/1/2026