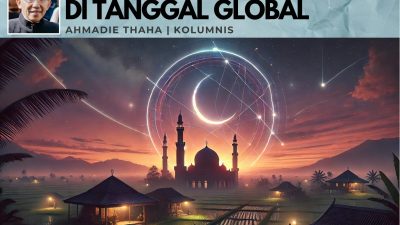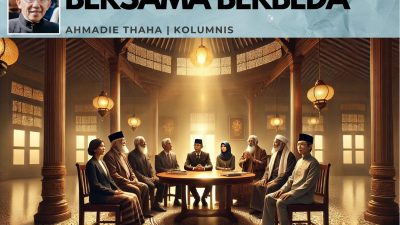Catatan Cak AT
Anjing itu jangan-jangan setengah suci. Setidaknya separuh dari reputasinya sudah dicuci bersih oleh Kitab Suci, yang menyebut namanya sampai lima kali dalam al-Qur’an —rekor yang bahkan ayam potong sekalipun tak mampu pecahkan meski setiap hari meramaikan meja makan umat manusia.
Aneh bin ajaib, sementara kita sibuk mempersoalkan fiqih air liurnya, al-Qur’an malah memasukkan makhluk ini dalam daftar hewan terhormat, disebut lengkap dengan jabatan kehormatan: penjaga gua kaum Aṣḥābul Kahf. Plus disebut pula dalam konteks perburuan _mukallibīn_, hewan terlatih yang bekerja seperti anjing, berdisiplin, taat SOP, tidak main-main seperti birokrat level kabupaten.
Kalau begitu, apakah benar saran para ilmuwan modern bahwa anjing adalah makhluk paling tua dalam sejarah domestikasi? Jangan-jangan yang tua bukan anjingnya, tapi hubungan cinta segitiga antara manusia–makanan–anjing yang tak kunjung putus sejak zaman batu.
Maka ketika ilmuwan genetika membuka kembali reruntuhan purba di Kazakhstan dan menemukan enam anjing dikubur rapi, entah sebagai peliharaan kesayangan atau sesajen, saya langsung curiga: jangan-jangan ini bukan pemakaman biasa.
Kayaknya ini mirip prosesi pejabat dilepas purnatugas. Ia dihormati dengan segala tata krama, diberi ruang khusus, bahkan mungkin disertai instruksi terakhir kepada generasi anjing penerus: jaga manusia ini baik-baik, meski kadang mereka keras kepala dan suka berpindah ideologi setiap tiga tahun sekali.
Para ilmuwan pun merunut DNA-nya, seperti kita merunut silsilah keluarga untuk mencari siapa sebenarnya yang mewariskan bentuk hidung paling tidak simetris di keluarga besar. Hasilnya mencengangkan: anjing sudah jalan-jalan ke mana-mana jauh sebelum manusia kenal koper, boarding pass, atau TikTok.
Di Eurasia, 10.000 tahun silam, anjing-anjing itu berpindah dari satu perkampungan ke kampung lain, kadang dibawa manusia, kadang malah ditinggal, dan anjingnya justru menetap. Betapa ironis —manusianya pergi, anjingnya tetap.
Para ahli genetika —yang hobi membangunkan kembali sejarah dari serpihan tulang dan gigi seperti arkeolog berjubah lab— melakukan penelitian monumental atas DNA 17 anjing purba dari kawasan Eurasia, dengan rentang usia hingga 10.000 tahun.
Mereka memanfaatkan teknologi sekuensing DNA purba yang sekarang sudah lebih canggih dari sinetron yang bisa menghidupkan kembali tokoh yang mati tiga musim lalu. Dalam jurnal _Science_ edisi 13 November 2025, tim yang dipimpin Laurent Frantz dari Ludwig Maximilian University of Munich mengungkap peta migrasi anjing yang luar biasa rumit.
Mereka menemukan bahwa sebelum Zaman Perunggu, anjing di Eurasia bagian barat dan timur adalah dua populasi berbeda, seperti dua suku tetangga yang saling tahu tapi enggan gabung arisan. Di wilayah Botai, Kazakhstan, justru ditemukan anjing yang memiliki jejak nenek moyang dari kawasan Arktik —barangkali karena iklimnya dingin atau masyarakat Botai butuh hewan penjaga yang bisa tahan cuaca “lemari es alami”.
Namun ketika teknologi perunggu melaju dari barat ke timur 5.000–4.000 tahun lalu, masyarakat Botai tersapu perubahan besar: genetika manusianya banyak yang hilang, budaya mereka tergantikan, dan anjing-anjing mereka pun ikut lenyap dari garis keturunan.
Anehnya, di Asia Timur terjadi fenomena yang berkebalikan: penduduk lokal tetap dominan secara genetik, tapi mereka mengadopsi teknologi perunggu “bersama” anjing-anjing pendatang. Bahasa akademisnya: gen anjing menyebar seperti inovasi budaya. Bahasa kampungnya: manusianya ogah pindah, tapi anjingnya yang diterima masuk keluarga.
Dari penelitian ini, ilmuwan menyimpulkan bahwa anjing bukan hanya ikut manusia bermigrasi; dalam banyak kasus, anjing-anjing justru “bertahan” ketika manusianya tak lagi menetap —menjadikan DNA anjing semacam buku harian peradaban yang lebih disiplin daripada catatan sejarah manusia.
Ketika teknologi perunggu merambat dari barat ke timur benua Asia, masyarakat Botai di Kazakhstan seperti kena badai modernisasi yang terlalu cepat. Kebudayaan mereka tersapu; genetika manusianya hilang bak proposal pembangunan desa yang tak pernah kembali dari meja camat; bahkan anjing-anjing mereka ikut punah, seolah menyadari majikannya sudah tak ada lagi, dan mereka pun pamit diam-diam, tanpa membuat upacara perpisahan.
Menariknya, para ilmuwan belum berhenti pada bentangan daratan Asia yang luas itu. Frantz dan rekan-rekan justru tampak gatal ingin membuka bab berikutnya: perjalanan anjing menuju Asia Tenggara hingga Australia —wilayah yang, bagi para genetisi, ibarat ruang belakang rumah yang belum dirapikan tetapi penuh kejutan.
Artikel _Time_ menyebut dengan jelas bagaimana Frantz _”eager to explore”_ jalur migrasi ini, karena sampai sekarang peta genetik anjing di kawasan kita masih seperti arsip kelurahan yang tercecer: ada petunjuk, ada pola, tapi belum pernah diurai tuntas.
Boleh jadi nenek moyang anjing-anjing di kampung kita pernah menumpang perahu Austronesia, ikut rombongan pelaut purba yang melintasi lautan seperti tukang pos antarbenua. Atau mungkin mereka datang lewat jalur darat yang perlahan tenggelam oleh sejarah. Kita belum tahu.
Yang jelas, Asia Tenggara —termasuk Nusantara— menunggu giliran dibedah DNA-nya. Siapa tahu, dalam heliks purba itu tersimpan rahasia kecil bahwa anjing-anjing di halaman rumah kita ternyata punya kisah petualangan lebih panjang daripada riwayat dinasti manapun.
Ada ahli menyebut anjing sebagai “teknologi”. Dan barangkali betul. Ia alarm rumah sebelum manusia kenal sensor gerak; ia penjaga malam sebelum kita kenal satpam; ia sahabat terapi mental jauh sebelum ada psikolog daring; ia bahkan navigator sebelum kompas ditemukan —meski terkadang navigasinya berakhir di warung bakso.
Jika demikian panjang umur hubungan manusia–anjing, wajar bila DNA mereka menjadi arsip perjalanan peradaban.
Para ilmuwan menyebutkan bagaimana anjing menyertai para pemburu, prajurit Romawi, penduduk pulau terpencil Siberia, hingga masyarakat Australia awal. Peradaban berpindah seperti curah hujan yang pindah musim, tapi anjing tetap setia berjaga, kadang lebih setia dibanding manusia itu sendiri.
Sedangkan kita —umat manusia modern— berkelahi soal apakah boleh bersentuhan dengan anjing, apakah najisnya kategoris atau berkadar, seolah lupa bahwa hewan ini ikut mengawal sejarah manusia sejak sebelum lahirnya pertanian, kota, dan negara.
Mungkin benar yang setengah suci bukan anjingnya, tapi kesetiaan mereka, sebuah nilai yang makin jarang ditemukan dalam relasi sosial kita yang semakin mirip pasar modal—sentimen naik turun berdasarkan isu harian.
Dan pada akhirnya, jika sebuah makhluk disebut berkali-kali dalam kitab suci, dijadikan simbol kesetiaan dalam kisah gua, serta diikuti jejaknya oleh ilmu genetika modern sebagai pengiring setia manusia sejak awal sejarah, maka barangkali yang perlu kita renungkan bukan apakah anjing itu najis atau tidak, tetapi mengapa manusia yang katanya makhluk paling bermartabat sering kali kalah setia dari seekor binatang.
Dalam renungan itu, tragedi menjadi gurauan lembut, gurauan menjadi pintu hikmah —dan sejarah anjing yang panjang tiba-tiba menjadi cermin: mungkin kita yang harus belajar, bukan mereka.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 28/12/2025