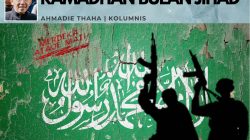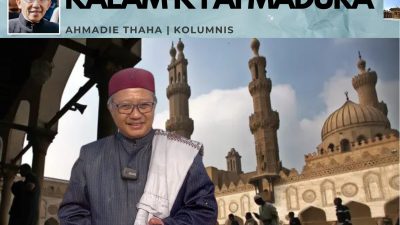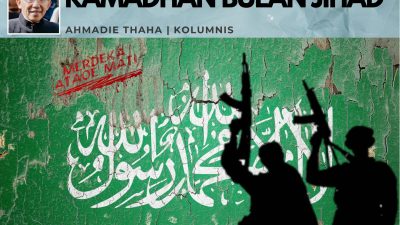Catatan Cak AT
Maaf sebesar-besarnya bila saya harus menuliskan ini. Di kalangan pengurus ormas Islam, mengulik dapur masing-masing itu ibarat mengupas bawang di depan umum: kita tahu pasti pedihnya bukan main, tapi apa daya sudah terlanjur menjadi konsumsi publik.
Saya sendiri pernah menjadi Sekjen Persatuan Ummat Islam (PUI), ormas yang usianya sedikit lebih muda dari Muhammadiyah namun lebih tua dari NU dan tercatat resmi sejak 1917. Maka naluri paling mendalam dalam tradisi keormasan adalah menjaga kehormatan, bukan meruntuhkannya.
Itu sebabnya, ketika gonjang-ganjing melanda PBNU kini, rasanya tak sopan bila kita hanya duduk memicingkannya menjadi sekadar “rebutan kursi dan wewenang.” Saya yakin, jarang pengurus ormas Islam berseteru karena ambisi jabatan.
Namun apa yang tersaji di media arus utama seolah ormas telah menabrak pagar etiket itu. Faktanya, Rais Aam Syuriyah NU, K.H. Miftachul Akhyar akhirnya mengumumkan bahwa KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
Situasi seolah gawat. Bayangkan, pengumumannya seperti keputusan penting di ruang krisis: terhitung 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, Gus Yahya tak lagi berwenang memakai atribut maupun berbicara atas nama PBNU. Kepemimpinan kini berada di tangan Rais Aam. Maksudnya, diambil-alih.
Konferensi pers pun digelar, para petinggi hadir, 36 PWNU se-Indonesia disebut ikut bermusyawarah. Bahkan dibentuk tim pencari fakta untuk menyisir isu-isu lain terkait yang beredar menghiasi pembicaraan publik, misalnya pertambangan, kebijakan, dan konflik kewenangan.
Bila itu sebuah drama politik, naskahnya tentu sangat sempurna: lengkap dengan kronologi, pernyataan resmi, relokasi kewenangan, bahkan ancang-ancang muktamar. Tapi itu terjadi dalam sebuah ormas Islam yang dipimpin para ulama, bahkan sebagiannya menyandang ulama khas.
Sayangnya, banyak orang kemudian tergoda melihat kasus ini hanya sebagai sengketa merebut navigasi organisasi: seolah-olah ada kuasa yang ingin dikunci, lalu ada kursi yang ingin direbut kembali. Seolah-olah ulama telah berebut posisi untuk mengurus cuan besar pertambangan.
Padahal siapa saja yang memahami kultur ulama NU, tahu persis bahwa di balik setiap keputusan para kiai ada satu hal yang jauh lebih besar dari urusan kekuasaan. Tidak ada kiai sepuh yang merelakan kehormatan ulama dijadikan permainan politik murahan.
Dalam perjalannya dari muktamar ke muktamar, tidak pernah ada kyai NU yang mau didudukkan —apalagi mengejar— jabatan Rais Aam, meskipun mereka tahu jabatan ini dapat dijadikan tiket menempuh ambisi pribadi. Urusan mereka di pesantren sudah lebih dari berat.
Setiap Rais Aam NU —meski tetap manusia yang bisa salah— senantiasa melangkah dari asas memperbaiki sesuatu yang dianggap sudah berada di titik genting. Ini bukan drama memperebutkan jabatan, tetapi tanggung jawab moral mengembalikan NU ke orbitnya.
Kita perlu memahami kultur NU agar tidak keliru membaca konteks. Silakan tengok ke belakang, dari sejarah muktamar ke muktamar. Betapa rumitnya tim formatur sembilan yang disebut _Ahlul Halli Wal ‘Ahdi_ (AHWA) mencari seorang kiai yang mau diangkat menjadi Rais Am.
Orang luar mengira jabatan itu diincar mati-matian seperti perebutan saham perusahaan tambang. Ah, betapa lucunya. Dibanding tradisi NU, perebutan jabatan di perusahaan multinasional itu justru jauh lebih sederhana: siapa yang menang tender, dialah yang dapat.
Di NU justru sebaliknya —tidak ada yang mau. Mari kita masuk ke Sidang AHWA. Bagi saya, itu lebih dramatis daripada pemilihan Paus di Konklaf Vatikan. Sembilan kiai terpilih dikumpulkan di ruang tertutup. Setiap nama yang muncul sebagai kandidat Rais Am, langsung menolak.
Nama-nama kandidat diseret, dioper, dilempar kembali. Bahkan belum sampai ditunjuk, baru dipandang wajahnya saja sudah angkat tangan sambil menggeleng. Muter, memantul, berseliweran seperti bola pingpong yang ditolak semua pemain.
Misalnya KH Maimoen Zubair, di Muktamar Jombang 2015, dengan tegas menolak: “Saya ini sudah tua, terlalu tua.” Lalu ditunjuklah KH Mustofa Bisri, beliau menolak juga. Dioper lagi, lari lagi. Sampai akhirnya KH Ma’ruf Amin “terpaksa” menerima.
Karena sudah dipojokkan oleh kiai-kiai sepuh, ia yang jauh lebih muda dari kiai-kiai lain terpaksa menerima dapukan jabatan Rais Am. Maka, di NU dan di banyak ormas Islam lainnya, model kepemimpinan bukan muncul dari keinginan, tapi dari keharusan moral untuk mengalah.
Di sinilah kita harus membaca peristiwa PBNU hari ini. Pemecatan Gus Yahya oleh Rais Aam mungkin terlihat sebagai perebutan pucuk organisasi. Tetapi di dalam tradisi keulamaan NU, jabatan itu justru ditempatkan sebagai beban amanah yang sering kali dihindari.
Ketika Rais Aam mengambil alih kewenangan, itu bukan kudeta, bukan pula gerak seorang politisi yang bernafsu pada kekuasaan. Itu gerakan seorang ulama yang merasa perlu menghentikan badai, sebelum kapal tenggelam dan penumpangnya kacau balau.
Indonesia sering tak paham betapa NU itu bukan sekadar organisasi besar. Ia seperti rumah raksasa yang seluruh tiangnya berdiri dari keikhlasan dan ketawadhuan. Mungkin banyak orang melihat risih dengan pergolakan di tubuh NU, tapi yakinlah itu bukan perebutan kekuasaan.
Dalam ormas Islam, ketika satu pilar goyah, bukan hanya bangunannya yang terancam, tetapi sejarah panjang yang dijaga para ulama. Dan seperti dalam setiap tragedi sejarah, selalu ada yang mengira ini urusan kursi. Padahal yang dipertaruhkan adalah marwah.
Mungkin inilah pelajaran terbesarnya: kadang badai tidak datang untuk merobohkan kapal, tetapi justru untuk menguji siapa yang masih bertahan di kemudi dengan keyakinan dan adab.
Kadang kehilangan jabatan bukan akhir sebuah karier, tetapi awal untuk menata ulang arah.
Kadang krisis menjadi cara Allah Swt mengingatkan kita bahwa kehormatan lebih mahal dari kekuasaan.
Dan barangkali, dari peristiwa ini NU tidak sedang retak —ia justru sedang dirawat.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 1/12/2025