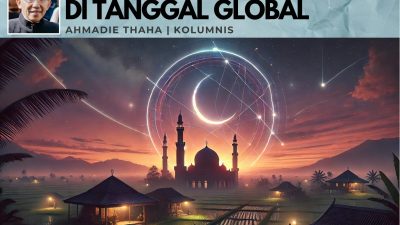Catatan Cak AT
Mari kita mulai dari yang paling sederhana dan paling rumit sekaligus: makan. Ya, urusan perut yang katanya sepele, tapi sesungguhnya menjadi sumber segala drama ekologis dunia modern. Piring yang kita isi tiga kali sehari itu, diam-diam mengatur arah bumi: ke surga kelestarian, atau ke jurang kebinasaan.
Dalam laporan Top 10 Emerging Technologies 2025 kolaborasi World Economic Forum (WEF) dan Frontiers, dua teknologi pertama yang dipilih bukan roket ke Mars, bukan AI, atau chip pengatur otak —melainkan sesuatu yang berhubungan dengan dapur: precision fermentation dan automated food waste upcycling.
Kedua teknologi tampak sederhana, tapi sebenarnya sedang menulis ulang kitab besar tentang hubungan manusia dengan makanan, bumi, dan masa depan.
Bayangkan dunia di mana daging tidak lagi berasal dari sapi yang perlu padang rumput seluas provinsi, air seliter-seember, dan kentut yang menghasilkan gas metana sebanyak satu mobil tua. Bayangkan susu tanpa sapi, telur tanpa ayam, bahkan kopi tanpa pohon.
Semua itu kini bukan lagi fantasi vegan ekstremis, tapi hasil kerja mikroba di dalam bioreaktor —makhluk halus dalam dunia sains yang lebih patuh dari politisi dan lebih produktif dari influencer. Jumlah mikroba ciptaan Allah Swt itu tak kasat mata, tapi bekerja patuh mengikuti SOP Sang Maha Kuasa.
Teknologi ini disebut precision fermentation: fermentasi presisi, bukan fermentasi asal jadi seperti tape atau tempe zaman kakek. Ini mirip slogan polisi presisi? Jauh beda: “Presisi Polri” adalah singkatan dari PREdiktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan.
Para ilmuwan memprogram mikroba seperti insinyur memprogram komputer: mikroba diberi DNA sintetis, disuruh memproduksi protein tertentu, dan hasilnya bisa sama —bahkan lebih bersih— dari protein hewani. Tak perlu sawah, tak perlu ladang, tak perlu ternak. Cukup tabung stainless, listrik hijau, dan sains.
Di Inggris, misalnya, sebuah startup sudah berhasil membuat protein susu tanpa sapi. Di Amerika, daging “babi sintetis” sedang dikaji (konon halal secara kimia, tapi jangan khawatir, belum sampai ke pasar Indonesia —nanti kita repot di labelnya).
Di Singapura, burger dengan daging hasil fermentasi yang mutunya tak kalah dari daging asli sudah dijual di restoran berlisensi. Dan di Indonesia? Kita masih sibuk memperdebatkan apakah tahu bulat dari kedelai lokal itu inovasi atau krisis kreativitas kuliner.
Tapi jangan salah: teknologi ini nanti bisa menjadi jawaban atas krisis pangan, air, dan lahan yang makin mencekik. Ketika suhu global naik, sawah mengering, laut meninggi, dan populasi manusia bertambah dua miliar lagi, kita tak bisa terus-menerus berpikir bahwa makan itu hanya soal kenyang.
Makan adalah keputusan ekologis. Sangat bergantung pada alam dan lingkungan yang telah diciptakan begitu sempurna oleh Allah. Dan kalau setiap suapan bisa menghemat sepetak hutan, mengurangi emisi, dan menyelamatkan sumber air —bukankah itu ibadah modern yang paling nyata?
-000-
Nah, teknologi kedua, _automated food waste upcycling_, mungkin lebih dekat ke dapur rumah tangga. Ini soal bagaimana sisa makanan —nasi basi, kulit pisang, roti kedaluwarsa— tidak lagi jadi sampah, tapi bahan baku baru. Jumlahnya luar biasa besar, diproduksi manusia tiap hari.
Dengan bantuan AI dan sensor otomatis, limbah makanan yang jutaan ton diproduksi manusia tiap hari bisa disortir, kemudian dikeringkan, serta diolah ulang jadi bahan pupuk organik, energi biogas, sumber listrik, atau pangan bergizi. Ini bisa dibuat dalam skala rumahan hingga korporat.
Di Korea Selatan, mesin pengolah sisa makanan kini ada di apartemen. Di Eropa, restoran-restoran tinggi harga tinggi pula kesadarannya: mereka pakai sistem otomatisasi yang menghitung dan mengatur ulang stok agar tak ada yang terbuang. Di kampus-kampus, para mahasiswa teknik dan gizi berkolaborasi mengubah limbah kantin jadi pakan ikan, bahan sabun, bahkan plastik biodegradable.
Bayangkan kalau teknologi semacam itu masuk ke sekolah-sekolah kita. Nasi sisa di kantin jadi kompos untuk taman, kulit jeruk jadi bahan pembersih alami, dan siswa belajar langsung tentang siklus kehidupan dari sisa makan siang. Tidak perlu khotbah panjang soal “jangan mubazir”, karena teknologi sendiri akan mempermalukan pemborosan.
Tapi tentu saja, bukan alatnya yang ajaib. Yang menentukan tetap manusianya. Karena sebagaimana diingatkan oleh para ilmuwan di WEF–Frontiers, teknologi hanyalah _enabler_ —penggerak, bukan pengganti kesadaran.
Fermentasi presisi tidak akan berarti kalau kita tetap rakus. Mesin daur ulang makanan tidak akan berguna kalau kita masih menganggap sisa makanan itu dosa yang bisa disembunyikan di tempat sampah.
-000-
Seorang teman pernah berseloroh, “Bumi ini rusak bukan karena manusia tidak punya teknologi, tapi karena manusia tidak punya rasa cukup.” Nah, mungkin dua teknologi ini sedang menuntun kita ke arah itu: agar kita makan secukupnya, tapi dengan cara yang tidak merusak apa pun.
Jika dulu revolusi industri lahir dari arang dan uap, maka revolusi pangan lahir dari mikroba dan kesadaran. Bukan lagi soal menanam, tapi menciptakan; bukan lagi tentang menghasilkan banyak, tapi menghasilkan cukup—tanpa merampas.
Dan jika itu terjadi, mungkin kelak anak-anak kita akan menulis buku sejarah berjudul “Zaman Ketika Daging tidak Lagi Membunuh Sapi.”
Teknologi bisa menggantikan pabrik, tapi tidak bisa menggantikan hati. Makan tanpa membunuh bumi memerlukan bukan hanya inovasi, tapi juga empati. Karena di balik setiap butir nasi atau burger sintetis, ada doa lama yang tetap sama: semoga yang kita makan menjadi berkah, bukan bala.
Dan barangkali, di situlah letak revolusinya — bukan pada tabung fermentasi atau robot daur ulang, tapi pada kesediaan manusia untuk menundukkan diri di hadapan bumi, dan berkata: “Maaf, aku sudah kenyang.”
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 28/10/2025