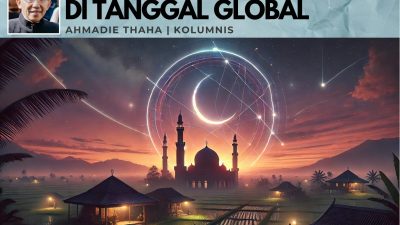Catatan Cak AT
Kalau ada lomba “Siapa Cepat, Siapa Lapor Polisi,” boleh jadi banyak pejabat dan institusi kita akan naik podium. Begitu tersinggung sedikit, langsung ancang-ancang bikin laporan. Netizen nyeletuk dikit, esoknya sudah keluar jumpa pers.
Untunglah kali ini, dalam kaksus Ferry Irwandi, TNI memilih jalur yang “Indonesia banget” —bukan langsung lapor, tapi konsultasi dulu ke polisi. Wah, ini langkah langka! Mungkin kalau sering dibudayakan, kita bakal punya “Budaya Konsultasi Sebelum Lapor” (BKSL).
Dan di sinilah Yusril Ihza Mahendra, Menko Kumham Imipas sekaligus juris senior, masuk dengan nada yang agak filosofis: “Pidana itu ultimum remedium, jalan terakhir.” Artinya, jangan baru kena senggol opini di medsos, langsung ngebut ke kantor polisi.
Dengan penuh kearifan, melengkapi upaya konsultasi pihak TNI, Yusril seolah kasih saran: Ada baiknya ngobrol dulu, mbok ya dialog dulu, siapa tahu yang dikatakan atau yang ditulis Ferry di media sosial itu cuma salah ketik atau efek auto-correct.
Kasus Ferry Irwandi bermula dari sejumlah unggahannya di media sosial. Di tengah maraknya demo-demo besar di Ibukota dan sejumlah daerah, aktivis ini mengungkap TNI tengah menyiapkan skenario “darurat militer” untuk merespons situasi politik dan keamanan dalam negeri.
Narasi ini tak hanya diangkat Ferry secara personal, tetapi juga bergema di lingkaran beberapa aktivis media alternatif yang kerap bersuara keras terhadap aparat. Bahkan sempat disorot pula oleh media besar seperti Tempo yang mengangkat isu serupa.
Namun, tudingan ini dianggap janggal karena pemberlakuan darurat militer bukanlah perkara “komando Panglima” semata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, penetapan darurat militer hanya bisa dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia.
Itu pun harus didasarkan pertimbangan ancaman nyata terhadap keamanan negara, kemudian disampaikan melalui Peraturan Pemerintah dan dilaporkan ke DPR. Artinya, TNI tidak punya kewenangan sepihak untuk menetapkan darurat militer. Mereka hanya menjadi alat negara yang menjalankan perintah Presiden.
Karena itu, bagi akal sehat, narasi Ferry hanyalah analisa semata. Tapi, bagi TNI, itu narasi provokatif yang dapat membentuk persepsi publik yang menyesatkan, dan berpotensi menggerus legitimasi TNI yang selama dua dekade terakhir tengah membangun citra sebagai tentara profesional dalam sistem demokrasi.
Membayangkan TNI menetapkan darurat militer hanya karena unggahan Ferry Irwandi di medsos itu ibarat membayangkan presiden mengeluarkan dekrit negara lewat status WhatsApp. Absurd sekaligus kocak.
Proses darurat militer jelas bukan perkara sepele: ada kajian intelijen, pertimbangan politik, keputusan Presiden, sampai mekanisme hukum via UU Keadaan Bahaya.
Jadi, tudingan Ferry bahwa TNI seenaknya bisa “klik tombol” darurat militer sama saja dengan menuduh tukang parkir bisa seenaknya mengibarkan bendera start Formula 1. Secara logika hukum dan prosedur kenegaraan, ini nonsense.
Namun di alam demokrasi digital, nonsense yang dikemas dramatis bisa laku keras —apalagi jika diamplifikasi kawan-kawan seperjuangan di kanal media alternatif yang hobi bikin headline bombastis.
Ironinya, sebagian media arus utama pun sempat latah, mengutip isu ini tanpa penjelasan utuh dan, lebih fatal lagi, tanpa konfirmasi. Alhasil, publik dijejali narasi horor seolah-olah TNI akan “turun gunung” menutup jalanan besok pagi.
Padahal, dalam kenyataan birokrasi kita yang terkenal ribet, bahkan pengadaan seragam pun bisa molor bertahun-tahun, apalagi menetapkan darurat militer.
Dalam literatur hukum pidana, ultimum remedium yang diungkap Yusril bukan barang baru. Para akademisi dari Utrecht sampai Sudarto sudah menekankan, hukum pidana ibarat palu Thor: jangan dipakai buat tiap masalah remeh, nanti meja retak semua. Hukum pidana seharusnya digunakan hanya ketika semua mekanisme sosial, etik, dan administratif gagal.
Namun dalam praktik, di Indonesia hukum pidana sering berubah jadi _primus remedium_ alias obat pertama. Macam pusing kepala dikit, langsung minum antibiotik dosis tinggi. Padahal kadang cukup minum air putih dan tidur siang.
Nah, kasus Ferry Irwandi ini menarik. TNI merasa dicemarkan oleh tudingan provokatif di medsos. Tapi, menurut Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024, “institusi” tidak boleh melapor pencemaran nama baik.
Menurut MK, hanya “individu” yang merasa dirugikan yang bisa lapor. Kalau begitu, siapa di TNI yang merasa dicemar? Panglima? Dansatsiber? Atau seluruh prajurit bikin laporan berjamaah di Polda Metro Jaya? Bisa penuh tuh loket laporan.
Menurut analis politik Boni Hargens, tudingan Ferry tentang TNI bikin darurat militer jelas provokatif. Mantan Kepala BAIS, Soleman Ponto, malah bilang ini manipulasi fakta yang bisa membahayakan NKRI.
Dari perspektif politik keamanan, provokasi semacam ini memang punya efek domino: publik resah, aparat terpecah, dan ruang demokrasi bisa direcoki. Tapi, di sisi lain, demokrasi tanpa provokasi itu ibarat sate tanpa sambal: hambar.
Peran media sosial di alam demokrasi justru membuka ruang bagi kritik, sikap sinis, bahkan narasi hiperbolik. Selama tidak menghasut kekerasan atau merusak integritas negara secara nyata, mestinya ruang dialog tetap ada.
Dan Yusril konsisten di jalur demokrasi: buka ruang dialog dulu. Tidak ada ruginya. Toh TNI sudah dianggap matang dalam berdemokrasi. TNI saat ini bukan tentara tahun 70-an yang alergi kritik dan sedikit-sedikit main ciduk.
Menariknya, secara positif langkah Brigjen Juinta Omboh yang datang ke Polda Metro Jaya untuk konsultasi justru membuka ruang pendidikan hukum bagi publik.
Polisi pun menjawab enteng: “Maaf jenderal, sesuai putusan MK, institusi tidak bisa melapor pencemaran nama baik.” Nah lho, ternyata TNI juga bisa kena “remedial hukum” sebelum sidang.
Ini patut dicatat: “budaya konsultasi sebelum lapor” bisa jadi model penyelesaian sengketa di era digital. Bayangkan kalau semua orang pakai jalur ini —dari artis ribut soal endorse, pejabat tersinggung meme, sampai tetangga protes suara karaoke.
Polisi pun mungkin bisa punya lebih banyak waktu untuk menangani kasus-kasus bangsa yang sangat serius dan masuk level merah: narkoba, human trafficking, judi, hingga korupsi.
Secara ilmiah, penelitian tentang digital disinformation (Wardle & Derakhshan, 2017) menunjukkan bahwa berita palsu atau provokatif di media sosial bisa merusak tatanan sosial, terutama jika menyasar institusi publik. Namun solusi yang paling efektif bukan selalu pidana, melainkan kombinasi: literasi digital, dialog terbuka, dan klarifikasi cepat.
Yusril tampaknya menggemakan hal yang sama: pidana itu jalan terakhir. Kalau dipakai terlalu cepat, yang terjadi justru “efek Streisand” —kritik makin viral, masalah makin besar.
Kasus Ferry Irwandi vs TNI adalah cermin tarik-menarik antara kebebasan berpendapat dan martabat institusi. TNI merasa dicemarkan, Ferry merasa berhak bicara, dan publik malah jadi penonton yang bingung siapa kebablasan.
Di tengah semua itu, Yusril tampil seperti dosen hukum pidana di kelas besar, menegaskan: hukum jangan jadi obat mujarab untuk tiap keluhan, karena ia hanya pantas dipakai ketika semua jalan lain buntu.
Mungkin, dari kasus ini kita bisa belajar: sebelum lapor polisi, cobalah minum teh, ajak dialog, atau sekadar kirim direct message.
Kalau masih buntu, barulah kita panggil palu Thor bernama hukum pidana. Itu pun, ingat kata Yusril: “Ultimum remedium, bukan primus remedium.”
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 13/9/2025