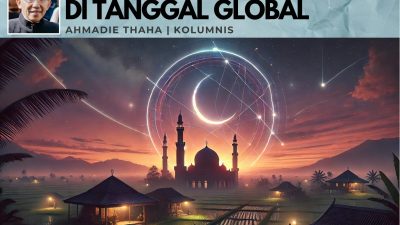Catatan Cak AT
Bayangkan Anda sedang makan bakso di warung sederhana. Suara sendok ketemu mangkuk porselen direkam jadi musik pengiring. Tiba-tiba datang petugas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), berkata: “Maaf, suara mangkoknya mirip perkusi, apakah sudah bayar royalti?”
Begitulah nasib dunia musik Indonesia: ribut sejagat bukan pada soal kreatifitasnya, tapi pada siapa yang paling berhak memungut royalti. Seolah-olah musik bukan lagi tentang getaran jiwa, melainkan getaran ATM. Ributnya mengganggu irama nafas.
Padahal, kalau merujuk pada Tempo (20 Agustus 2025), jelas masalah utama ada pada ketidaktransparanan sistem distribusi royalti. Banyak musisi kecil merasa seperti jadi kurir makanan: capek masak, capek antar, tapi tip disedot aplikasi.
Nah, di tengah drama “royalti vs hajatan”, ada satu solusi alternatif yang lebih segar, agak satiris, tapi serius: bikin lagu open source pakai AI. Tapi tentu tetap ada manusia pembuatnya, yang tetap memiliki hak cipta namun ala open source.
Jangan bayangkan robot Terminator menyanyi dangdut, tapi bayangkan komunitas kreatif baru, semacam “koperasi musik alternatif”, di mana para aktivis lirik, pembuat partitur, dan teknisi AI berkumpul. Ini bukan koperasi merdeka Merah Putih _top down,_ tapi merdeka dari royalti.
Mereka duduk bareng, mungkin sambil minum kopi sachet di emperan kampus seni, lalu berkata: “Oke, kita bikin lagu-lagu alternatif, semua orang boleh pakai, tapi tetap ada hak cipta yang tidak dimonopoli LMK.” Semua punya ruang kreativitas yang sepenuhnya merdeka.
Pertanyaan besar: apakah ada jenis lisensi berbentuk open source untuk lagu? Jawabannya: ada. Walau tidak persis seperti MIT atau Apache License di dunia software, musik bisa dibuka dengan lisensi _Creative Commons_ (CC) yang diakui dunia.
Bentuk lisensinya, misalnya: CC-BY: semua orang boleh pakai, asal mencantumkan pencipta. Ada juga CC-BY-SA: boleh dipakai, asal karya turunan ikut terbuka. Terakhir, model lisensi CC0: serahkan semua ke publik domain, alias ikhlas _lillahi ta‘ala._
Di Eropa, banyak musisi independen sudah pakai lisensi semacam ini. Band indie Berlin misalnya, merilis _track techno_ mereka di bawah CC-BY-SA sehingga DJ di Meksiko bisa melakukan remix atasnya tanpa takut digebuk polisi hak cipta.
Sementara di Amerika, komunitas “Open Music Initiative” (berbasis di Berklee College of Music, Boston) sudah mendorong _blockchain_ untuk transparansi royalti. Tujuannya, agar tidak ada _“blanket license”_ abal-abal seperti yang dikritik Panji Prasetyo di Tempo.
Di Indonesia? Kebanyakan masih terjebak logika “semua harus bayar”. Bahkan kafe kecil yang memutar playlist Spotify dengan iklan “Shopee, gratis ongkir” tetap kena tagihan. Bayangkan, para pemilik kafe kini ketar-ketir putar lagu apa pun, takut kena tagihan royalti.
Padahal, studi di Inggris menunjukkan bahwa kafe dan kedai justru meningkatkan popularitas musisi lewat pemutaran gratis. Di sana, pemerintah justru menganggap kedai kopi sebagai “ruang promosi”. Eh, di sini malah dianggap seperti “venue festival” skala Coldplay.
Di dunia internasional, konsep musik open source bukanlah mimpi utopis. Ada _Free Music Archive_ (FMA), sebuah perpustakaan musik bebas sangat besar yang dikelola sejak 2009 oleh radio independen WFMU di Amerika Serikat.
Ribuan musisi dari berbagai genre merilis karyanya dengan lisensi Creative Commons, sehingga bisa diunduh, dipakai, bahkan di-remix secara legal oleh siapa saja, mulai dari mahasiswa film indie sampai produser podcast. Hasilnya, musik tak lagi terkungkung birokrasi royalti, melainkan berkembang lewat kolaborasi lintas batas.
Selain itu, ada Jamendo, platform asal Luksemburg yang kini punya lebih dari 600 ribu track dari 40 ribu artis independen di seluruh dunia. Mereka menyediakan dua jalur: musik gratis berlisensi Creative Commons untuk publik.
Jakur lainnya, mereka juga menyediakan layanan komersial dengan sistem lisensi sederhana untuk bisnis yang mau memutar lagu di restoran atau toko. Model hybrid ini membuktikan bahwa musik bisa tetap terbuka, tapi pencipta tidak kehilangan hak ekonomi.
Bahkan, inisiatif seperti _Open Music Initiative_ yang digagas Berklee College of Music di Boston menunjukkan bagaimana teknologi blockchain bisa dipakai untuk transparansi royalti, sehingga tidak ada lagi musisi yang merasa “ditipu” oleh angka-angka gelap ala LMK.
Sekarang, mari bayangkan proses lahirnya komunitas musik AI alternatif tersebut. Pertama, keresahan jadi pemicu. Musisi indie Bandung, penyanyi jalanan Jogja, sampai pembuat _beat bedroom_ di Makassar sama-sama bosan diperas sistem royalti yang absurd.
Mereka mulai segalanya dengan bikin grup WhatsApp bernama “Musik Merdeka”. Dari obrolan itulah muncul gagasan: “Gimana kalau kita bikin lagu pakai AI, hasilnya open source, bebas dipakai siapa saja, tapi tetap diakui penciptanya?”
Kedua, muncul ruang kolaborasi. Di _coworking space_ pinggir jalan atau balai RW, mereka kumpul bareng. Lirik ditulis manual, musik dihasilkan pakai aplikasi AI seperti Suno, lalu digabung jadi karya utuh. Setiap karya langsung dirilis dengan lisensi Creative Commons.
Ketiga, sistem distribusi. Karena bosan dengan birokrasi LMK, mereka pakai GitHub atau platform serupa untuk lagu. Jadi bukan hanya kode yang bisa di-fork, lagu pun bisa di-remix. Anak kampus di Surabaya bisa bikin versi dangdut, sementara santri di Jombang bikin versi shalawat.
Keempat, pengakuan publik. Begitu media menulis, publik menyadari: ternyata ada jalan tengah antara “musik gratis tanpa penghargaan” dan “musik berbayar dengan birokrasi rente”. Komunitas ini jadi semacam Wikipedia-nya dunia musik, di mana semua orang bisa ikut kontribusi, tapi tetap ada struktur etika dan penghargaan.
Tentu ada yang sinis: “Lagu AI itu tidak punya jiwa!” Ya benar, tapi apa semua lagu manusia punya jiwa?
Mari jujur: jingle iklan mi instan atau lagu parpol kadang lebih mirip spam ketimbang ekspresi seni. Bedanya, saat AI bikin jingle basi, maka kita bisa langsung tekan tombol “delete”. Tapi kalau manusia bikin lagu basi, lagu ini bisa bertahan jadi ringtone selama satu dekade.
Yang lebih penting, AI memecahkan masalah aksesibilitas. Dulu, bikin musik butuh studio mahal, mixer, gitar seharga motor. Kini, cukup laptop kentang plus koneksi WiFi gratis tetangga, sudah bisa bikin orkestra digital.
Artinya, lebih banyak orang bisa masuk ke dunia penciptaan lagu tanpa terhalang modal. Daripada ribut soal siapa yang harus bayar royalti di pesta kawinan, lebih baik pemerintah memfasilitasi lahirnya ekosistem open source musik. Caranya?
Pertama, akui lisensi Creative Commons sebagai format sah hak cipta di Indonesia. Lantas dorong LMK untuk mengadopsi sistem digital seperti Spotify: berbasis data penggunaan nyata, bukan asumsi kursi restoran. Juga, bentuk program inkubasi komunitas musik AI.
Itu semua, maksudnya, agar musisi indie bisa berkreasi tanpa takut digebuk regulasi. Dengan cara itu, kita bisa mengurangi sengkarut royalti, sekaligus membuka ruang inovasi. Musik tetap dihargai, tapi tidak lagi jadi ladang rente segelintir lembaga.
Pada akhirnya, musik adalah soal resonansi, bukan soal retribusi. Ia mengikat manusia lewat nada, bukan lewat nota tagihan. Kalau musik bisa lahir dari suara jangkrik, bisakah kita membayangkan masa depan di mana musik lahir dari prompt AI?
Itu terbuka untuk semua, dan tetap adil bagi pencipta. Kalau itu bisa terjadi, mungkin di pesta kawinan nanti, yang ditagih bukan lagi royalti lagu, tapi royalti tawa karena kita berhasil menertawakan absurditas sistem lama.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 24/8/2025