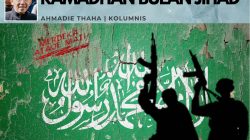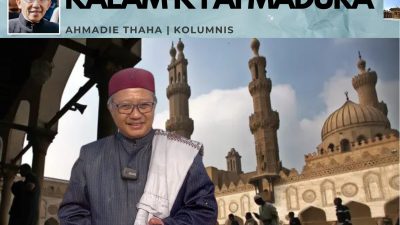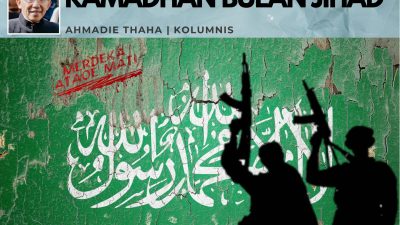Catatan Cak AT
“Pendidikan itu menanam. Pesantren menumbuhkan. Taman Siswa merawat. Maka marilah kita bertanam bersama, sebelum ladang ini jadi pabrik.” – Catatan dari halaman 5._
Pada suatu pagi yang biasa saja, halaman 5 koran Kedaulatan Rakyat menyajikan berita yang tak biasa: “Tamansiswa mendirikan pondok pesantren.” Tidak di perbatasan, bukan di desa ujung utara Sleman, tapi di jantung kompleks Taman Wijaya Brata, pada mushalla bersebelahan langsung dengan makam Ki dan Nyi Hadjar Dewantara di Yogyakarta.
Berita ini bisa saja luput dari perhatian jika Anda hanya mencari kabar seputar harga cabai atau kasus ijazah yang berseri-seri. Tapi bagi yang membaca pelan, dengan hati dan rasa sejarah, ini seperti menemukan bahwa akhirnya seperti Einstein buka pesantren fisika, atau Karl Marx menulis tafsir surat An-Nisa.
Mengejutkan, menyentuh, sekaligus membuat kening mengerut: Lho, kenapa baru sekarang?
Mari kita mulai dengan pertanyaan paling mendasar: kenapa Tamansiswa baru mendirikan pesantren setelah 103 tahun? Apakah karena Ki Hadjar dulu alergi sarung? Atau karena Majelis Luhur baru menemukan bahwa “Ki” dan “Kyai” itu berasal dari akar kata yang sama: penghormatan kepada ilmu, bukan gelar feodal?
Tentu tidak. Jawabannya lebih rumit dari sekadar masalah sarung atau sorban. Ini seperti menanyakan kenapa tukang bakso baru jual siomay setelah satu abad berdagang. Kadang kita hanya butuh momen yang tepat untuk menyadari bahwa identitas kita sejak dulu sudah nyantri, hanya tanpa menyebut diri sebagai santri.
Tamansiswa didirikan pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Meskipun menerima siswa dari berbagai latar belakang, termasuk pesantren, Tamansiswa bukanlah pesantren. Tamansiswa lebih menekankan pada pendidikan umum yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan.
Tamansiswa memiliki tiga semboyan utama yang dikenal sebagai “among”, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani. Sama seperti pesantren, Tamansiswa bertujuan mencerdaskan bangsa, mempertebal keindonesiaan, dan mencapai kemerdekaan.
Ki Rahmat Fauzi, pimpinan Pondok Pesantren Ki Hadjar Dewantara, berkata lantang: “Saya meyakini, Ki Hadjar Dewantara adalah orang pesantren.” Dan beliau tidak sendirian. Kalau kita telaah secara jujur, seluruh sistem Tamansiswa sejak awal memang bercita rasa pesantren —bedanya hanya pada kosmetika istilah dan tata busana.
Mari kita bandingkan:
Di pesantren, Kyai sebagai pemimpin spiritual. Di Tamansiswa, Ki sebagai pamong dan pendidik. Di pesantren, santri mondok; di Tamansiswa, belajar mengabdi . Di pesantren, murid hidup di asrama; di Tamansiswa, murid belajar berbudaya.
Di pesantren, ada kitab kuning, tafsir, akhlak. Sementara di Tamansiswa, ada sastra Jawa, sejarah, budi pekerti. Di pesantren, sanri menghormati guru melebihi orang tua. Di Tamansiswa, pelajar ing ngarso sung tulodho.
Di pesantren, ilmu sebagai cahaya, bukan komoditas, dan di Tamansiswa berlaku pendidikan sebagai alat pemerdekaan
Ternyata bedanya hanya di warna, tidak pada ruhnya. Ki Hadjar, tanpa sorban dan peci haji, adalah kyai pendidikan nasional. Ia mengaji filsafat Barat di satu sisi, namun menyisipkan nilai budi pekerti dan laku prihatin yang tak ubahnya lelaku pesantren.
Yang menarik dari Ponpes Ki Hadjar ini adalah target santrinya: para mahasiswa. Sebuah rekayasa sosial yang luar biasa, karena biasanya santri jadi mahasiswa. Tapi sekarang, setelah melewati jenjang S1, para sarjana diminta kembali “mondok” —agar tidak hanya pintar Google Scholar, tapi juga paham ilmu ngelmu kahanan.
Mungkin inilah kritik diam-diam Tamansiswa kepada dunia akademik hari ini: terlalu banyak kepala, terlalu sedikit hati. Maka didirikanlah pondok di tengah kampus keabadian Ki Hadjar, agar generasi post-TikTok ini bisa kembali mencium bau kitab dan sesekali mematikan ponsel saat mengaji.
Pertanyaannya kini: apakah pendirian ponpes ini murni kontinuitas nilai, atau justru respons terhadap kegelisahan modern? Bisa jadi, Tamansiswa —yang selama ini dipersepsikan sebagai sekolah nasionalis sekuler Jawa-sentris— merasa perlu menegaskan bahwa spiritualitas tidak pernah absen dari pendidikannya.
Kita hidup di zaman ketika pesantren dianggap benteng terakhir moral bangsa. Mungkin Tamansiswa pun ingin menunjukkan bahwa mereka tidak pernah kehilangan jati diri santri, hanya saja mereka menuliskannya dalam aksara Latin dan kadang dalam bentuk sandiwara panggung.
Barangkali inilah waktunya ki dan kyai bersatu kembali dalam satu laku pendidikan. Bukan sekadar rekonsiliasi istilah, tapi penyatuan visi bahwa pendidikan sejati adalah yang membebaskan jiwa, memerdekakan akal, dan menumbuhkan akhlak.
Perlu waktu satu abad lebih bagi Tamansiswa untuk “kembali ke pesantren”. Tapi kita tidak boleh menyikapinya sebagai keterlambatan. Lebih tepatnya, ini tanda bahwa pendidikan besar selalu menemukan jalannya kembali ke akar, bahkan bila harus melingkar dulu satu abad.
Dan kalau pun butuh 100 tahun untuk mendirikan pesantren, semoga tak perlu satu abad lagi untuk mencetak Kyai Hadjar Dewantara generasi baru. Salam hormat, dari santri Ki dan Kyai.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 8/7/2025