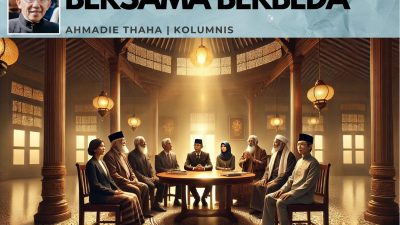GWS, 3 Juli 2025
Coba, bayangkan sebentar: Anda seorang mahasiswa PTPG di Bandung tahun 1958. Setiap pagi, Anda bangun dengan kebanggaan bahwa institusi Anda adalah salah satu dari hanya empat lembaga di seluruh Indonesia yang berhak mencetak guru. Tidak ada yang namanya “kampus pinggiran yang mendadak buka FKIP karena lagi trend.” Tidak ada oversupply lulusan keguruan. Yang ada adalah sistem yang ketat, terhormat, dan—yang terpenting—bertanggung jawab terhadap masa depan pendidikan bangsa.
Kini, 70 tahun kemudian, cucu Anda bisa kuliah di salah satu dari 400+ LPTK yang tersebar seperti warung nasi padang di seluruh nusantara. Apakah ini kemajuan?
Era Emas yang Terlupakan
Kemudian, mari kita mulai dengan nostalgia yang tak usah disembunyikan. Tahun 1954, ketika bangsa ini masih belajar berdiri tegak setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia dengan bijaksana mendirikan PTPG (Pendidikan Tinggi Pendidikan Guru) di empat lokasi strategis: Bandung, Malang, Batu Sangkar, dan Tondano. Empat saja. Tidak lebih, tidak kurang.
Tentunya, keputusan ini mencerminkan kearifan yang kini terasa asing: bahwa mencetak guru berkualitas membutuhkan konsentrasi sumber daya, bukan penyebaran tipis-tipis seperti mentega di atas roti tawar. PTPG menerapkan prinsip spesialisasi—mereka hanya fokus satu hal: menghasilkan guru terbaik dengan standar yang tidak bisa ditawar-tawar.
Berkaca dari apa yang dikatakan Ki Hadjar Dewantara, “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.” Filosofi kepemimpinan pendidikan ini tercermin sempurna dalam era PTPG: di depan memberikan teladan dengan kualitas, di tengah membangun semangat melalui selektivitas, di belakang memberikan dorongan melalui sistem yang bertanggung jawab.
Bandingkan dengan hari ini, di mana filosofi yang berlaku lebih mirip “sing penting ono” (yang penting ada). Kuantitas mengalahkan kualitas, aksesibilitas menggeser akuntabilitas.
Revolusi Sukarno: Dari Dualisme Menuju Sentralisasi IKIP
Selanjutnya, tahun 1963 menjadi titik balik penting ketika Presiden Sukarno, melalui Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1963, memutuskan untuk menyatukan dualisme FKIP dan IPG menjadi IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Keputusan ini lahir dari keresahan Bung Karno terhadap ketidakefisienan sistem yang terpecah-pecah.
Ironinya, masalah dualisme di era 1960-an justru lebih sederhana dibanding kekacauan hari ini. Dulu, “hanya” ada dua sistem yang berkompetisi: FKIP dan IPG. Kini? Ada ratusan lembaga yang beroperasi tanpa koordinasi, tanpa proyeksi kebutuhan, dan tanpa sistem kontrol yang jelas.
Menteri Prijono, yang sempat mendirikan IPG sebagai alternatif FKIP, mungkin akan tertawa getir melihat kondisi sekarang. Dia khawatir dengan dualisme dua lembaga, sementara kita hidup dalam era “multipolarisme” ratusan lembaga yang masing-masing merasa paling berhak mencetak guru.
Era IKIP (1963-1999) menunjukkan bagaimana sentralisasi yang bijaksana bisa menghasilkan kualitas. Sebelas IKIP tersebar strategis di seluruh Indonesia, masing-masing dengan mandat khusus untuk memenuhi kebutuhan regional. Sistem ini mempertahankan kontrol kualitas yang relatif baik sambil menjawab kebutuhan ekspansi secara terukur.
Seperti kata bijak, pause and reflect. Era IKIP mencerminkan kebijaksanaan untuk berhenti sejenak, memikirkan sistem yang tepat, baru kemudian melangkah dengan terukur.
Era Bank Dunia: “Modernisasi” Yang Menjadi Trojan Horse
Momentum kritisis terjadi di akhir 1990-an ketika gelombang reformasi ekonomi global mulai merambah pendidikan Indonesia. Program Bank Dunia “Secondary School Teacher Development” (1996-2001) menjadi katalis transformasi besar-besaran yang mengubah lanskap pendidikan guru Indonesia secara permanen.
Menteri Juwono Sudarsono dan Yahya Muhaimin, melalui Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999, menandatangani konversi IKIP menjadi universitas. IKIP Bandung menjadi UPI, IKIP Jakarta menjadi UNJ, dan seterusnya. Secara konseptual, kebijakan ini terdengar progresif: memberikan “kesetaraan” kepada IKIP dengan universitas umum.
Tapi seperti cerita tentang Kuda Troya dalam mitologi Yunani, “hadiah” modernisasi ini ternyata membawa konsekuensi yang tidak terduga. Universitas eks-IKIP kini bisa membuka program non-kependidikan, yang mengubah fokus dan alokasi sumber daya secara fundamental. Yang dulunya 100% fokus pada pendidikan guru, kini terpecah perhatiannya ke berbagai bidang.
Dr. Sunaryo Kartadinata, mantan Rektor UPI, pernah mengungkapkan kekhawatirannya: “Konversi IKIP memang memberikan kebebasan, tapi juga mengaburkan misi utama kita sebagai pencetak guru.” Kekhawatiran yang terbukti tepat ketika kita melihat kondisi hari ini.
Yang lebih ironis, era “modernisasi” ini justru membuka pintu bagi proliferasi FKIP di hampir setiap universitas dan sekolah tinggi. Jika dulu ada pembatasan ketat siapa yang boleh mencetak guru, kini hampir semua institusi pendidikan tinggi merasa berhak memiliki FKIP—seolah-olah mencetak guru semudah mencetak karcis parkir.
Liberalisasi Tanpa Batas: Era LPTK Terbuka (2000-Sekarang)
Selanjutnya, memasuki milenium baru, Indonesia mengalami apa yang bisa disebut sebagai “demokrasi pendidikan” dalam bentuk yang paling ekstrem. Sistem yang dulunya eksklusif dan terkontrol kini menjadi terbuka bagi semua institusi yang memenuhi persyaratan administratif minimal—yang sayangnya sering kali sangat minimal.
Merujuk data Kemendikbudristek 2023 menunjukkan realitas yang mengejutkan: lebih dari 400 LPTK memproduksi sekitar 300.000 lulusan FKIP per tahun, sementara kebutuhan guru baru nasional hanya sekitar 50.000. Artinya, 250.000 lulusan—setara dengan populasi Kota Balikpapan—terpaksa mencari peruntungan di luar profesi yang mereka pelajari selama empat tahun.
Pak Sutomo, pensiunan dosen IKIP Jakarta (kini UNJ), yang saya temui tahun lalu, menggambarkan perubahan ini dengan analogi yang menyentuh: “Dulu, kami seperti pemilik bengkel spesialis Mercedes-Benz. Pelanggan sedikit, tapi setiap mobil yang keluar dari bengkel kami dijamin kualitasnya. Sekarang? Pasar dipenuhi bengkel umum yang ngaku bisa servis semua merk. Hasilnya? Mercedes-Benz diperlakukan sama seperti sepeda motor butut.”
Liberalisasi ini menciptakan paradoks yang familiar: semakin banyak “bengkel guru” yang buka, semakin rendah kualitas “produk” yang dihasilkan. Kompetisi yang seharusnya mendorong inovasi justru memicu _race to the bottom_ dalam hal standar dan kualitas.
Pembelajaran dari Masa Lalu: “Mundur” Yang Maju
Ada kebijaksanaan dalam pitutur Jawa: “yen ora iso maju maneh, yo mundur sik ora popo” (kalau tidak bisa maju lagi, ya mundur dulu saja tidak apa-apa). Dalam konteks sistem pendidikan guru Indonesia, “mundur” ke sistem yang lebih terkontrol bukanlah kemunduran, melainkan koreksi arah yang diperlukan.
Era PTPG dan IKIP menunjukkan bahwa kontrol kualitas dalam pendidikan guru bukan hambatan, melainkan prasyarat. Ketika hanya empat PTPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, setiap lulusan memiliki jaminan kualitas dan prospek karir yang jelas. Ketika hanya sebelas IKIP yang mencetak guru, profesi guru masih dihormati dan diinginkan.
Bandingkan dengan era sekarang, di mana “demokratisasi” pendidikan guru justru menciptakan devaluasi massal terhadap profesi ini. Guru honor dengan gaji 500 ribu per bulan bukan anomali, melainkan norma baru yang menyedihkan.
Singapura dan China, seperti yang dibahas dalam esai sebelumnya, memahami bahwa kualitas guru dimulai dari kontrol sistem produksinya. Mereka tidak malu menerapkan sistem otoritas yang ketat—hanya institusi tertentu yang boleh mencetak guru. Hasilnya? Profesi guru dihormati dan digaji layak.
Finlandia: Pelajaran dari Negeri yang “Mundur” untuk Maju
Finlandia memberikan pelajaran menarik tentang keberanian untuk “mundur” demi kemajuan yang sejati. Pada 1970-an, Finlandia memiliki sistem pendidikan guru yang relatif terbuka. Namun, menyadari bahwa hal ini tidak menghasilkan kualitas optimal, mereka berani melakukan reformasi radikal.
Kini, hanya 10% pelamar terbaik yang diterima di fakultas pendidikan Finlandia. Guru wajib bergelar S2, dan proses seleksinya lebih ketat daripada masuk fakultas kedokteran. Hasilnya? Finlandia menjadi rujukan pendidikan dunia, dan guru di sana dihormati setara dengan dokter atau insinyur.
Seperti yang dikatakan Pasi Sahlberg, mantan direktur pendidikan Finlandia: “Kita mundur dari sistem terbuka menuju sistem selektif, bukan karena elitis, tapi karena kita menghormati profesi guru dan masa depan anak-anak kita.”
Nostalgia Produktif: Belajar dari Era IKIP
Generasi yang mengalami era IKIP masih mengingat bagaimana rasanya bangga menjadi mahasiswa lembaga pendidikan guru. Ada rasa kekhususan, ada jaminan kualitas, ada prospek karir yang jelas. Mahasiswa IKIP Jakarta tidak merasa “kalah gengsi” dibanding mahasiswa UI, karena mereka tahu bahwa institusi mereka memiliki misi mulia dan reputasi yang solid.
Prof. Dr. Dedi Supriadi, yang pernah menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dalam wawancaranya tahun 2018 mengenang: “Era IKIP adalah era ketika menjadi guru masih dianggap profesi terhormat. Lulusan IKIP tidak perlu khawatir soal pekerjaan, karena sistem sudah menjamin penyerapan mereka dengan gaji yang layak.”
Nostalgia ini bukan sekadar romantisasi masa lalu, tapi refleksi kritis tentang apa yang hilang dari sistem pendidikan guru kita. Dalam mengejar “modernisasi” dan “liberalisasi,” kita justru kehilangan esensi: kontrol kualitas dan tanggung jawab sistemik.
Jalan Mundur yang Progresif: Solusi untuk Indonesia
Jadi, solusi untuk masalah oversupply guru Indonesia mungkin terdengar kontroversial: kembali ke sistem otoritas yang terbatas seperti era PTPG/IKIP, dengan penyesuaian sesuai konteks zaman.
Pertama, terapkan sistem “Normal University” seperti di China. Hanya universitas dengan track record, fasilitas, dan komitmen terbukti yang boleh membuka program pendidikan guru. Universitas lain? Silakan fokus pada keunggulan masing-masing.
Kedua, batasi jumlah LPTK secara bertahap. Dari 400+ LPTK saat ini, bisa dikurangi menjadi 50-100 institusi terpilih yang tersebar strategis sesuai kebutuhan regional. Moratorium pembukaan FKIP baru harus diterapkan hingga rasio supply-demand kembali seimbang.
Ketiga, kembalikan sistem job guarantee seperti era IKIP. Setiap LPTK yang mencetak guru harus memiliki jaringan penyaluran lulusan yang konkret, bukan sekadar “melepas ke alam bebas” setelah wisuda.
Keempat, perkuat sistem sertifikasi dan standar kompetensi. Seperti profesi dokter atau engineer yang memiliki ujian kompetensi nasional, guru juga harus melalui uji kelayakan yang ketat sebelum diizinkan mengajar.
Refleksi
Indonesia hari ini berada di persimpangan: terus melanjutkan sistem liberal yang terbukti menghasilkan oversupply dan devaluasi profesi guru, atau berani “mundur” ke sistem kontrol yang lebih ketat demi menjamin kualitas dan martabat profesi.
Keberanian untuk mundur ini bukan tanda kekalahan, melainkan kematangan dalam berpikir sistemik. Seperti yang dikatakan Sun Tzu dalam Art of War: “Kadang-kadang, mundur satu langkah adalah strategi untuk maju sepuluh langkah.” Dalam konteks pendidikan guru, mundur ke sistem kontrol yang ketat adalah strategi untuk maju menuju kualitas pendidikan yang lebih baik.
Negara-negara maju seperti Finlandia, Singapura, dan China tidak malu menerapkan sistem selektif dan terkontrol dalam pendidikan guru. Mereka memahami bahwa profesi guru terlalu penting untuk diserahkan kepada mekanisme pasar bebas yang tidak teratur.
Penutup
Yang menjadi catatan penting dari tulisan ini, sejarah evolusi sistem pendidikan guru Indonesia mengajarkan satu hal penting: tidak semua perubahan adalah kemajuan, dan tidak semua kemajuan memerlukan perubahan radikal. Kadang-kadang, kemajuan sejati justru datang dari keberanian untuk kembali ke prinsip-prinsip dasar yang terbukti efektif.
Era PTPG dan IKIP bukan masa yang sempurna, tapi mereka memiliki satu hal yang hilang dari sistem kita hari ini: tanggung jawab sistemik terhadap kualitas dan masa depan profesi guru. Dalam era yang terobsesi dengan “disruption” dan “innovation,” kita lupa bahwa beberapa hal fundamental justru tidak boleh di-disrupt.
Pertanyaan untuk kita semua: sanggupkah Indonesia belajar dari sejarahnya sendiri? Beranikah kita “mundur” ke sistem yang lebih terkontrol demi menjamin masa depan pendidikan yang lebih baik? Ataukah kita akan terus terjebak dalam ilusi kemajuan yang sejatinya adalah kemunduran berkedok modernisasi?
Pilihan ada di tangan kita. Masa depan guru Indonesia—dan dengan demikian masa depan pendidikan bangsa—bergantung pada keberanian kita untuk belajar dari masa lalu, mengakui kesalahan sistem saat ini, dan berani melakukan koreksi arah yang fundamental.
Karena seperti yang dikatakan pepatah Minang: “balik ka pangka, luruih ka muaro” (kembali ke pangkal, lurus ke muara). Untuk mencapai tujuan yang lurus, kadang kita perlu kembali dulu ke pangkal yang benar.
“Dalam dunia yang terobsesi dengan perubahan, keberanian untuk tidak berubah—atau bahkan mundur ke hal yang terbukti benar—kadang adalah bentuk kemajuan yang paling sejati.”