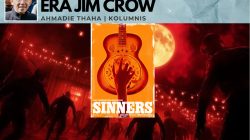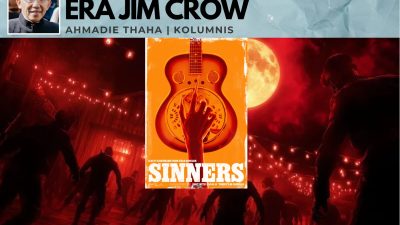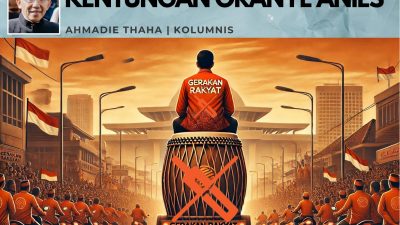Catatan Cak AT
Kalau politik luar negeri itu permainan catur, maka keputusan Presiden Prabowo Subianto meneken akta Board of Peace (BoP, Dewan Perdamaian) adalah langkah “skak” yang membuat banyak penonton di tribun mendadak menahan napas.
Terutama para kiai dan pimpinan ormas Islam, yang dahi mereka berkerut serempak seperti papan tulis penuh coretan dosen killer. Mereka riuh menyatakan penolakan atas keikutsertaan Indonesia dalam BoP bentukan Donald Trump.
Riuh itu wajar, tentu saja. Gaza bukan papan latihan, Palestina bukan pion cadangan. Maka, ketika ormas-ormas Islam dipanggil datang untuk diberi paparan, Istana pun berubah serasa ruang sidang skripsi tingkat doktoral.
Hampir lima puluh pimpinan ormas duduk anteng, sementara sang Presiden — dengan tenang khas prajurit lama — memaparkan argumen. Ia tidak menjual mimpi, apalagi janji surga diplomatik.
Kalimat Prabowo sederhana, nyaris datar: kita masuk bukan untuk jadi pengikut, melainkan pemain. Baginya, lebih baik punya kursi di dalam ruangan daripada berteriak dari luar pagar sambil berharap pintu terbuka karena iba.
Para tokoh ormas pun melunak ketika ada jaminan yang diselipkan Prabowo, seperti tombol darurat di kokpit pesawat: jika BoP berubah menjadi panggung legitimasi penindasan, Indonesia siap angkat kaki. Mundur terhormat. _Sayonara._
Jaminan ini penting, sebab sebagian keberatan ormas — yang disampaikan antara lain melalui Majelis Ulama Indonesia — bukan perkara remeh. Mereka paham, sejarah Palestina terlalu sering dipenuhi forum internasional yang ramai di awal, sunyi di akhir.
Lalu mengapa tetap nekat masuk ke kolam yang keruh, licin, dan beraroma busuk kepentingan? Jawabannya, yang tak pernah diungkap Prabowo, mengerucut pada satu nama yang kelicinannya menyaingi belut sawah berminyak: Benjamin Netanyahu.
Bagi Netanyahu, perdamaian bukan tujuan, melainkan variabel yang bisa diutak-atik. Rencana 20 poin Trump di tangannya berubah seperti cat air kehujanan: gambarnya masih ada, tapi maknanya luntur.
Sejak gencatan senjata 10 Oktober, ia memainkan jurus favoritnya — ingkar janji secara sistematis. Saat dunia berharap bantuan kemanusiaan mengalir, hampir lima ratus warga Palestina justru meregang nyawa.
Saat musim dingin menggigit seperti sekarang, monster itu menahan karavan tempat berlindung, hingga bayi-bayi di Gaza mati bukan oleh peluru, melainkan oleh dingin. Dalam kamus Netanyahu, kemanusiaan hanyalah hambatan logistik.
Manusia di Gaza baginya bukan siapa-siapa. Tak heran ia gerah dengan gagasan Dewan Perdamaian. Struktur berlapis yang dirancang Trump — komite eksekutif, komite Palestina, jenderal AS sebagai kepala pasukan stabilisasi — secara halus mencoba mencabut hak veto tak tertulis Netanyahu atas masa depan Gaza.
Lebih menyebalkan lagi bagi Netanyahu, Trump mulai bicara fase kedua perdamaian, setelah fase pertama tukar-menukar tahanan selesai: penarikan pasukan Israel dan rekonstruksi. Bagi Netanyahu, itu alarm bahaya.
Maka lahirlah dari oatknya kelicikan tingkat tinggi bernama “syarat di dalam syarat”. Perlintasan Rafah jadi contoh klasik. Trump mengutus Jared Kushner dan Steve Witkoff, berharap pintu kemanusiaan dibuka.
Namun Netanyahu menolak kecuali satu prasyarat dipenuhi, yaitu penyerahan tahanan terakhir janazah warga Israel. Begitu jazanah ketemu, dan prasyarat itu beres dalam 24 jam, dunia menunggu: apakah truk bantuan masuk?
Ternyata tidak. Netanyahu tak sepenuhnya membuka perlintasan Rafah. Yang dibuka hanyalah jalur pejalan kaki, terbatas pula. Truk bantuan tak boleh masuk. Ini bukan diplomasi; ini seni menghina logika internasional sambil tetap memakai jas resmi.
Sementara ruang-ruang rapat ber-AC sibuk berdiskusi, sekitar enam puluh persen Gaza telah diratakan. Parit-parit digali bukan untuk bertahan, melainkan memastikan warga tak kembali. Strategi _scorched earth_ dibungkus retorika keamanan.
Netanyahu tahu satu hal yang sering luput dari politisi sipil: kelelahan adalah senjata. Dunia bisa bosan, media bisa pindah isu, dan simpati bisa menguap. Maka siapa pun yang mencoba membantu Palestina akan berhadapan dengan tembok syarat, veto, dan alasan keamanan yang elastis seperti karet gelang.
Di titik ini, langkah Prabowo masuk BoP perlu dibaca dengan kacamata strategi, bukan emosi sesaat. Seorang jenderal tak pernah masuk “medan perang” tanpa rencana keluar.
Bergabung dengan BoP bukan berarti menyerahkan prinsip, melainkan memasuki papan catur untuk membaca niat lawan dari jarak dekat. Menghadapi Netanyahu tak cukup dengan slogan moral. Dibutuhkan kesabaran, tekanan kolektif, dan keberanian menarik diri ketika proses berubah menjadi alat penindasan.
Paradoksnya, dunia sering percaya perdamaian lahir dari niat baik semata. Padahal sejarah berulang kali mengingatkan: perdamaian justru lahir dari kewaspadaan terhadap niat buruk yang disamarkan.
Gaza hari ini adalah cermin pahit — rencana damai yang dijalankan tampak indah di atas kertas, tapi disabotase oleh kepentingan politik Netanyahu yang berusaha mempertahankan hidup dan kekuasaannya dari konflik.
Karena itu, masuknya Indonesia ke BoP bukan sekadar soal reputasi diplomatik, melainkan kejernihan membaca musuh.
Barangkali di situlah taruhan Prabowo: lebih baik berada di gelanggang untuk menilai apakah papan ini masih bisa diselamatkan, daripada berteriak dari luar sambil membiarkan Netanyahu bermain sendirian.
Sejarah kelak tak akan menilai siapa yang paling lantang bersumpah atas nama damai, melainkan siapa yang berani keluar ketika damai hanya menjadi topeng.
Netanyahu sedang bermain catur dengan niat menghabiskan papan — menolak peran Turki dan Qatar, menolak pasukan asing, bahkan membangun perlintasan baru di samping Rafah yang sepenuhnya ia kendalikan. Tujuannya satu: kendali mutlak, entah sampai kapan.
Maka, keikutsertaan Indonesia bisa dibaca sebagai upaya memegang kerah baju proses ini agar tak sepenuhnya disetir satu pihak. Diplomasi dari dalam, sambil mengetuk meja bila perlu.
Jika Trump sungguh ingin rencananya berhasil, ia harus membuktikan satu hal: mampu menjinakkan Netanyahu, satu-satunya orang yang berkepentingan agar perang tak pernah benar-benar usai demi menyelamatkan karier politiknya sendiri.
Pelajaran pahit Gaza sederhana tapi kejam: maut tak menunggu hasil rapat. Sementara kita berbincang, artileri bisa kembali berbunyi.
Indonesia kini meniti jembatan yang dibangun Trump, sementara di bawahnya Netanyahu sibuk menggergaji tiangnya.
Harapannya satu — Presiden kita bukan hanya pandai masuk, tetapi juga berani keluar dengan kepala tegak jika perdamaian yang dijanjikan ternyata hanya fatamorgana di atas puing-puing Gaza.
Sebab pada akhirnya, kredibilitas bangsa tidak diukur dari berapa banyak akta yang ditandatangani, melainkan dari seberapa nyata kemerdekaan yang kelak dirasakan anak-anak Palestina yang hari ini masih menggigil kedinginan.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 5/2/2026