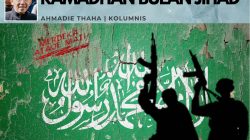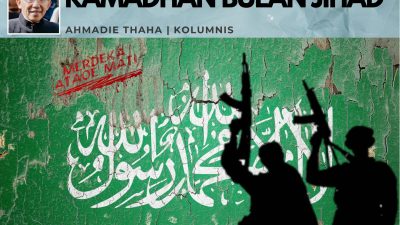Catatan Cak AT
Pagi itu, awal Januari 2026, ruang hotel tempat Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN PIM) berkumpul terasa lebih serius dari biasanya. Bukan karena karpetnya baru diganti atau kopinya mendadak pahit —kopi hotel selalu pahit secara ideologis— melainkan karena topik yang dibicarakan bukan sekadar agenda tahunan, melainkan fondasi cara kita bertengkar sebagai bangsa.
Saya yang selalu berjiwa wartawan pun ikut duduk di deretan kursi depan bersama rekan-rekan pengurus DN PIM. Dari kursi yang posisinya lebih tinggi 20 cm dari lantai, saya menyaksikan wajah rekan-rekan sesama wartawan yang setengah penasaran, setengah curiga, seolah bertanya dalam hati: “Ini negara mau maju atau mau mundur ke zaman pasal karet?”
Rekan-rekan DN PIM yang tampil —Prof Din Syamsuddin, Prof Philip K Wijaya yang datang jauh dari Surabaya, Prof R. Siti Zuhro, Prof Fadhilah Suralaga, Kak Ulla Nuchrowati Usman, Mbak Widya Murni, dan Umar Husin— tentu tak kaget dengan wajah-wajah itu. Mereka pernah muda, dan juga aktivis yang kenyang makan-minum garam kehidupan.
Pikiran yang dituangkan DN PIM kali ini, kalau boleh dibilang, bukan sekadar kumpulan kalimat yang rapi dan beradab, melainkan semacam alarm kebangsaan yang bunyinya sengaja tidak dibuat nyaring, tapi justru mengganggu nurani. Ia tidak berteriak seperti sirene ambulans, tetapi mengetuk pelan seperti tamu tua yang membawa kabar buruk.
Mereka hendak menyadarkan bahwa rumah kita masih berdiri, tapi fondasinya retak. Di satu sisi bangsa ini masih bisa bergotong royong saat banjir datang, mengumpulkan nasi bungkus dan doa; di sisi lain, banjir itu sendiri terus diproduksi ulang oleh keserakahan ekonomi yang difasilitasi negara dengan wajah santai.
DN PIM melihat, kita rajin mengutuk air yang meluap jadi banjir bandang yang memporak-porandakan apa saja, tapi terlalu sering memaafkan tangan-tangan yang menebang hutan. Maka wajar bila DN PIM tidak hanya bicara soal musibah, tetapi juga menunjuk siapa yang menjadikannya rutinitas —sebuah kritik yang sopan, namun menyengat seperti sindiran orang tua yang kecewa.
Lebih jauh, Pikiran DN PIM ini terasa seperti cermin besar yang diletakkan di tengah alun-alun politik nasional. Di situ terlihat jelas wajah ekonomi kita yang makin jauh dari Pasal 33, wajah hukum yang tampak tegas ke bawah tapi rabun ke atas, serta wajah persatuan yang retaknya disamarkan oleh slogan.
Ini bukan wacana pesimistis, justru optimistis dengan cara yang dewasa, tidak mabuk jargon, tidak silau pertumbuhan angka. DN PIM seakan berkata, Indonesia tidak kekurangan sumber daya, juga tidak kekurangan orang baik; yang kurang hanyalah keberanian kolektif untuk jujur pada kesalahan, adil dalam menata ulang arah, dan rendah hati untuk saling memaafkan tanpa menghapus keadilan.
Tahun 2026, dalam bingkai pikiran ini, bukan sekadar pergantian kalender—ia adalah ajakan untuk berhenti berbohong pada diri sendiri, agar bangsa ini tidak sekadar maju di pidato, tapi juga bermartabat di kenyataan.
Pesimisme tak ayal muncul lewat pertanyaan bernada sopan dari seorang rekan wartawan: Apa yang membuat DN PIM masih optimis dengan Indonesia dan pemimpin negeri ini? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya tidak bisa dijawab dengan kata mutiara kalender. Pertanyaan senada juga pernah disampaikan seorang profesor kepada saya, yang saya jawab sisi optimisnya.
Optimisme, jawab saya, bukan keyakinan bahwa negara ini bebas masalah, melainkan keyakinan bahwa kita masih mau repot membenahi masalah lewat aturan, bukan lewat teriakan. Dan bukti paling konkret adalah lahirnya dua kitab hukum perdana bangsa ini: Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mulai berlaku serentak 2 Januari 2026.
Dua kitab ini lahir bukan dalam suasana hening seperti kitab suci, melainkan dalam kegaduhan khas demokrasi tropis. Belasan orang dan kelompok langsung mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ada yang khawatir, ada yang curiga, ada pula yang —jujur saja— belum membaca pasalnya tapi sudah keburu marah.
Ini pemandangan yang sebenarnya sehat, meski riuh. Negara hukum memang tidak pernah sunyi; ia selalu berisik oleh tafsir. Di tengah kebisingan itulah muncul satu salah paham besar yang beredar lebih cepat daripada klarifikasinya: anggapan bahwa KUHP baru adalah alat untuk membungkam kritik.
Seolah-olah negara tiba-tiba anti-dikritik, alergi pada suara sumbang, dan ingin kembali ke masa ketika satire dianggap subversif. Padahal, jika mau sedikit saja membuka teks hukum —bukan hanya membuka emosi— ceritanya jauh lebih sederhana dan masuk akal. Tapi, itu bisa kita maklumi karena selama ini nyatanya negara memang terlalu sering membungkam para pengkritik.
Yusril Ihza Mahendra, dalam kapasitasnya sebagai Menko Kumham Imipas, sudah menjelaskan dengan gamblang: yang dipidana itu bukan kritik, melainkan penghinaan. Penjelasan yang sama juga diberikan menteri hukum, wakil menteri, dan aparat terkait.
Kritik adalah ekspresi pendapat yang ditujukan pada kebijakan, tindakan, atau kinerja pemerintah, dengan tujuan koreksi dan perbaikan. Sementara penghinaan adalah serangan terhadap kehormatan atau harkat martabat pribadi, yang niatnya bukan memperbaiki, melainkan merendahkan. Perbedaan ini bukan permainan kata; ia punya konsekuensi hukum yang sangat nyata.
Dalam KUHP baru, pasal-pasal yang sering dipersoalkan —Pasal 218 dan 219— secara eksplisit memberi pengecualian bagi perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Termasuk kritik, pendapat, atau penilaian terhadap kebijakan, tindakan, atau kinerja Presiden/Wakil Presiden, itu tidak dipidana.
Bahkan dijelaskan secara eksplisit bahwa unjuk rasa, pendapat yang berbeda, dan kritik betapa pun keras terhadap kebijakan presiden atau wakil presiden, itu tidak dianggap termasuk penyerangan kehormatan. Ini bukan tafsir politis, melainkan teks hukum yang bisa dibaca siapa saja, tanpa perlu gelar doktor atau kacamata ideologis.
Mari kita bedakan secara konkret, agar tidak terus berputar di kabut abstraksi. Jika seseorang menulis, “Kebijakan X pemerintah boros, tidak efektif, dan merugikan rakyat karena data A dan B menunjukkan anggaran membengkak tanpa hasil,” itu kritik. Kalimatnya mungkin pedas, tapi ia menyerang kebijakan, bukan martabat pribadi.
Bahkan jika ditutup dengan kalimat, “Presiden gagal memahami realitas lapangan,” itu tetap kritik, karena yang disasar adalah kapasitas dan keputusan, bukan kehormatan personal. Atau bahkan jika kalimat lebih pedas lagi, “Presiden hanya omon-omon karena janjinya begini-begitu namun tak pernah ditepati.”
Sebaliknya, jika seseorang berteriak di ruang publik, “Presiden itu bodoh, hina, dan pantas ditertawakan,” tanpa konteks kebijakan, tanpa argumen, tanpa kepentingan umum selain melampiaskan emosi, di situlah kita masuk wilayah penghinaan. Yang diserang bukan kebijakan, melainkan harga diri. Bukan koreksi, melainkan ejekan.
KUHP baru juga tidak bekerja dengan logika “tangkap dulu, pikir belakangan”. Delik penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara dikategorikan sebagai delik aduan. Artinya, penegak hukum tidak bisa bertindak tanpa adanya pengaduan resmi dari pihak yang merasa dihina. Negara tidak tiba-tiba bangun pagi lalu tersinggung sendiri. Ada mekanisme, ada rem, ada prosedur.
Ini poin penting yang sering hilang dalam diskusi yang terlalu emosional. Sejarahnya pun tidak dihapus begitu saja. Kita masih ingat bagaimana pasal penghinaan presiden dalam KUHP lama dibatalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 karena dianggap rawan multitafsir dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum serta kebebasan berekspresi.
Putusan MK itu menjadi pelajaran mahal, dan KUHP baru mencoba menjawab pelajaran tersebut dengan memberi batas yang lebih jelas, termasuk pengecualian untuk kepentingan umum. Apakah ia sempurna? Tentu tidak. Tapi ia jelas bukan kemunduran tanpa rem. Landasan konstitusional dan internasionalnya pun terang.
Kebebasan berekspresi dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Pasal 19 DUHAM, dan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia. Namun, semua instrumen itu juga mengakui bahwa kebebasan datang bersama tanggung jawab, terutama untuk menghormati hak dan nama baik orang lain.
Demokrasi bukan lisensi untuk menghina; ia adalah ruang untuk berdebat secara bermartabat.
Di ruang hotel itu, seperti rekan DN PIM yang lain, khususnya Prof Kyai Din Syamsuddin sebagai ketua, saya melihat kegelisahan sekaligus harapan. Kegelisahan karena hukum selalu ditakuti akan disalahgunakan, yang selama ini memang sering begitu. Harapan karena kita masih mau memperdebatkannya secara terbuka.
Optimisme saya bukan karena yakin semua aparat akan selalu adil —karena pengalaman justru sering berkata sebaliknya— melainkan karena mekanisme koreksi masih tersedia: dari kritik publik, pengawasan media, hingga uji materi di Mahkamah Konstitusi. Negara yang masih mau diuji adalah negara yang belum menyerah pada kekuasaan absolut.
Maka, ketika ada yang bertanya mengapa masih optimis, saya justru ingin membalik pertanyaannya: mengapa harus pesimistis hanya karena hukum mencoba membedakan kritik dari penghinaan? Bukankah kedewasaan demokrasi justru diukur dari kemampuan warganya mengkritik tanpa memaki, dan dari kemampuan negaranya menahan diri untuk tidak alergi pada kritik?
Dua kitab hukum ini mungkin belum sempurna, sebagaimana diakui sendiri oleh Yusril. Tapi kehadiran keduanya merupakan tanda bahwa republik sedang belajar berjalan dengan tongkatnya sendiri, bukan lagi bersandar pada warisan kolonial yang usang.
Walhasil, kritik yang jujur akan tetap hidup, karena ia dilindungi. Penghinaan yang sembrono akan tetap dipersoalkan, karena ia merusak ruang bersama. Di antara keduanya, kita belajar menjadi bangsa yang berani bicara tanpa kehilangan adab.
Dan mungkin, justru di situlah sisa optimisme paling masuk akal dari rekan-rekan DN PIM dan kita semua itu berada: bukan pada keyakinan bahwa negara ini bebas konflik, melainkan pada kesediaan kita mengelola konflik dengan nurani, akal sehat dan aturan.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 6/1/2026