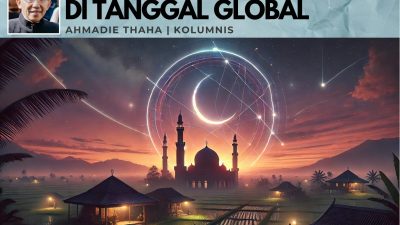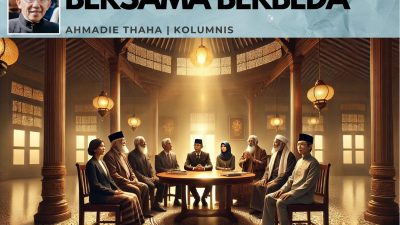Catatan Cak AT
Bersama Kyai Mudrik Qori dan rombongan guru Pondok Pesantren al-Ittifaqiah, pekan lalu saya datang ke kampus Madrasah TechnoNatura dengan perasaan biasa saja, tapi pulang dengan kepala yang penuh gejolak pikiran. Lokasi kampus madrasah ini di pinggir Kali Ciliwung, di antara perumahan yang tenang dan dekat Rumah Tahanan Militer Depok, Jawa Barat.
Itu bukan lokasi yang lazim untuk membayangkan “pangan masa depan”, apalagi pangan umat manusia. Tapi justru di situlah ironi pertama dimulai. Di halaman kampus itu, anak-anak madrasah tidak sedang menghafal definisi. Mereka sedang mengerjakan banyak proyek. Bukan proyek pura-pura, tapi proyek yang sungguh-sungguh memaksa akal bekerja dan tangan kotor.
Tema besar mereka tahun ini terdengar ambisius: pangan masa depan. Maka, di sebuah ruang besar, pipa-pipa transparan disusun melingkar seperti usus raksasa yang sedang mencerna cahaya. Di dalamnya mengalir berkilo-liter air kehijauan, hidup, berdenyut. Air itu berisi spirulina, ganggang alga yang namanya sering disebut-sebut sebagai “makanan para astronot”.
Untuk menggerakkan sistem itu, dipasang panel surya dengan daya sepuluh ribu watt. Sepuluh hari penuh, air terus mengalir, alga terus tumbuh, sampai akhirnya dipanen. Hasilnya bukan nasi, bukan roti, melainkan lembar-lembar hijau pekat yang jika dilihat sekilas tampak seperti hasil cetakan tinta yang terlalu bersemangat.
Itulah spirulina siap konsumsi. Cukup ambil satu-dua lembar, itu sudah cukup untuk kebutuhan nutrisi sehari. Spirulina memang kaya protein, mengandung asam amino esensial, vitamin, mineral, dan antioksidan. Ringkas, padat, efisien. Tak heran jika ia dipilih sebagai kandidat pangan astronot: ringan, bernutrisi, dan tidak cerewet minta lahan.
“Inilah makanan para astronot di ruang angkasa,” kata Dr. Riza Wahono, principal Madrasah TechnoNatura, sambil tersenyum tenang. Ia mengajar _design engineering_ dan robotika, tapi pagi itu ia sedang bicara tentang makanan masa depan dan keberlanjutan. Tema pangan masa depan dipilihnya sebagai tema utama bagi seluruh pembelajaran yang berbasis proyek di TechnoNatura.
Saya mengangguk kagum. Namun di titik itu pula muncul pertanyaan yang mengusik di benak saya: kalau untuk menumbuhkan segenggam spirulina saja kita perlu tabung, nutrisi terukur, panel surya 10.000 watt, dan disiplin teknis yang ketat, apakah ini benar-benar bisa menjadi solusi pangan manusia kebanyakan, khususnya di Indonesia?
Di situlah cerita berbelok. Pikiran saya melayang ke pangan-pangan alternatif lainnya. Dan ternyata, saya menemukan, selain spirulina yang futuristik itu, alam diam-diam menyimpan opsi yang jauh lebih sederhana, lebih murah, dan —ini yang paling menggelitik— sudah lama hidup di sekitar kita, tapi nyaris tak pernah kita anggap makanan.
Namanya Wolffia. Inilah salah satu dari tiga anggota keluarga _duckweed_. Di Indonesia, ia masuk kelompok yang sering disebut “paku air”, meski secara ilmiah ia bukan paku sejati. Dalam keluarga ini ada tiga nama yang sering tertukar nasib dan reputasinya. Yang paling sering disebut di video-video media sosial adalah azolla.
Azolla itu paku air sejati yang akrab dengan petani padi karena kemampuannya mengikat nitrogen dan menyuburkan tanah. Anggota keluarga _duckweed_ lainnya adalah Lemna, _duckweed_ sejati yang berdaun kecil dengan akar halus menggantung, mengapung di permukaan kolam dan sawah. Dan terakhir, yang paling ekstrem dan paling diremehkan, Wolffia, si telur air.
Wolffia unik. Tanaman ini memiliki bunga terkecil di dunia. Ukurannya sekitar satu milimeter, tanpa akar, tanpa batang, tanpa daun dalam pengertian yang kita kenal. Ia seperti titik hijau yang lupa membesar. Dalam kesederhanaannya ini, ia justeru dapat mengoptimasi nutrisi yang masuk dari atas dan bawah air.
Tapi jangan tertipu oleh ukurannya. Dalam tubuhnya yang nyaris tak terlihat itu, Wolffia menyimpan protein antara tiga puluh hingga empat puluh lima persen berat keringnya. Bayangkan, 45%! Hampir separuh tubuhnya adalah protein. Dan hampir separuhnya lagi adalah karbohidrat, cukup untuk kebutuhan tubuh.
Tak hanya itu. Profil asam aminonya lengkap. Rasanya netral. Teksturnya lembut. Ia bisa dimakan manusia, bukan sekadar pakan ikan, dan justru karena sifatnya yang jinak di lidah dan ramah di perut itulah Wolffia berpotensi masuk ke dapur manusia tanpa perlu rekayasa rasa berlebihan atau teknologi pengolahan yang rumit.
Di sinilah ironi kedua muncul. Tadi sudah saya sebutkan, untuk menumbuhkan spirulina di TechnoNatura, dibutuhkan teknologi tinggi dan energi besar. Sementara Wolffia, dengan kandungan protein yang tak kalah impresif, cukup air tawar dangkal, cahaya matahari, dan sedikit nutrisi.
Wolffia tidak butuh tanah untuk bisa hidup. Cukup ada air tawar dan matahari, serta sedikit tambahan nutrisi. Tidak butuh pupuk kimia rumit. Tidak butuh listrik sepuluh ribu watt. Ia tumbuh, berlipat ganda dalam waktu singkat, namun jika dibiarkan terlalu lama justru dianggap “mengotori” kolam.
Di beberapa negara Asia Tenggara, Wolffia sudah lama dimakan sebagai sayur. Di Thailand ia dikenal sebagai _khai nam_, telur air. Kita di Indonesia menyebutnya paku air, lalu berhenti berpikir sampai di situ. Padahal, jika ada satu pangan non-konvensional yang paling mungkin diadopsi manusia Indonesia tanpa lompatan teknologi ekstrem, Wolffia-lah kandidatnya.
Ia bisa dibudidayakan di kolam kecil, di sawah dangkal, bahkan di kolam terpal di halaman rumah. Ia bisa dipanen harian. Ia bisa dimasak seperti sayur, dikeringkan menjadi bubuk, atau dicampur ke makanan lain.
Tantangannya ada, tentu saja: air harus bersih, konsumsi harus dimasak untuk menurunkan oksalat, dan tidak dimakan berlebihan. Tapi tantangan itu masih jauh lebih ringan dibandingkan membangun reaktor spirulina berpanel surya raksasa di setiap desa.
Yang menarik, Wolffia justru dipelajari serius untuk pangan masa depan manusia di luar angkasa. Bukan karena ia eksotis, tapi karena ia efisien. Di ruang hampa pasar dan estetika, ketika satu-satunya tujuan adalah bertahan hidup, Wolffia dinilai apa adanya: mesin biologis kecil pengubah cahaya menjadi protein.
Betul, Wolffia dipelajari serius untuk pangan masa depan manusia ruang-ruang penelitian bio-teknologi, bahkan hingga luar angkasa. Dan ini bukan rumor YouTube atau klaim influencer pangan hijau, melainkan hasil riset lembaga-lembaga ilmiah kelas dunia.
Sejak dekade 1990-an, NASA sudah memasukkan keluarga _duckweed_ —termasuk Wolffia— dalam konsep _Controlled Ecological Life Support System_ (CELSS), sebuah sistem tertutup untuk menopang kehidupan manusia di misi jangka panjang.
Alasannya sederhana dan dingin: laju pertumbuhan Wolffia sangat cepat, efisiensi konversi cahaya ke protein tinggi, dan hampir seluruh biomassa dapat dimakan. Penelitian ini berlanjut hingga era modern.
Pada November 2023, perusahaan biotek pangan asal Israel GreenOnyx, bekerja sama dengan badan antariksa dan universitas riset, mengirim Wolffia globosa ke _International Space Station_ melalui misi kargo SpaceX CRS-29.
Tujuannya bukan romantika, melainkan uji keras: apakah Wolffia tetap tumbuh stabil dalam kondisi mikrogravitasi, bagaimana pola pembelahan selnya, dan apakah kandungan proteinnya berubah. Hasil awal yang dipublikasikan pasca-misi menunjukkan bahwa Wolffia tetap hidup, membelah, dan mempertahankan profil gizinya.
Bahkan karena ia tidak berakar, Wolffia relatif “tenang” menghadapi ketiadaan gravitasi dibanding tanaman darat. Sementara itu di Bumi, riset Wolffia telah lama dilakukan secara sistematis.
Wageningen University & Research di Belanda sejak awal 2010-an meneliti Wolffia sebagai sumber protein nabati alternatif, menemukan kandungan protein hingga 40% berat kering dengan komposisi asam amino esensial yang mendekati protein hewani.
Di Israel, Ben-Gurion University of the Negev bersama startup pangan melakukan uji keamanan dan bioavailabilitas Wolffia untuk konsumsi manusia, dengan hasil bahwa Wolffia aman dikonsumsi, mudah dicerna, dan stabil setelah dikeringkan.
Di Asia, riset-riset di Thailand dan Vietnam sejak awal 2000-an mencatat konsumsi tradisional Wolffia _(khai nam)_ tanpa dampak kesehatan serius, sekaligus menegaskan keunggulannya sebagai pangan air tawar tropis.
Jadi, ketika Wolffia disebut sebagai pangan masa depan, itu bukan karena ia eksotis atau “hijau”, melainkan karena ia sudah lulus serangkaian ujian ilmiah —di laboratorium, di kolam riset, hingga di luar angkasa— dan tetap berdiri sebagai kandidat pangan paling efisien yang pernah diuji manusia.
Di titik ini saya kembali teringat kampus TechnoNatura di pinggir Ciliwung. Anak-anak madrasah itu sedang belajar tentang masa depan dengan alat-alat canggih. Sementara di luar pagar kampus, di genangan air yang mungkin dianggap kotor, bisa jadi tumbuh Wolffia —pangan masa depan versi paling membumi. Yang satu membutuhkan panel surya sepuluh ribu watt, yang lain cukup matahari yang sudah Allah sediakan gratis sejak penciptaan.
Mungkin pelajaran terpenting dari Wolffia bukan soal gizinya saja, tapi soal cara kita memandang. Bahwa pangan masa depan tidak selalu datang dari laboratorium berkilau, tapi kadang mengapung diam-diam di air yang selama ini kita suruh bersih dan jernih. Bahwa sesuatu yang terlalu kecil sering kita singkirkan, padahal justru di situlah efisiensi bersembunyi.
Jika suatu hari Indonesia serius bicara ketahanan pangan, barangkali ia perlu menoleh sebentar ke bawah, ke kolam-kolam kecil, ke paku air yang tak punya nama populer. Siapa tahu, masa depan itu sedang menunggu, sekecil telur air, sambil terus berlipat ganda tanpa banyak bicara.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 23/12/2025