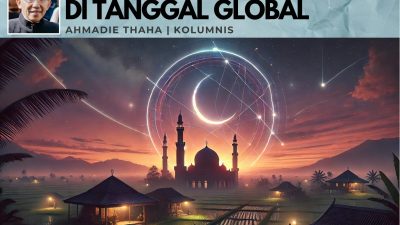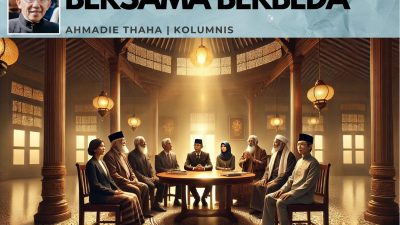Catatan Cak AT
Ada film yang ditonton untuk hiburan, ada film yang ditonton untuk menangis diam-diam di pojok bioskop, dan ada pula film yang —tanpa diminta— mengajak penonton berdiskusi serius sambil mengernyitkan dahi. Film _Mengejar Restu_ jelas masuk kategori terakhir.
Film yang sedang tayang di banyak layar lebar ini hadir sebagai drama religi keluarga yang tampak santun, lembut, penuh musik sendu. Tapi sekaligus ia menyimpan satu bom tema yang oleh banyak ulasan justru diputar haluannya: poligami.
Aneh memang. Film ini nyaris mustahil dibicarakan tanpa menyentuh poligami, tetapi justru tema itulah yang seolah diperlakukan seperti gajah di ruang tamu. Semua tahu ada, semua melihat jelas, tapi pura-pura tidak ada.
Barangkali ada kekhawatiran pragmatis mengapa banyak ulasan film di media menghindari soal inti ini: nanti penontonnya berkurang, nanti para istri melarang suaminya ikut nonton, nanti pulang dari bioskop ada dialog berbahaya, “Mah, kalau dalam kondisi tertentu….”
Padahal, menghindari pembahasan poligami dalam film ini sama janggalnya dengan membahas _Titanic_ tanpa menyebut kapal tenggelam. Dalam _Mengejar Restu_, poligami bukan sekadar bumbu konflik, melainkan poros cerita.
Faiz, sang tokoh utama, masuk ke pernikahan kedua bukan karena birahi atau cinta rahasia, melainkan oleh wasiat ayahnya, KH. Abdullah: pesantren harus dipimpin keturunan laki-laki. Di titik ini, naskah mulai menguji kesabaran penonton yang pernah bersentuhan dengan dunia pesantren, atau setidaknya pernah membaca berita.
Pertanyaannya sederhana, nyaris naif: sejak kapan kepemimpinan pesantren mensyaratkan kromosom Y? Dunia pesantren Indonesia —yang ratusan tahun usianya— justru kaya contoh kepemimpinan perempuan yang sah, kuat, dan berhasil.
Pondok Pesantren Ashriyah Parung di Bogor, misalnya, bukan sekadar hidup, tapi tumbuh besar di bawah kepemimpinan Dr. Hj. Umi Waheedah setelah wafatnya sang suami, Habib Saggaf bin Mahdi. Tidak runtuh, tidak chaos, tidak pula kehilangan legitimasi keumatan.
Pesantren lain pun demikian. Tak sedikit pesantren dipimpin oleh nyai, terutama setelah kepergian suami. Maka wasiat KH. Abdullah dalam film ini terasa lebih sebagai kebutuhan dramatik ketimbang refleksi realitas sosiologis pesantren.
Yang lebih menggelitik —atau menjengkelkan, tergantung sudut pandang— anak Kyai Abdullah sendiri adalah laki-laki. Ia ada. Ia hidup. Ia sah secara biologis dan sosial. Tetapi naskah memilih jalan berbelok tajam: bukan sang anak yang disiapkan, melainkan Faiz yang harus berpoligami. Di sini, logika cerita mulai menyerupai sandal tertukar di masjid —bisa dipakai, tapi terasa aneh dan tidak pas.
Dalam tradisi pesantren, inti keberlangsungan pendidikan bukanlah jenis kelamin, melainkan kaderisasi. Pesantren hidup karena sistem, bukan rahim. Pesantren yang gagal menyiapkan kader —entah laki-laki atau perempuan— akan tumbang bukan karena tak punya anak lelaki, tetapi karena tak punya visi.
Film ini melewatkan peluang besar untuk membahas isu kaderisasi pesantren secara lebih serius dan edukatif, lalu menggantinya dengan solusi instan: poligami sebagai jalan keluar struktural. Terlalu sederhana untuk persoalan yang sejatinya kompleks.
Ada satu hal lagi yang sebetulnya paling provokatif dari film ini, justru tersembunyi rapi di judulnya sendiri: “Mengejar Restu”. Restu siapa yang dikejar? Ini pertanyaan yang tampak sederhana, tapi sesungguhnya filosofis, bahkan teologis.
Apakah restu ayah —seorang kyai— yang wasiatnya diposisikan nyaris setara dalil? Ataukah restu istri pertama, yang dalam film ini digambarkan seperti malaikat penjaga pintu surga rumah tangga? Atau jangan-jangan restu mertua, keluarga besar, lingkungan pesantren, bahkan masyarakat yang kelak akan memberi label “sah” atau “tidak pantas” atas sebuah poligami?
Film ini seperti sengaja membiarkan pertanyaan itu menggantung, seolah restu adalah satu benda abstrak yang bisa dikejar seperti layangan putus di sore hari: semua berlari, tapi tak jelas siapa pemiliknya.
Dalam perspektif Islam, persoalan “restu” dalam nikah —terutama nikah lagi— sebenarnya tidak sesederhana judul film. Secara fikih, syarat sah nikah tidak mencantumkan restu orang tua bagi laki-laki dewasa, apalagi restu mertua. Yang menjadi pusat etika justru keadilan, kemampuan, dan tanggung jawab, bukan sekadar izin simbolik.
Al-Qur’an bahkan memberi peringatan keras: jika khawatir tidak mampu berlaku adil, maka satu saja sudah cukup. Ini bukan anjuran poligami, melainkan rem kerasnya. Maka, ketika poligami dipresentasikan sebagai proyek “mengejar restu”, film ini tanpa sadar menggeser pusat moral dari tanggung jawab substantif ke legitimasi sosial. Seolah-olah jika semua sudah merestui, maka persoalan selesai.
Padahal dalam Islam, restu manusia —betapapun pentingnya secara sosial— tidak pernah menggantikan pertanggungjawaban etis di hadapan Tuhan. Di titik inilah judul film itu justru menjadi cermin ironis: yang dikejar ramai-ramai adalah restu, sementara beban keadilan —yang jauh lebih berat— justru luput dikejar dengan kesungguhan yang sama.
Namun, harus diakui, secara teknis _Mengejar Restu_ digarap dengan rapi. Sinematografinya bersih, pergerakan kameranya halus, tata warna dan pencahayaan mendukung suasana religius yang tenang dan khidmat.
Tata suara dan _scoring_ film ini bekerja efektif mengaduk emosi, bahkan menolong beberapa dialog yang terasa kaku agar tetap sampai ke hati penonton. Pada titik klimaks, musik dan gambar bersatu padu, membuat bioskop mendadak hening —jenis keheningan yang hanya bisa diciptakan oleh drama keluarga yang menyentuh saraf empati.
Masalahnya kembali ke skenario. Dialog kerap terdengar seperti ceramah yang disalin rapi, bukan percakapan manusia yang berdarah dan bernapas. Pace cerita terlalu tergesa, seolah takut penonton keburu berpikir terlalu jauh.
Perubahan emosi terjadi cepat, keputusan besar “berpoligami” diambil instan. Dania, istri pertama, digambarkan terlalu suci —begitu ikhlas, begitu lapang, nyaris tak menyisakan ruang psikologis yang manusiawi. Ia bukan lagi perempuan, melainkan metafora kesabaran.
Bandingkan dengan drama klasik seperti _Kuch Kuch Hota Hai_, yang membangun penerimaan emosional bertahun-tahun lamanya. Di sana, keikhlasan lahir dari proses panjang, bukan dari satu adegan klimaks. Andai _Mengejar Restu_ berani memperlambat langkah, memberi ruang luka, ragu, marah, dan negosiasi batin, konflik poligaminya justru akan terasa lebih jujur dan mendidik.
Beberapa set-up konflik lain pun terasa dipaksakan, seperti adegan anak Bella yang sakit dan cara Faiz-Dania masuk rumah tanpa izin, atau karakter mantan suami yang klise dan terlalu mudah ditebak. Semua ini menunjukkan naskah yang ingin cepat sampai ke tujuan, tanpa sabar menyiapkan jalan.
Walakin, _Mengejar Restu_ adalah film yang baik secara teknis, cukup menghibur, dan emosional, tetapi belum sepenuhnya berani jujur secara intelektual. Ia menyentuh poligami, tapi tidak membedahnya tuntas. Ia berbicara pesantren, tapi luput dari logika kaderisasi. Ia ingin religius, tapi kadang terjebak romantisasi solusi instan.
Mungkin di situlah refleksi terpentingnya. Dalam kehidupan nyata, masalah keluarga, pesantren, dan kepemimpinan tidak pernah sesederhana wasiat film. Tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan menikah lagi, sebagaimana tidak semua konflik bisa diredakan oleh musik sendu dan air mata ikhlas. Kadang yang dibutuhkan bukan restu tambahan, melainkan keberanian untuk berpikir ulang.
Dan barangkali, justru di situlah fungsi film ini: bukan untuk menormalisasi poligami, tetapi untuk memancing kita bertanya —apakah kita sedang mengejar restu, atau sedang lari dari kerja-kerja kaderisasi dan keadilan yang lebih sulit?
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 21/12/2025