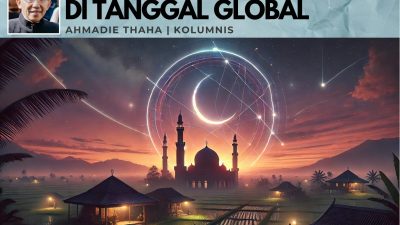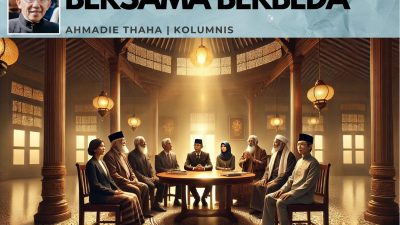Catatan Cak AT
Konon, sejarah itu seperti foto lama yang warnanya mulai pudar: semakin kabur, semakin banyak orang merasa berhak menafsir. Tetapi siapa sangka, di balik sebuah foto yang mengguncang nurani dunia tersimpan juga drama kemanusiaan lain: drama tentang siapa sebenarnya yang menekan tombol kamera pada detik yang memisahkan manusia dari mitos.
Foto itu tentang seorang bocah perempuan berlari telanjang sambil menjerit menahan panas napalm pada 1972. Bagi yang belum pernah melihatnya, selembar foto “Napalm Girl” sebenarnya bukan sekadar gambar. Ia jeritan visual yang membeku, gambar yang membuat siapa pun tercekak oleh luka yang bahkan tak menimpa dirinya.
Hanya foto hitam-putih, memang. Di tengah jalan desa Trảng Bàng yang berdebu di Vietnam, tampak seorang anak perempuan sembilan tahun berlari tanpa sehelai kain—bukan karena kemiskinan, tetapi karena bajunya habis terbakar napalm, menempel ke kulit hingga harus ia lepaskan.
Bom itu baru saja dijatuhkan oleh pesawat Vietnam Selatan dalam operasi yang diarahkan penasihat militer Amerika Serikat —sebuah kolaborasi perang yang tak pernah akrab dengan kata “perikemanusiaan”.
Wajah anak itu meringis, mulutnya terbuka mengeluarkan teriakan yang tak kita dengar tetapi terasa menggema hingga sekarang. Di sampingnya, anak-anak lain ikut berlari; sebagian menangis, sebagian terpaku oleh teror yang tak mereka pahami.
Di belakang mereka, tentara Vietnam Selatan berjalan dengan langkah bingung, sementara gumpalan asap hitam menutup langit seperti tirai penutup bab tragedi Asia Tenggara.
Foto itu tidak hanya menggambarkan perang. Ia cermin yang memaksa dunia —termasuk kita hari ini— bertanya: sampai kapan anak-anak harus membayar keputusan orang dewasa? Ia menjadi pengingat bahwa setiap konflik, dari Vietnam hingga Gaza, selalu dimulai dari sebuah kebijakan, tetapi selalu berakhir di tubuh rapuh seorang anak.
Ironisnya, foto yang memotret tragedi itu justru melahirkan tragedi lain: ia menjadikan seorang fotografer amatir sebagai legenda global, dan di saat bersamaan —jika benar demikian adanya— membiarkan sang pemotret asli tersesat dalam lorong sunyi diaspora, hidup di California, bekerja mengembangkan film Hollywood, jauh dari kilatan Pulitzer yang katanya lahir dari jepretannya. Dramatis? Tentu. Realistis? Sangat Vietnam.
Film dokumenter _The Stringer: The Man Who Took The Photo_, yang beredar dari server Netflix, muncul seperti surat kaleng dari masa perang. Ia mengusik memori tentang Amerika Serikat yang hegemonis dan menjajah, kini memecah keheningan dan mengundang debat para penjaga memori global.
Film itu mempertanyakan sesuatu yang selama lima puluh tahun lebih tak disentuh: benarkah Nick Út, fotografer _Associated Press_ (AP), yang mengambil foto “Napalm Girl”? Ataukah justru sang pemilik asli momen itu adalah seorang _stringer_ lokal, Nguyễn Thành Nghệ, yang dibayar 20 dolar per foto —bukan dengan kehormatan, melainkan dengan pelupaan?
Bagi penggemar sejarah, ini seperti menemukan titik aneh pada peta lama. AP bersikeras: _credit remains with Nick Ut_. Sementara film tersebut menghadirkan fakta yang dikemas elegan dengan model 3D, analisis posisi kamera, dan log buku film yang diklaim pernah mencantumkan nama Nghệ sebelum sang editor legendaris, Horst Faas, memintanya diganti.
Dan di sinilah tragedi kecil itu bermula. Carl Robinson, editor foto AP yang kini renta, ingin membersihkan hati nurani. Seperti adegan film noir: seorang lelaki tua memegang beban seumur hidup, mencari seseorang di ranjang rumah sakit —bukan untuk menagih hutang, tetapi untuk meminta maaf karena telah mencuri sejarah orang lain.
Mungkin juga itu semacam tobat atas sejarah kelam Amerika Serikat. _”I feel bad that we stole your name,”_ katanya. Kalimat seperti ini tak pernah muncul dalam buku pelajaran; ia lahir dari rasa bersalah yang memar selama setengah abad.
Hal lain yang sering luput adalah bahwa foto itu sendiri, setelah tiba di meja redaksi AP, melesat menjadi senjata moral dunia. Dalam hitungan jam, gambar Kim Phúc itu dikirim via satelit ke Tokyo, Hong Kong, New York, London, dan Paris. Media besar — _New York Times, Washington Post, Le Monde, Süddeutsche Zeitung_ —memajangnya di halaman depan tanpa perlu rapat panjang.
Foto itu tidak meminta izin untuk mengguncang dunia. Ia langsung membelah opini publik Amerika tentang perang Vietnam. Nixon bahkan sempat curiga foto itu palsu. Tetapi di hadapan kulit terbakar seorang anak kecil, teori konspirasi yang dicurigainya pun otomatis kehilangan suara.
Foto itu memenangkan Pulitzer —hadiah yang mengubah karier seorang fotografer, dan mungkin juga mengubur nama yang lain.
Bersamaan itu, dunia tersentak melihat kezaliman yang tersembunyi di balik bom napalm. Senjata yang diciptakan universitas ternama dan militer AS itu menempel pada kulit seperti kutukan kimia, membakar apa saja: pohon, rumah, orang dewasa, bayi, termasuk Kim Phúc kecil yang abadi dalam gambar itu.
Lalu mari kita lihat kembali medan perang itu melalui rekonstruksi teknis film _The Stringer_. Model 3D para penyelidik memperlihatkan betapa jauh posisi Nick Út dari lokasi jepretan. Jarak yang membuatnya mustahil tiba tepat waktu —kecuali ia berlari seperti atlet olimpiade yang kerasukan malaikat pencatat sejarah.
Namun kesaksian lain tetap membela Út: beberapa jurnalis mengaku melihatnya memotret. Sayangnya, tak ada negatif film, tak ada kontak _sheet_, tak ada arsip teknis yang memastikan nama Nghệ sebagai pemotret asli.
Antara fisika dan kesaksian, kebenaran pun berubah seperti asap napalm: mengepul, menyengat, tapi tak pernah bisa benar-benar digenggam.
Ada pula drama domestik yang getir. Sang istri Nghệ, kecewa karena suaminya tak diberi kredit, merobek cetakan foto yang diberikan AP sebagai “souvenir”. Siapa sangka, kemarahan dapur ternyata bisa lebih tajam dari editorial kantor berita internasional. Ironisnya, foto yang ia hancurkan mungkin satu-satunya bukti sejarah yang kini hilang.
Setelah itu, Nghệ meninggalkan dunia fotografi perang. Ia hidup sunyi, bekerja di ruang gelap Hollywood, memproses film-film blockbuster —sementara foto paling ikonis yang mungkin ia ambil justru menghantui dunia tanpa namanya.
Dunia internasional kini terbelah. AP bersikukuh, _World Press Photo_ menangguhkan atribusi, sementara publik merayakan romantisme membela yang kecil, yang tertindas, yang terlupakan. Kim Phúc sendiri percaya foto itu diambil Nick Út —sebuah keyakinan yang diwariskan keluarganya, meski ingatannya sendiri kabur oleh trauma.
Kesimpulan investigasi _World Press Photo_ sendiri justru menambah lapisan ironi pada drama ini. Setelah menelaah ulang bukti visual, rekonstruksi teknis, dan kesaksian yang berserakan seperti serpihan sejarah yang tak mau disusun rapi, lembaga itu menyatakan bahwa —jika pengujian dibatasi pada dua nama, Út dan Nghệ— maka bukti yang ada lebih condong ke Nghệ.
Apalagi, ada indikasi kuat bahwa di lokasi kejadian terdapat lebih dari dua fotografer, sebuah fakta yang membuat peta atribusi semakin kabur seperti foto gelap yang tak tersentuh developer. Karena tak ada satu pun bukti yang benar-benar final, dan karena kebenaran justru makin berbiak ketika dikejar, World Press Photo memilih langkah yang paling jujur: menangguhkan kredit foto yang juga diberi judul oleh media: “The Terror of War”.
Dalam bahasa paling sederhana, lembaga itu berkata, “Kami belum tahu siapa pemotretnya —dan justru karena itu, kami tak ingin berpura-pura tahu.” Sebuah ketegasan yang jarang lahir dari institusi besar, tetapi mungkin itulah cara sejarah mengingatkan bahwa ikon global pun bisa berdiri di atas fondasi yang retak.
Dokumenter ini akhirnya bukan semata tentang siapa menekan tombol kamera, tetapi tentang siapa yang diberi suara dalam sejarah, dan siapa yang didiamkan. Di medan perang, peluru tak peduli siapa wartawan penuh waktu, siapa _stringer_. Tetapi kredit foto —itulah panggung peradaban, yang lampunya tak pernah adil menyinari semua pemain.
Jika benar Nghệ adalah sang pemotret asli, maka napalm bukan hanya membakar kulit seorang anak kecil, tetapi juga menghanguskan jejak sebuah nama dari lembar sejarah. Dan jika Nick Út tetaplah fotografernya, dokumenter ini mengingatkan: kebenaran pun dapat digugat lima puluh tahun setelah kamera dimatikan.
Sejarah, rupanya, tak pernah selesai. Ia seperti film dokumenter yang editannya terus berubah, dipotong, diperpanjang, atau ditambah testimoni baru.
Dalam ketidakpastian itulah manusia belajar rendah hati: bahwa kebenaran bukan trofi, melainkan perjalanan. Bahwa sebuah foto bisa menjadi ikon dunia, tetapi manusia yang memotretnya tetap rapuh, tetap mencari ruang didengar, tetap berharap dikenang.
Dan mungkin, di situlah hikmahnya: tragedi perang melahirkan foto yang mampu mengakhiri perang paling brutal; tragedi penghapusan nama melahirkan film yang mengingatkan bahwa setiap manusia —sekecil apa pun perannya— berhak mendapatkan kembali suaranya.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 7/12/2025