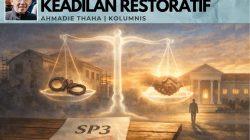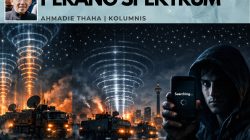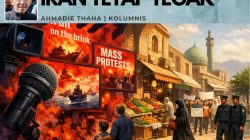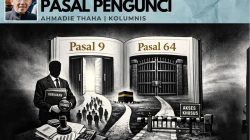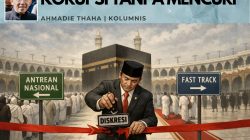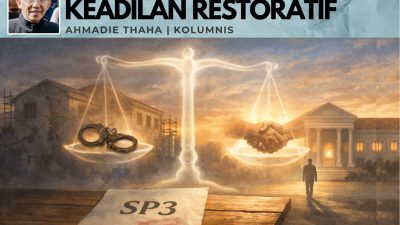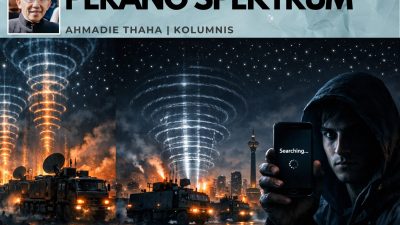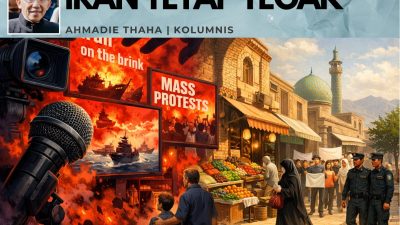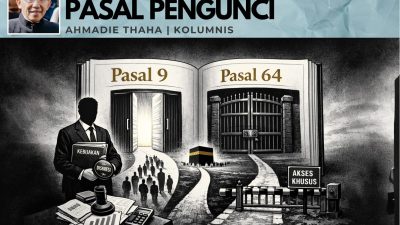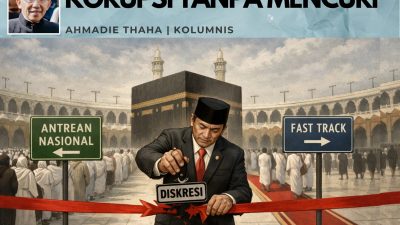Catatan Cak AT
Konon, di tengah hiruk-pikuk kabinet baru yang lebih mirip rombongan ekspedisi Himalaya —ada yang sibuk pasang tenda kementerian, ada yang gelagapan cari oksigen politik— muncul satu sosok yang tampak seperti anomali: Yusril Ihza Mahendra.
Dia seorang Menteri Koordinator yang, alih-alih mengumpulkan _briefing_ dari staf ahli, malah berkumpul dengan jamaah untuk khutbah Jumat. Lelaki asal Belitung ini, kata sebagian orang, kalau berdiri di mimbar, seperti bayang-bayang Natsir Muda sedang mampir sebentar dari masa lalu.
Benar saja. Pertengahan November kemarin, ketika sebagian pejabat sudah sibuk memikirkan akhir tahun —proyek belum cair, laporan belum rapi— Yusril justru berdiri di mimbar Masjid Al-Hijrah, di lingkungan kantornya di kompleks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta.
Tempat yang sehari-hari penuh dengan urusan paspor, deportasi, dan tetek-bengek pemasyarakatan itu tiap Jumat mendadak jadi tempat kontemplasi moral. Kalau sistem imigrasi sering membuat orang hilang kesabaran, khutbah justru mengajak jamaah mencari kesabaran yang mungkin hilang.
Judul khutbahnya sederhana tapi menyentak: Untuk Apa Kita Menjadi Orang Baik? Ini semacam pertanyaan yang biasanya hanya muncul saat kita baru saja ditilang padahal sudah pakai helm dobel atau ketika melihat maling koruptor senyum-senyum di TV.
Yusril memadatkan khutbahnya dengan pengamatan yang begitu manusiawi: hidup sering berperilaku absurd. Orang baik kadang tumbang lebih cepat, sementara orang jahat bisa hidup nyaman, penuh _endorsement_ duniawi. Seolah-olah alam semesta sedang bercanda, atau mungkin server kehidupan sedang _error_.
Namun di sinilah Yusril mengunci pesan moralnya. Katanya, kalau ukuran hidup hanya hasil dunia, tentu pertanyaan itu jadi menyakitkan. Tapi Islam —sejak masa awalnya— sudah menancapkan dua jangkar yang membuat manusia tidak hanyut oleh drama dunia: iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir.
Dua pilar yang membuat seseorang tetap memilih baik meskipun dunia sering tidak ramah pada kebaikan.
Yusril memulai khutbahnya mengacu _Tarikh al-Thabari_, dengan memutar ulang babak-babak sejarah Islam yang sering kita dengar tetapi jarang kita resapi dengan serius. Apalagi di tengah suasana kantor yang pintunya lebih sering berderit karena keluar-masuknya berkas daripada keluar-masuknya hidayah.
Ia mengingatkan jamaah pada masa ketika Nabi Muhammad SAW memulai perjuangannya dengan pengikut yang bisa dihitung lebih cepat dari jumlah staf ahli Menko. Mereka segelintir orang Makkah yang setia meski diejek, dicemooh, dikepung hoaks, dan diboikot sosial-ekonomi oleh elit Quraisy.
Kemudian ia mengisahkan bagaimana tekanan itu memaksa Nabi meminta sekitar seratus Muslim berhijrah ke Habasyah (Ethiopia), mencari perlindungan pada Raja Najasyi yang adil. Ini sebuah eksodus kecil tapi monumental, seperti rapat kabinet yang beralih dari gedung A ke gedung B.
Hijrah itu bukan sekadar “pindah lokasi”, melainkan strategi moral dan spiritual: bukti bahwa kebaikan butuh tempat yang memungkinkan ia tumbuh. Nabi tak hanya mengajarkan sabar dan tawakal, tapi juga mencari ekosistem di mana kebenaran tak dibungkam dan keadilan mendapat ruang bernapas.
Dari pengalaman hijrah ke Habasyah itulah Nabi kemudian pada akhirnya memutuskan mengajak seluruh warga Muslim berhijrah ke Madinah. Bagi Yusril, perjalanan umat Islam adalah perjalanan membangun sistem yang adil —bukan hanya membangun pribadi yang saleh.
Dengan cerdik Yusril kemudian menarik garis merah dari peristiwa itu ke inti khutbahnya: bahwa menjadi orang baik saja tidak cukup jika struktur sosial dan politik tidak menopang. Sama seperti kaum Muslim awal yang saleh tetapi tetap tertindas di Makkah karena sistemnya bengkok.
Begitu pula halnya hari ini. Individu sebaik apa pun akan kesulitan hidup jika hukum pincang, birokrasi gemuk namun lelet, dan lembaga tidak mampu melindungi yang benar. Maka tugas generasi sekarang sama seperti generasi sahabat dulu: mempertahankan kebaikan diri, sekaligus memperjuangkan ekosistem yang membuat kebaikan tidak mati muda.
Khutbah itu pun bergerak. Dari moralitas individu menuju peta besar kehidupan sosial. Di sini letak menariknya. Yusril bukan sekadar da’i, ia Menko yang mengurusi hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan —empat bidang yang kalau satu saja macet, rasa keadilan masyarakat bisa masuk ICU.
Maka saat ia mengatakan bahwa “dalam sistem yang buruk, orang baik bisa frustrasi; dalam sistem yang baik, orang jahat dipaksa jadi baik,” itu bukan kalimat filosofis belaka. Itu pengalaman birokrasi, diagnosis teknokrat yang sudah makan asam garam regulasi dari zaman Orde Baru sampai era Reformasi.
Bayangkan analogi sederhana dari kehidupan sehari-hari yang ia sampaikan: kalau kantin kementerian kacau, antrean panjang, pembayaran berbelit, dan makanannya suka habis duluan, maka orang paling sabar pun lama-lama ingin teriak juga.
Tapi kalau sistem kantin rapi, antre jelas, makanan terdistribusi baik, maka orang yang tadinya suka serobot pun terpaksa ikut tertib. Kebaikan, kata Yusril, bukan hanya soal karakter pribadi; ia butuh ekosistem. Ia harus diperjuangkan dalam bentuk aturan, lembaga, dan konsistensi.
Di titik ini khutbah itu terasa sebagai dua khutbah dalam satu tubuh: khutbah masjid dan khutbah negara. Di satu sisi ia mengingatkan jamaah bahwa kebaikan pribadi tetap prioritas. Di sisi lain, sebagai pejabat, ia sedang menegaskan PR besar pemerintah.
Negara mesti membangun sistem yang tak membuat orang baik merasa sia-sia. Ketika Yusril mengatakan bahwa kebaikan harus tegak dalam sistem yang benar, ia seolah sedang menebalkan garis batas tanggung jawab: “Kita boleh saleh di sajadah, tapi negara harus saleh di meja kebijakan.”
Dan betapa ironi negeri ini sering kita temukan di situ: banyak orang baik tersangkut aturan tak masuk akal, sementara orang nakal pandai berenang di celah regulasi. Maka khutbah Yusril, meskipun dibungkus tutur lembut, sejatinya adalah kritik halus.
Khutbahnya juga pengingat keras bahwa moralitas publik tidak akan tegak jika sistemnya bengkok. Di akhir khutbahnya ia kemudian mengajak jamaah melihat kebaikan secara lebih luas. Ia menegaskan bahwa menjadi baik bukan jaminan mulusnya hidup.
Bahwa pahala bukan selalu berupa jabatan atau proyek, tapi ketenangan hati dan kejelasan tujuan. Bahwa dunia memang sering tidak adil, tapi keadilan akhirat pasti. Dan bahwa tugas manusia adalah terus memperbaiki diri —dan bila punya kuasa, memperbaiki sistem.
Pada akhirnya kita diajak merenung: orang baik pun bisa kalah, bisa lelah, bisa kecewa. Tapi justru karena dunia sering kacau, kebaikan jadi relevan. Tanpa kebaikan, hidup kita hanya tinggal perebutan antrean dan rebutan mikrofon. Namun tanpa sistem yang benar, kebaikan pun hanya jadi berita harian yang cepat menguap.
Maka mungkin itu alasan Yusril berdiri di mimbar dan di ruang rapat sekaligus. Di satu tempat ia mengajak orang menjadi baik, di tempat lain ia mengupayakan agar kebaikan itu punya rumah, atap, dan pagar. Sebab orang baik tanpa sistem hanya jadi legenda; tapi sistem baik tanpa orang baik hanya jadi alat baru bagi mereka yang licik.
Dan dari khutbah hari itu, kita belajar satu hal: dunia boleh tak adil, tapi manusia tidak boleh menyerah untuk menjadi baik —dan bertugas memastikan agar sistem ikut membaik. Dari tragedi ketidakadilan lahir hikmah, dari antrean panjang lahir kesabaran, dan dari khutbah singkat di hari Jumat lahir renungan panjang tentang bagaimana negara seharusnya berjalan.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 28/11/2025