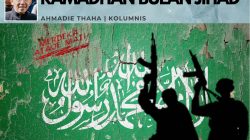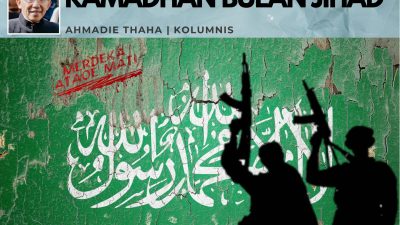Catatan Cak AT
Alangkah ajaibnya republik ini. Kita pikir kita sudah cukup sering menonton drama hukum kelas wahid, lengkap dengan adegan ketukan palu, sorot kamera, dan narasi “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ternyata belum. Masih jauh dari kelas dua, apalagi dari kelas satu.
Kemarin (20/11/2025), rakyat diberi tontonan episode baru: bagaimana sebuah putusan bisa lebih absurd dari sinetron mistis jam sebelas malam, ketika logika ikut menyerah dan lari terbirit-birit meninggalkan ruang sidang pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Rakyat menyaksikan sidang itu via streaming.
Coba tengok nasib Mbak Ira Puspadewi dan kawan-kawan. Semua fakta persidangan —iya, semua— menunjukkan mereka tidak mengambil sepeser pun uang negara. Duit ASDP tidak bocor, tidak digerogoti, tidak dijilat, bahkan tidak dicolek. Semua hakim mengakui itu.
Hakim juga membuktikan, mereka tidak berniat korupsi, tidak menerima hadiah yang berbau sogokan, dan tidak main mata dengan siapa pun. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba Mbak Ira dkk dikalungi vonis seolah-olah sedang memakai kalung mutiara palsu: tak cocok, tak nyambung, dan tak ada gunanya.
Lebih lucu lagi: ketua majelis hakim, yang biasanya jadi kompas moral sebuah persidangan, justru disingkirkan pendapatnya. Hakim ketua ini, bernama Sunoto, bilang begini soal pokok perkara yang diadili: “Ini keputusan bisnis. Tidak ada mens rea. Tidak ada kerugian negara yang terbukti.”
Tetapi dua hakim lainnya tampaknya sedang memakai Google Translate untuk menerjemahkan justice, dan hasilnya berubah jadi “asal ketok”. Padahal, pendapat Sunoto itu bukan pendapat kacangan. Ia bicara tentang Business Judgement Rule (BJR).
Anda pun tahu, BJR itu sebuah konsep hukum tingkat tinggi, pusat gravitasi tata kelola korporasi modern, semacam vitamin otak bagi direksi yang harus mengambil keputusan berisiko demi berkembangnya perusahaan. Tapi rupanya di ruang sidang itu, BJR dianggap seperti pengumuman liburan: bisa diabaikan.
Lalu muncullah alasan paling heroik dari majelis: bahwa para terdakwa telah “memperkaya orang lain”. Sebuah frasa dalam UU Tipikor yang diperlakukan seolah-olah “atau” di situ artinya “pokoknya salah”. Padahal, “atau” dalam bahasa hukum itu pilihan. Bukan paket lengkap. Bukan combo meal.
Dan celakanya, hakim tidak bisa menjelaskan bagaimana orang lain yang diperkaya itu? Siapa pula? Pemilik perusahaan? Loh, kapal-kapalnya justru diambil-alih ASDP, bahkan juga perusahaannya. Kalau begitu, siapa? Jin penjaga dermaga? Atau siluman akuntansi yang muncul tiap akhir tahun fiskal?
Dalam ilmu ekonomi paling dasar —yang bahkan pedagang cilok pun paham— setiap orang berhak mendapatkan keuntungan dari jual-beli. Ini _fundamental law of jualan_. Beli rumah 1 miliar, rawat 5 tahun, lalu jual 2 miliar. Itu bukan dosa. Itu wajar.
Yang tidak wajar adalah kalau saya jual rumah 1 miliar, lalu disuruh jual rugi 700 juta. Itu bukan transaksi, itu amal jariyah terpaksa.
Begitu juga dengan kapal-kapal yang, buka hanya dibeli, tapi diakuisisi ASDP. Kapal itu bukan ikan di freezer, tapi aset yang dirawat, dipelihara, dihitung depresiasi dan residual value-nya.
Usia 20–30 tahun bukan berarti wajib dijual murah. Kalau begitu, mobil klasik milik kolektor di Eropa yang harganya 12 kali lipat harusnya ditangkap KPK juga, karena “memperkaya orang lain”.
Tapi logika semacam itu rupanya sedang cuti. Hakim-hakim itu lebih sibuk main bisnis pasal, bukan bisnis akal sehat. Barangkali memang benar, logika mereka sedang diparkir di dengkul kaki, dan sayangnya dengkul itu pun tampaknya tidak protes.
Dan betapa ironisnya, vonis kali ini diberikan oleh majelis yang tahu persis bahwa hukuman semacam ini akan membuat para direksi BUMN se-Indonesia kelak gemeteran sebelum mengambil keputusan bisnis.
Mereka akan berpikir begini: “Kalau untung, dipuji. Kalau buntung, dipenjara.” Lah, bagaimana perusahaan bisa berkembang kalau direksinya dipaksa jadi cenayang?
Andaikan para hakim itu pernah berjualan cilok atau kacang rebus di pinggir jalan, mereka pasti paham bahwa orang berjualan tidak pernah menargetkan rugi. Hanya semut yang mau menjual gula lebih murah daripada harga gula —karena dia tinggal di sarangnya dan tidak butuh biaya operasional.
Penonton pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Rasa-rasanya membacakan putusan semacam ini hanya cocok apabila para hakimnya memakai jubah bertuliskan “Plot Twist”.
-000-
Awal mulanya, perlu pembaca tahu: perkara yang menjerat Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, bukan perkara kecil yang jatuh dari langit. Bersamanya ikut terseret Muhammad Yusuf Hadi (Direktur Komersial dan Pelayanan) dan Harry Muhammad Adhi Caksono (Direktur Perencanaan dan Pengembangan).
Tiga nama ini adalah wajah-wajah yang pernah lama mengelola ASDP, perusahaan penyeberangan terbesar di negeri kepulauan ini —bukan komplotan gelap yang menunggu celah di gudang keuangan.
Tuduhan yang diarahkan kepada mereka pun sebenarnya sederhana: bahwa dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi kapal-kapal milik PT Jembatan Nusantara (JN), mereka “merugikan keuangan negara” dan “memperkaya orang lain” sampai Rp 1,27 Triliun.
Tetapi membaca dakwaan itu rasanya seperti menelan bubur panas: mengandung sesuatu, tapi tidak jelas apa yang sebenarnya.
Kasus ini bermula ketika ASDP mengambil langkah bisnis besar: akuisisi perusahaan JN beserta kapal-kapalnya. Keputusan itu disetujui manajemen, didukung kajian. Bahkan, ini bukan rumor, pernah dipuji juga oleh kementerian teknis sebagai sebuah langkah strategis.
Tetapi entah bagaimana, langkah bisnis yang dulu dianggap visioner itu kini diperlakukan seperti adegan pencurian sandal di masjid. Jaksa menilai ada kerugian negara sampai Rp 1,27 triliun.
Dan, angka itu sendiri berasal dari hitungan yang dilakukan oleh akuntan forensik internal KPK dan seorang dosen teknik perkapalan —keduanya tidak memiliki sertifikat resmi penilai publik. Bayangkan, menilai kapal tanpa izin menilai, sama seperti menimbang sapi tanpa timbangan, lalu memaksa semua orang percaya hasilnya.
Penahanan terhadap ketiga terdakwa berlangsung cukup panjang dan melelahkan. Mereka bolak-balik dari rumah tahanan ke ruang sidang, sering tegang menghadapi perdebatan teknis antara jaksa dan penasihat hukum.
Sidang demi sidang berjalan seperti serial TV berseason-season, lengkap dengan jeda-jeda yang membuat publik semakin bingung: apakah kasus ini perkara hukum, perkara ilmu perkapalan, atau perkara keuletan menunggu? Yang jelas, proses persidangan begitu panjang, cukup untuk membuat pengunjung sidang hapal nomor kursi dan jalur masuk hakim.
Di dalam ruang sidang, fakta-fakta janggal bermunculan seperti jamur tumbuh sehabis hujan. Tidak ada uang negara yang mengalir ke kantong pribadi terdakwa. Tidak ada tindakan memperkaya diri sendiri. Tidak ada pemberian hadiah. Tidak ada mens rea.
Dan —yang paling lucu —bahkan pihak yang disebut “diperkaya” itu pun perusahaannya diakuisisi ASDP, sehingga mereka tidak sedang menikmati bonus, tetapi menyerahkan asetnya.
Namun jaksa tetap berkeras bahwa keuntungan wajar dari jual-beli aset adalah “memperkaya orang lain”. Kalau logika seperti itu dipakai untuk semua transaksi, maka setiap pembeli bakso yang menguntungkan penjualnya lima ribu per mangkuk pun bisa dianggap “memperkaya orang lain”.
Persidangan sempat beberapa kali memanas, terutama ketika penasihat hukum mempersoalkan perhitungan kerugian negara yang tidak memenuhi standar profesi. Di titik inilah publik mulai melihat ada yang dipaksakan.
Saksi-saksi ahli yang tidak sepenuhnya kompeten, tafsir pasal yang diperlakukan seperti plastisin mainan, dan dorongan agar perkara ini tetap berlanjut meski pondasi hukumnya goyah.
Bahkan dissenting opinion hakim ketua memperlihatkan betapa majelis sebenarnya tidak solid dalam memahami fakta-fakta yang terungkap. Ketegangan itu tidak tampak di layar TV, tapi semua yang hadir di ruang sidang merasakannya: aroma sebuah kasus yang dibawa terlalu jauh dari rel nalar.
-000-
Tapi, baiklah. Di balik semua hiruk-pikuk ini, ada semacam pelajaran pahit yang terasa manis di ujung lidah: kebenaran tidak selalu menang cepat, tapi ia tidak akan kelelahan dikejar waktu.
Kadang yang adil tampak kalah, tapi kekalahan itulah yang justru membuka jalan kemenangan berikutnya.
Kadang vonis menjadi tragedi, tapi tragedi itu sendiri yang mengajarkan bangsa ini: bahwa hukum tanpa logika hanyalah teks kosong yang menunggu ditertawakan sejarah.
Dan bila akhirnya sejarah itu tiba, barangkali kita akan mengenang hari ini sebagai momen ketika nalar publik lebih jernih daripada nalar hukum, dan ketika ketegaran beberapa orang —termasuk seorang hakim bernama Sunoto— menjadi saksi bahwa integritas masih punya ruang, meski sempit, di Republik yang semakin absurd ini.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 21/11/2025