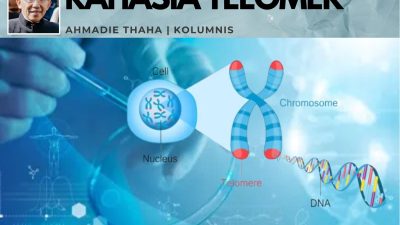Catatan Cak AT
Coba bayangkan dunia yang tak lagi belepotan dengan oli, tak lagi bau bensin, tak ada suara genset meraung di tengah malam, dan tagihan listrik tak lagi membuat jantung berdebar seperti menunggu hasil ujian. Betapa indah dunia yang energinya hijau, bikin lingkungan tak lagi tercemar.
Itulah dunia di mana energi bukan lagi kutukan, tapi keberkahan. Sebuah dunia yang, kata laporan hasil kolaborasi _World Economic Forum (WEF)_ dan _Frontiers (2025)_, bisa dicapai lewat tiga kunci: amonia hijau, panas bumi modular, dan mobil yang bisa balas dendam ke PLN.
Ya, kita sedang bicara tentang masa depan energi — tapi bukan yang berasap dan bising. Ini tentang listrik yang datang dari langit dan tanah, bukan dari cerobong dan tambang.
Mari mulai dari yang paling tidak wangi: amonia. Selama ini, amonia dikenal sebagai bahan pupuk dan bau kandang ayam. Tapi kini, di mata WEF, ia sedang naik pangkat jadi bahan bakar bersih masa depan.
Dalam bentuk barunya, _green ammonia_, ia tak lagi dibuat dari gas alam atau batu bara, melainkan dari air dan udara — dengan bantuan listrik dari sumber terbarukan seperti surya atau angin.
Bayangkan: air dipecah jadi hidrogen dan oksigen, lalu hidrogen itu digabungkan dengan nitrogen dari udara untuk membentuk amonia. Tanpa emisi karbon, tanpa boros energi fosil.
Amonia hijau ini bisa disimpan, diangkut, bahkan dibakar di mesin kapal, pabrik baja, dan pembangkit listrik. Tapi dengan satu syarat: manusia berhenti mencampuri reaksi kimia itu dengan kerakusan.
Di Jepang dan Norwegia, kapal bertenaga amonia sudah berlayar. Di Australia, proyek _green ammonia hub_ sedang dibangun di tengah gurun, menyiapkan ekspor energi bersih untuk dunia.
Di Indonesia? Kita masih mengimpor pupuk dengan harga yang membuat petani menanam padi sambil mengeluh. Padahal, kita punya laut, udara, dan sinar matahari yang gratis — hanya saja belum kita ubah jadi “bahan bakar langit”.
-000-
Sekarang mari menunduk ke bawah tanah: _modular geothermal_, si anak kandung bumi yang pemalu tapi setia. Panas bumi sebenarnya bukan hal baru. Kita sudah tahu gunung berapi bisa memanaskan air jadi uap dan menggerakkan turbin.
Tapi teknologi _modular geothermal_ membawa ide baru. Ia bukan lagi proyek raksasa dengan biaya miliaran, tapi pembangkit kecil yang bisa dipasang di mana saja, bahkan di halaman belakang pabrik atau kampung.
Bayangkan kalau setiap kota kecil punya “sumur panas bumi” mini yang bisa menyuplai listrik tanpa asap, tanpa batu bara, tanpa PLTU. Energi tak lagi datang dari jauh, tapi dari tanah di bawah kaki sendiri. Tak perlu tunggu izin proyek raksasa; cukup butuh kemauan politik dan keberanian teknis.
Islandia sudah hidup dengan listrik dari bumi sejak lama. Kenya kini menjadi pelopor panas bumi di Afrika. Dan di Indonesia — negeri seribu gunung api — potensi panas bumi kita seolah menunggu dengan sabar sambil mendengus asap: “Kapan kalian sadar aku ini bukan ancaman, tapi karunia?”
-000-
Lalu ada teknologi ketiga — yang paling dekat dengan keseharian kita: _bi-directional EV charging_. Kalau dulu mobil listrik cuma bisa disetrum, sekarang ia bisa “balas menyetrum balik.” Mobil bukan lagi hanya alat transportasi, tapi bank energi berjalan.
Ketika mobil di-charge malam hari, ia menyimpan listrik dari jaringan listrik _(grid)_. Tapi di siang hari, saat jaringan butuh tambahan daya, mobil bisa mengembalikannya ke rumah, kantor, atau bahkan ke PLN. Ini bukan mobil biasa — ini mobil yang punya dendam sosial: “Dulu aku disetrum, sekarang giliran aku menyetrum balik.”
Di Jepang, rumah tangga sudah mulai memanfaatkan mobil listrik untuk _back-up energy_. Di Eropa, sistem _vehicle-to-grid_ menjadi bagian dari tata kota cerdas. Bayangkan kalau ini terjadi di Indonesia: mobil tetangga yang dulunya sekadar gaya hidup, kini bisa jadi penyelamat listrik ketika PLN padam. Mobil bukan lagi simbol kemewahan, tapi kemandirian energi.
-000-
Tiga teknologi ini — amonia hijau, panas bumi modular, dan mobil penyimpan energi — bukan sekadar ide futuristik. Ketiganya sedang mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana: energi tidak hilang, hanya perlu diputar untuk dihadirkan dengan niat baik.
Selama ini, kita menyalakan lampu dengan mematikan masa depan — membakar batu bara, gas, dan minyak tanpa memikirkan gantinya. Tapi kini, bumi mulai menagih. Suhu naik, laut mendidih, badai datang bergiliran. Alam sudah capek jadi korban _power supply_ yang rakus.
WEF dan Frontiers menyebut transformasi energi ini sebagai “jalan menuju _resilient planet_” — planet yang tahan banting, bukan planet yang pasrah. Tapi teknologi hanyalah setengahnya. Separuh lainnya adalah kesadaran manusia untuk tidak menjadikan energi sebagai candu.
Coba renungkan: dulu kita berpikir listrik adalah simbol kemajuan. Sekarang, listrik adalah ukuran kebijaksanaan.
Karena dunia yang benar-benar maju bukanlah dunia yang paling terang di malam hari, tapi dunia yang paling hemat menyalakan siangnya. Dan ketika kita bisa menyalakan dunia tanpa membakar masa depan, mungkin baru di situlah kita benar-benar bisa menyebut diri kita “makhluk beradab.”
Jadi, lain kali ketika Anda menyalakan lampu, menyalakan mobil, atau menyalakan kompor — bayangkan juga, sedang menyalakan harapan bumi. Karena energi sejati bukan berasal dari langit atau tanah, tapi dari hati yang tidak ingin membakar masa depan.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 29/10/2025