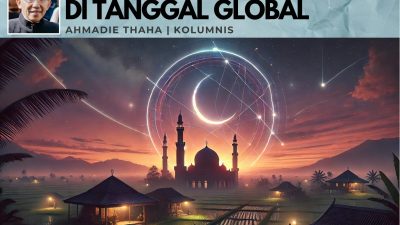Catatan Cak AT
Pagi itu, aula besar Kejaksaan Agung berubah jadi panggung drama yang tak kalah megah dari final Indonesia’s Got Talent. Bedanya, kali ini talenta yang ditampilkan bukan penyanyi atau pesulap, melainkan uang — ya, uang sungguhan — menggunung setinggi hampir dua meter.
Tumpukan rupiah merah itu dibungkus plastik bening, berkilau di bawah lampu sorot yang biasanya hanya menyinari tersangka. Presiden Prabowo Subianto berdiri di depan “gunung uang” itu dengan tatapan antara takjub dan curiga. Di sebelahnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Dia tampak bangga — kali ini seperti penyelam yang baru menemukan harta karun di Teluk Jakarta. Sementara di depan mereka, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menatap kalkulator dalam kepalanya, mencoba menebak: berapa bunga yang bisa dihasilkan dari Rp13 triliun kalau disimpan di deposito negara?
Suasana khidmat, tapi absurd. Para pejabat berdiri tegak di depan “monumen rupiah” itu seolah menatap simbol kebajikan yang lahir dari dosa. Kamera-kamera media berdesakan, blitz menyala bertubi-tubi, seakan semua ingin menangkap satu momen yang bisa jadi ikon pemerintahan bersih.
Atau, paling tidak, bersih dari sisa-sisa uang CPO yang sempat disedot tiga korporasi besar lewat jalur korupsi. Dari Wilmar Group sendiri, negara berhasil menarik Rp11,8 triliun; dua grup lain baru menyetor sebagian, mungkin masih sibuk menjual aset yang belum digadaikan.
Perjalanan uang itu tak mudah: melewati penyitaan panjang, gugatan hukum, dan negosiasi yang bisa jadi lebih alot dari rapat RAPBN. Kata Jaksa Agung, total kerugian negara mencapai Rp17,7 triliun — dan baru Rp13,2 triliun yang berhasil “pulang kampung.”
Sisanya masih banyak, sekitar empat triliun, entah di mana rimbanya. Mungkin sedang transit di surga pajak luar negeri, atau sekadar menunggu penerbangan lanjutan menuju rekening aman.
Peristiwa semacam ini jarang terjadi. Dulu, saat uang korupsi BLBI atau Jiwasraya dikembalikan, yang diserahkan biasanya cuma berkas dan janji. Kali ini berbeda: uangnya benar-benar hadir — bukan angka di laporan audit yang indah tapi tak berwujud.
Sutikno, Direktur Penuntutan Jampidsus, bahkan menegaskan, “Yang kita lihat ini cuma dua koma empat triliun. Kalau tiga belas triliun dibawa semua, gedungnya bisa ambruk.” Bayangkan, uang yang katanya ringan karena kertas, ternyata beratnya bisa meruntuhkan bangunan sekokoh Kejaksaan Agung.
Mungkin itu sebabnya tumpukan uang itu diletakkan dekat tangga — agar mudah ditata, tapi juga mudah ditatap. Simbol bahwa meniti kejujuran di negeri ini memang berat, tapi bisa dimulai dari anak tangga pertama yang bertuliskan: “uang sitaan korupsi.”
Pertunjukan ini, kata pejabat, adalah “simbol keberhasilan hukum.” Kado bagi rakyat menjelang setahun pemerintahan Prabowo Subianto. Dunia berdecak kagum, katanya. Tapi di tengah decak kagum itu, ada suara lirih bertanya: “Kalau ini yang kembali, yang tak kembali berapa?”
Dalam drama uang berlapis plastik itu, Prabowo berandai-andai, jika uang sebanyak itu dipakai untuk kampung nelayan, mungkin itu cukup untuk bikin 600 yang diprogram pemerintah. Tapi muncul pula ide paling nyeleneh tapi menggoda: bagaimana kalau satu triliunnya diserahkan ke media?
Usul ini datang dari analis politik yang dikenal santai tapi cerdas, Hendri Satrio — Hensat. “Pak Prabowo, dari 13 triliun itu, kasih satu triliun aja ke media,” ujarnya santai, tapi serius. Biarlah Rp 12 triliun untuk kampung nelayan, tapi sisakan juga untuk peduli pada media yang sedang kembang-kempis.
Alasan Hensat mulia: agar media bisa hidup, wartawan tak lagi di-PHK, dan demokrasi tetap bernapas. Argumen yang terdengar seperti doa di tengah reda iklan, sekaligus menunjukkan kepedulian tinggi pada dunia pers dan rekan-rekan wartawan yang terhimpit dunia yang telah berubah.
Mari kita hitung: kalau ada seribu media, satu triliun dibagi rata, maka masing-masing dapat satu miliar rupiah. Uang segitu lumayan bagi banyak perusahaan media yang kini hidup megap-megap. Cukuplah untuk mengganti kamera, menggaji reporter, atau sekadar membeli kopi robusta agar redaktur tetap waras membaca rilis pemerintah.
Tapi di sisi lain, muncul tanya getir: apakah dengan uang itu media masih bisa kritis?
Sejarah sudah banyak memberi pelajaran. Di Rusia, awal 2000-an, pemerintah memberi “subsidi” agar media tak terlalu keras pada Kremlin. Di Hungaria, Viktor Orbán melakukan hal serupa: media disubsidi, diakuisisi, lalu dipeluk — sampai lupa cara menggigit. Demokrasi pun berubah jadi monolog panjang satu suara.
Di Filipina, di masa Duterte, media yang terlalu tajam malah disayat balik dengan pajak dan tuntutan hukum. Di mana-mana, dana dari kekuasaan selalu berpotensi jadi _mic silencer_ paling ampuh.
Tentu Hensat percaya media Indonesia tak semudah itu dibungkam. Tapi, mohon maaf, sejarah republik ini penuh dengan niat baik yang berujung sial. Kita pernah punya “Pers Pembangunan” — katanya untuk kemajuan bangsa, tapi akhirnya hanya jadi pengeras suara Orde Baru.
Masalahnya bukan pada niat memberi, tapi pada konsekuensi menerima. Sebab uang hasil rampasan korupsi, betapapun telah “diputihkan”, tetap membawa jejak moral: ia berasal dari kejahatan yang merampas hak rakyat. Lebih tepat jika dikembalikan untuk rakyat — walau media juga bagian dari rakyat.
Sebab ketika uang itu dialirkan ke media bukan untuk audit atau edukasi, tapi untuk “menolong”, kita harus hati-hati: jangan-jangan dari korban korupsi, media berubah jadi penyambung lidah koruptor baru — yang lebih wangi parfum dan lebih rapi dasinya.
Sebenarnya, ide Hensat bahwa “media hidup, demokrasi hidup” itu indah. Tapi catat baik-baik: media hidup bukan dari sedekah, melainkan dari integritas. Integritas dan independensi adalah modal paling mahal yang tak bisa dibeli, bahkan oleh uang sitaan negara.
Kalau media mau diselamatkan, biarlah lewat insentif pajak, riset publik, atau pelatihan jurnalisme data — bukan amplop jumbo dari hasil kejahatan ekonomi. Sebab kalau kebenaran sudah disubsidi, maka kebenaran akan belajar berbohong.
Dan tumpukan uang dua meter itu, yang kini jadi ikon pemberantasan korupsi, sebenarnya sedang berbisik lirih dari balik plastiknya: “Aku dulu hasil mencuri, kini dipamerkan untuk kebanggaan.”
Betapa ironis — uang haram yang kini jadi simbol kehormatan. Mungkin inilah cara bangsa ini berzakat atas dosanya sendiri: memamerkan bukti dosa sambil menepuk dada, bangga sudah menebusnya.
Namun semoga, dari gunung uang itu, lahir juga gunung kesadaran. Bahwa korupsi bukan cuma tentang angka yang dikembalikan, tapi tentang kepercayaan yang dicuri.
Sebab kalau uang bisa dipajang, kejujuran tidak. Ia hanya bisa dirawat dalam gelap — di hati orang-orang yang masih percaya bahwa bekerja jujur lebih mulia daripada memegang segepok uang sitaan.
Dan kalau suatu hari benar ada Rp1 triliun digelontorkan ke media, semoga itu tak berubah jadi biaya diam seribu kata. Sebab ketika media berhenti menggonggong, yang tersisa hanyalah auman kekuasaan.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 25/10/2025