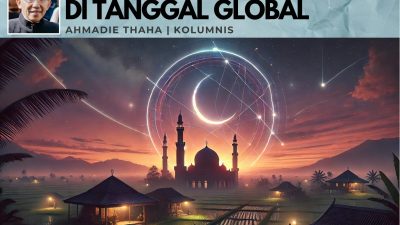Kolonialisme Digital (2)
Catatan Cak AT
Israel barangkali satu-satunya negara di dunia yang bisa menjual “rasa takut” sebagai komoditas ekspor. Amerika mengekspor jagung, Brasil mengekspor daging sapi, Indonesia mengekspor TKI dan batu bara.
Sementara itu, Israel mengekspor paranoia yang sudah dibungkus rapi dalam bentuk software security. Dan di balik semua itu, ada satu rahim intelijen digital Israel yang menjadi dapur rahasia, laboratorium paranoia sekaligus pabrik kapital: Unit 8200.
Unit militer Israel inilah yang menyadap seluruh pembicaraan orang Palestina dan menyimpannya di server awan Microsoft, untuk dianalisa, kemudian dieksekusi menjadi bom-bom yang dijatuhkan di titik wilayah Gaza sebelah mana dan kapan dengan presisi. Ini sudah saya tulis di bagian 1 kemarin.
Jangan bayangkan pasukan berlabel angka 8200 ini sekadar unit militer yang membosankan dengan prajurit botak bercelana loreng. Tidak. Ia lebih mirip start-up besar yang dikelola dengan disiplin militer.
Seragam bisa disimpan di lemari, tetapi otak-otak di baliknya adalah coder muda Israel yang baru tamat SMA, dipaksa pintar membaca kode musuh sambil juga menulis kode masa depan. Unit 8200 adalah tempat di mana perang tidak lagi membutuhkan darah untuk menjadi menakutkan. Cukup dengan kode biner.
Sederhananya, Unit 8200 adalah “NSA-nya Israel.” Dibentuk sejak awal 1950-an, ia lahir dari pengalaman trauma kolektif Israel: negeri yang kecil, dikelilingi musuh, harus punya kuping lebih banyak daripada telinga manusia. Seperti serigala lapar, mereka harus tahu setiap gerakan lawan.
Maka didirikanlah unit intelijen sinyal (SIGINT) yang kelak membesar menjadi 8200. Mereka belajar dari NSA Amerika, bahkan menyalin struktur organisasinya, hanya dengan skala lebih ramping. Bedanya, jika NSA menatap dunia dengan satelit raksasa dan kabel bawah laut, Unit 8200 melatih ribuan anak muda brilian untuk menyusup ke setiap celah digital.
Kisah heroik mereka sering dilebih-lebihkan dalam narasi resmi Israel. Misalnya, kemenangan Israel dalam perang enam hari 1967 konon dipengaruhi keberhasilan intel 8200 menyadap komunikasi Mesir dan Suriah. Di sinilah awal kolonialisme digital lahir: menaklukkan musuh bukan dengan tank, melainkan dengan menguasai percakapan dan informasi mereka.
Kalau Anda penasaran kenapa Tel Aviv bisa berubah jadi “Silicon Valley versi Timur Tengah,” jawabannya: Unit 8200.
Coba kita bongkar sedikit. Setiap tahunnya, ribuan anak muda Israel yang lulus SMA masuk wajib militer. Yang pintar matematika, jago komputer, cepat logika —akan dipindahkan ke 8200. Di sana, mereka ditempa bukan sekadar jadi tentara, tetapi jadi hacker profesional. Belajar membobol jaringan musuh, memetakan ponsel warga sipil Palestina, menyusup ke server lawan.
Setelah 3–5 tahun, mereka keluar dari dinas militer, kembali ke dunia sipil, dan —voilà!— langsung mendirikan perusahaan rintisan. Ada yang bikin cybersecurity company, ada yang menjual perangkat analisis data, ada pula yang menciptakan spyware dengan branding keren. Dunia internasional menyebut Israel sebagai Start-Up Nation, padahal lebih tepat disebut Spyware Nation.
Contoh paling terkenal? NSO Group, pencipta Pegasus spyware. Meski NSO bukan unit resmi militer, banyak pendirinya adalah alumni 8200. Pegasus kemudian dipakai untuk menyusup ke ponsel aktivis, wartawan, bahkan kepala negara. Dari Putra Mahkota Arab Saudi sampai presiden Prancis, semua bisa jadi korban. Betapa ironis, kolonialisme digital Israel kini menjangkau kepala-kepala negara yang justru sering melindungi mereka.
Apa hubungannya 8200 dengan kolonialisme digital? Mari kita tarik garisnya.
Kolonialisme klasik bekerja dengan fisik: datang dengan kapal, bawa senjata, rebut tanah, ambil rempah. Kolonialisme digital bekerja dengan data: menyusup ke jaringan, mengontrol informasi, lalu menjual hasilnya ke pasar global. Kalau dulu Belanda mengambil pala dari Banda Neira, kini Israel mengambil percakapan dari WhatsApp dan Gmail.
Dan di Palestina, ini lebih nyata daripada sekadar teori. Laporan dari mantan anggota 8200 sendiri —yang tahun 2014 menulis surat terbuka— menyatakan bahwa intel yang mereka kumpulkan bukan hanya soal militer. Mereka menyadap percakapan warga sipil: siapa yang selingkuh, siapa yang punya utang, siapa yang ketahuan gay. Semua dipakai sebagai alat kontrol politik. Kolonialisme dengan metode blackmail.
Bayangkan hidup di dunia di mana setiap kata yang Anda ucapkan bisa dipakai untuk menundukkan Anda. Di Gaza, mikrofon tak terlihat ini lebih kejam daripada tembok beton.
Namun 8200 tidak berhenti di Palestina. Setelah latihan gratis di laboratorium Gaza dan Tepi Barat, mereka menjual teknologi ini ke dunia. Banyak negara yang “butuh rasa aman” membeli paranoia dari Israel.
Pegasus adalah contoh paling terang. Spyware ini dijual ke rezim otoriter, dipakai untuk membungkam oposisi, menangkap jurnalis, atau sekadar mengintip istri pejabat. Boleh dibilang, Israel telah menciptakan franchise of surveillance. Dari Meksiko sampai India, dari Hongaria sampai Maroko, jejak Pegasus ada di mana-mana.
Lebih menakutkan lagi, alumni 8200 mendirikan ratusan perusahaan teknologi yang kini jadi penyedia utama cybersecurity dunia. Nama-nama seperti Check Point, Palo Alto Networks, CyberArk —semuanya punya DNA 8200. Dunia membeli software mereka dengan alasan keamanan, tanpa sadar ikut membiayai kolonialisme digital yang awalnya dipraktikkan di Gaza.
Mari kita letakkan Unit 8200 dalam konteks global.
Dulu, kolonialisme selalu datang dengan dalih “misi peradaban” — the white man’s burden. Hari ini, kolonialisme digital datang dengan slogan “cybersecurity for all.” Bedanya cuma baju. Intinya tetap sama: kontrol.
Jika abad ke-19 bangsa Eropa memetakan peta dunia, maka abad ke-21 Israel memetakan dunia digital. Dan lebih canggih: mereka tidak perlu kapal. Cukup kode. Mereka bisa duduk di Tel Aviv, tetapi menembus layar ponsel kita di Jakarta.
Di sinilah kolonialisme digital menjadi nyata. Data menjadi komoditas baru. Privasi menjadi rempah baru. Dan Unit 8200 menjadi VOC baru — Vereenigde Oostindische Cyber-Compagnie.
Narasi resmi Israel sangat cerdik. Dunia dibuat kagum dengan label Startup Nation. Mereka seolah negeri kecil yang penuh inovasi, padahal di balik layar, inovasi itu lahir dari penindasan. Gaza menjadi laboratorium uji coba. Tepi Barat menjadi pusat beta test. Dan hasilnya dijual ke dunia dengan bungkus canggih.
Bayangkan jika di masa kolonial dulu, Belanda menjual “teknologi perkebunan” ke dunia sambil menguji coba perbudakan di Jawa. Begitulah 8200 bekerja. Dunia mengagumi teknologi Israeli cybersecurity, tanpa mau tahu bahwa kode-kode itu pertama kali diuji di tubuh rakyat Palestina.
Kita sampai pada inti refleksi: mengapa Unit 8200 bukan sekadar soal militer, melainkan kolonialisme?
Karena mereka tidak hanya mengawasi musuh, tetapi menjadikan seluruh dunia sebagai pasar. Mereka tidak hanya mencuri data, tetapi menjadikan data sebagai instrumen kekuasaan. Mereka tidak hanya menjual paranoia, tetapi mengubah paranoia menjadi industri global.
Kolonialisme dulu mengubah tanah jadi kapital. Sekarang kolonialisme digital mengubah data jadi kapital. Dan Israel, lewat 8200, menjadi salah satu pemain utama.
Di dunia digital hari ini, kolonialisme tidak lagi memakai meriam. Ia memakai mikrofon yang disembunyikan dalam ponsel Anda. Ia tidak lagi menjajah tanah, tetapi menjajah memori. Ia tidak lagi menaklukkan pelabuhan, tetapi menaklukkan cloud server.
Unit 8200 adalah wajah paling telanjang dari kolonialisme digital: memproduksi rasa takut, menjualnya, lalu memetik keuntungan.
Dan ironinya, dunia membayar mahal untuk membeli paranoia itu. Dunia membeli software Israel untuk melindungi privasi, padahal privasi itulah yang pertama kali mereka hancurkan di Gaza.
Kita, manusia abad 21, hidup dalam dunia yang semakin menyerupai panoptikon digital. Setiap klik, setiap chat, setiap panggilan bisa terekam. Bedanya, kali ini bukan sekadar “Big Brother” yang mengintai, melainkan “Little Brother 8200” yang menjual hasil intaiannya ke siapa saja yang mampu membayar.
Apakah dunia sedang diseret masuk ke era kolonialisme digital yang lebih brutal? Jawabannya tergantung pada apakah kita sadar bahwa teknologi bukanlah netral, melainkan senjata. Dan senjata paling berbahaya bukanlah yang meledakkan bom, melainkan yang mencuri percakapan.
Karena kata-kata bisa membentuk sejarah, dan sejarah bisa dijajah lewat data.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 5/10/2025