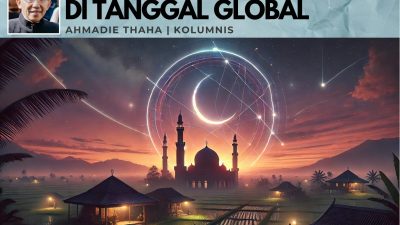Catatan Cak AT
Saya sebut lagi di sini, “Chaos,” kata Presiden Prabowo, dengan intonasi berat ala jenderal yang tengah membayangkan strategi perang. Tapi kali ini bukan soal perang melawan musuh negara, melainkan menghadapi rakyatnya sendiri.
Ironisnya, chaos itu bukan turun dari langit, melainkan muncul dari lidah anggota DPR yang seolah-olah dirancang memang untuk bikin gaduh. Chaos itu, kata Prabowo, lahir dari “unsur-unsur” dan “kelompok-kelompok” yang justru membuat rakyat makin susah.
Hari ini Presiden berbicara dengan para petinggi partai politik, kemudian mengeluarkan pernyataan bersifat politis: bahwa tunjangan untuk DPR dan perjalanan dinas ke LN mereka disepakati akan dibekukan; dan aparat diperintah bertindak tegas terhadap para pendemo anarkis perusak.
Sehari sebelumnya, Jusuf Kalla yang dua kali jadi Wakil Presiden, dengan gaya khas orang Bugis yang kalem tapi menusuk, tak salah menuding: penyebab demo masif dari Jakarta sampai Papua bukan karena rakyat gila, melainkan karena DPR memang bicara ngawur.
“Jangan menghina rakyat, jangan asal bicara!” kata JK dengan wajah serius. Itu sebetulnya pelajaran SD: kalau tidak bisa menenangkan suasana, setidaknya jangan menyalakan api di pom bensin. Namun kali ini, api itu menyala di mana-mana—dan sumbernya dari Parlemen, Senayan.
Semula massa hanya membakar ban-ban di tengah jalan. Lalu polisi menabrak pengojek online dengan mobil seberat 12 ton. Massa membakar mobil polisi, kemudian menyasar kantor polisi di sejumlah daerah. Tak lupa, gedung-gedung DPR di kota-kota besar ikut ludes dibakar api amarah rakyat.
Lihatlah penyebabnya, seperti dituding JK. Alih-alih menenangkan, anggota DPR malah melempar bensin premium ke dalam kobaran emosi rakyat yang sudah membuncah oleh kezaliman yang bertahun-tahun mereka simpan dalam dada.
Ada anggota DPR yang bilang tunjangan Rp 50 juta per bulan itu wajar, sebab tinggal di Bintaro itu macet. Ada pula yang dengan enteng menyebut rakyat “tolol se-dunia” karena mereka berteriak “bubarkan DPR”. Kalau ini bukan satire kehidupan nyata, saya tidak tahu lagi.
Mari kita lihat data: menurut Formappi, DPR periode 2024–2029 belum bekerja apa-apa. Mereka baru mengesahkan satu RUU prioritas. Ya, satu dari 42. Itu pun revisi UU TNI —bukan soal rakyat miskin, bukan soal kesehatan, apalagi pendidikan.
Namun, untuk urusan tunjangan rumah Rp 50 juta, tunjangan bensin Rp 3 juta, bahkan tunjangan beras (yang entah kapan terakhir mereka makan nasi di warteg), para anggota Dewan cekatan sekali bekerja. Pemerintah pun setuju memasukkannya dalam RAPBN.
Sosiolog politik menyebut fenomena ini elite disconnect: wakil rakyat yang semakin jauh dari realitas sosial. Mereka mengaku mewakili rakyat, tapi rakyat merasa tak terwakili. Rakyat antre minyak goreng, sementara DPR antre tunjangan perumahan.
Akibatnya? Ketimpangan terasa nyata. Survei LSI tahun lalu bahkan menunjukkan kepercayaan publik ke DPR sudah jatuh di titik rendah, lebih rendah dari kepercayaan pada lembaga RT. Bayangkan, Ketua RT lebih dipercaya daripada Ketua DPR—yang baru belakangan minta maaf.
Bandingkan dengan negara lain: gaji anggota parlemen Indonesia, menurut data Inter-Parliamentary Union (IPU), mencapai setara tiga kali PDB per kapita. Itu jauh di atas rata-rata global, yang bisa dengan mudah dibaca rakyat awam.
Di Inggris, anggota House of Commons memang bergaji tinggi, tapi mereka diwajibkan melaporkan hingga kuitansi teh celup. Di Jepang, anggota parlemen menerima gaji besar, tapi integritas politik mereka jauh lebih baik.
Sementara di Indonesia, rakyat masih bisa menyaksikan anggota DPR tidur siang berjamaah di ruang sidang dengan bantal “tunjangan” yang empuk. Ditambah lagi pertunjukan joget-joget dan nyanyi-nyanyi di ruang Gedung DPR Senayan —tanpa rasa simpati pada rakyat yang berduka.
Indeks ketimpangan Gini Indonesia pada 2024 tercatat di angka 0,388 (BPS), salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Artinya, ketika DPR membahas tunjangan Rp 50 juta per bulan, ada 26 juta rakyat hidup di bawah garis kemiskinan.
Ibaratnya, kapal sedang bocor, tapi nakhoda sibuk menaikkan tarif kursi VIP di geladak. Wajar kalau rakyat akhirnya berpikir: lebih baik kapal tua ini dibongkar, daripada ditingkahi opera sabun DPR yang kian lama kian tak lucu. Teriakan “Bubarkan DPR” pun menggema nyaring.
Prabowo benar ketika menyebut ada pihak yang menginginkan chaos. Tapi beliau lupa menambahkan: chaos itu justru tumbuh dari pupuk yang ditebar unsur negara sendiri —dari ketidakadilan, dari kebrutalan aparat, dari arogansi lidah para politisi.
Kita tidak bisa menutup mata: seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas dilindas rantis polisi seberat 12 ton. Ini bukan sekadar “eksesif”, ini barbar. Video rekamannya viral, mirip adegan film distopia, hanya saja kali ini tanpa aktor Hollywood.
Fakta inilah yang mengakumulasi amarah rakyat: mereka bukan hanya marah karena DPR kaya-raya, tapi juga karena nyawa mereka dianggap seharga ban kendaraan taktis. Kebrutalan aparat sudah terekam dalam benak jutaan rakyat, membuat mereka muak hingga ingin muntah.
Ketika rakyat meneriakkan “Bubarkan DPR!”, awalnya mungkin hanya sebuah satire. Sebuah sindiran bahwa lembaga itu tidak lagi relevan. Benar kata Mahfud MD: tuntutan pembubaran DPR memang tidak relevan secara konstitusional, tapi itu justru menunjukkan rasa frustasi rakyat yang dalam.
Namun, respon DPR yang sinis justru menyulut api. Ahmad Sahroni dengan gagah berani menyebut pengkritik DPR sebagai “tolol se-dunia”. Kalimat itu mungkin dimaksudkan sebagai punchline, tapi hasilnya justru jadi bahan bakar mobilisasi massa.
Tak lama kemudian, ribuan orang turun ke jalan dengan poster bertuliskan: “DPR: Dewan Pembeban Rakyat” hingga “Bubarkan DPR”. Sosiolog UI menyebut ini sebagai accumulated grievances: amarah rakyat yang menumpuk bertahun-tahun, membuncah, lalu pecah jadi demo-demo besar.
Lucunya, di tengah tragedi, anggota DPR malah joget dengan parodi “Sound Horeg”. Eko Patrio mungkin bermaksud menghibur diri, tapi bagi rakyat, itu seperti pesta di atas kuburan. Kontras ini —rakyat tertindas, DPR berpesta— hanya mempertegas jurang sosial yang makin lebar.
Ilmuwan politik seperti Jeffrey Winters pernah menulis bahwa oligarki di Indonesia hidup dengan “high income, low responsibility.” Rakyat membayar pajak makin tinggi, sementara oligarki dan elite politik hidup mewah dengan tanggung jawab yang makin rendah.
Kalau ini bukan bahan satire yang menyesakkan dada rakyat, entah apa lagi. Padahal rakyat tidak sedang meminta surga. Mereka hanya ingin keadilan sederhana: jangan ditindas, jangan dizalimi, jangan dihina, dan jangan dipermainkan.
Tapi ketika kritik dibalas cemoohan, ketika demonstrasi dibalas gas air mata dan rantis yang membunuh, ketika kemiskinan dibalas dengan angka tunjangan fantastis, maka chaos bukan hanya mungkin. Ia pasti terjadi —dan kini sudah terjadi.
Jika DPR dan negara masih ingin dihormati, maka solusinya bukan sekadar minta maaf ala selebriti, melainkan bekerja sungguh-sungguh, memotong tunjangan, dan menyelamatkan martabat lembaga. Kalau tidak, seruan “Bubarkan DPR” akan berubah dari satire menjadi sejarah revolusi.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 31/8/2025