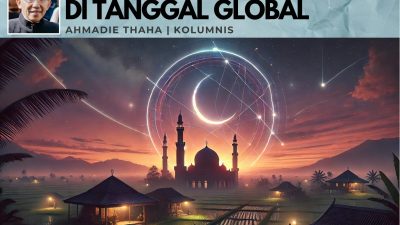Catatan Cak AT
“Chaos,” kata Presiden Prabowo, dengan intonasi berat ala jenderal yang sedang membayangkan strategi perang. Bedanya, kali ini ia tak bicara tentang palagan militer, melainkan tentang tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, yang dilindas mobil taktis polisi seberat 12 ton.
Saya hitung dari teks pernyataan Presiden Prabowo (29 Agustus 2025), kata “chaos” muncul tiga kali. “Ada unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin chaos,” katanya usai kalimatnya menyampaikan belasungkawa mendalam atas Affan.
Lalu ia menegaskan, “hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita.” Dan sekali lagi ia mengingatkan, “kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan (chaos).”
Pengulangan kata “chaos” jelas bukan kebetulan linguistik, melainkan strategi retoris klasik: mengulang istilah kunci agar melekat di benak pendengar. Dalam kerangka Aristotelian, ini membangun _pathos_ —membangkitkan emosi kolektif dengan menunjuk musuh eksternal. Chaos diposisikan sebagai ancaman, sekaligus tirai penutup bagi pertanyaan tentang kesalahan aparat.
Namun paradoksnya, semakin sering kata itu disebut, semakin kuat pula kesan bahwa negara memang sedang terjebak dalam pusaran ketidakstabilan. Alih-alih meredakan, mantra “chaos” justru berisiko memperkuat citra krisis.
Kata itu terdengar seperti kunci ajaib yang bisa menjelaskan segalanya: demo ojol di Senayan, barikade di depan Mabes Polri, hingga teriakan mahasiswa di Makassar. Seolah cukup dengan menyebut chaos, publik otomatis mafhum: ada tangan-tangan gelap yang sedang mengatur skenario.
Tapi tunggu dulu —kalau benar ada tangan gelap, siapa dalangnya? Dan kenapa seorang Affan Kurniawan, tukang ojol yang tiap hari sibuk mengantar penumpang dan nasi bungkus, harus jadi korban?
Affan jelas bukan bagian dari _deep state_ atau “Geng Solo.” Ia hanya rakyat kecil yang berhadapan dengan moncong barakuda. Nyawanya melayang, keluarganya menangis, dan solidaritas ribuan ojol pun meledak.
Solidaritas itulah yang membuat ribuan ojol turun ke jalan. Bukan karena mereka membaca teori konspirasi di Twitter, melainkan karena mereka tahu: hari ini Affan, besok bisa siapa saja. Dalam dunia ojol, solidaritas itu lebih nyata ketimbang subsidi.
Demo sehari setelah kematian Affan memang luar biasa. Dari DPR sampai markas Gegana di Kramat Raya, semua jadi sasaran. Polisi, mungkin belajar dari tragedi Kanjuruhan, kali ini agak menahan diri: biarkan massa berteriak, lepaskan kecewa. Toh jeritan itu lebih sehat ketimbang diam lalu meletup jadi radikalisme.
Kalau pun ke depan demo terus berlanjut, itu bukan sekadar soal Affan. Rakyat sudah lama menumpuk kekecewaan. Ingat Kanjuruhan 2022? Lebih dari 130 nyawa melayang. Ingat konflik Km 50, Rempang, Wadas, atau Morowali? Rakyat dipukul, diusir, dikriminalisasi. Polisi selalu hadir, tapi lebih sering dalam wujud pentungan, gas air mata, dan borgol.
Dalam psikologi sosial, ini disebut _accumulated grievance_ —keluhan berlapis yang lama-lama jadi bara. Affan hanyalah percikan kecil; bensinnya sudah lama ditumpahkan oleh negara sendiri.
Nah, masuklah kita ke teori chaos. Dalam literatur gerakan massa ada istilah _strategy of tension_: menciptakan ketegangan sosial agar penguasa tampak gagal, lalu muncul tuntutan mundur. Mirip resep warung kopi: bikin gaduh dulu, biar semua orang salah fokus.
Prabowo sadar itu. Ia bilang ada pihak-pihak yang memang ingin kerusuhan. Betul. Tapi rakyat juga tahu, chaos bukan hanya karya lawan politik. Aparat yang brutal pun ikut menyumbang. Chaos lahir bukan semata dari konspirasi, melainkan juga dari inkompetensi.
Gustav Le Bon dalam _The Crowd_ (1895) menyebut massa mudah tersulut emosi dan kehilangan kendali individu. Tapi Le Bon lupa menambahkan: kadang yang lebih dulu kehilangan akal justru polisi di lapangan.
Politik pun masuk: semua orang tahu, kalau Prabowo jatuh, otomatis Gibran naik. Skenarionya jelas: ada kerusuhan, muncul narasi “Presiden gagal,” rakyat marah, tuntutan mundur bergema, dan episode berikutnya Gibran tersenyum di Istana.
Masalahnya, kalau skenario terlalu jelas, rakyat malas menontonnya. Sama seperti sinetron yang ketebak ending-nya: rating turun, meski kerusakan nyata tetap terjadi.
Di titik ini, Prabowo menghadapi ujian serius. Hanya berteriak “awas chaos” tak cukup. Ia harus mengendalikan aparat, penyakit kronis yang sudah lama jadi sumber luka.
Ia pun perlu semakin menunjukkan bukti berpihak pada rakyat, bukan sekadar santunan. Ia juga mesti berani memisahkan diri dari lingkaran lama, atau publik akan melihatnya sekadar perpanjangan tangan masa lalu.
Masalahnya, di negeri ini, chaos sering dituding sebagai agenda musuh, padahal kadang justru diproduksi negara sendiri. Polisi menembak gas air mata, rakyat lari pontang-panting, dan elite politik menonton sambil ngopi. Chaos jadi panggung.
Namun jangan lupa: Affan Kurniawan bukan aktor. Ia korban nyata. Keluarganya kehilangan tulang punggung. Teman-temannya kehilangan kawan seperjuangan di jalanan.
Maka jika Presiden ingin bicara soal chaos, mulailah dari yang paling sederhana: hentikan rakyat mati sia-sia karena aparat gagal mengendalikan diri. Chaos bisa diskenariokan elite, tapi luka rakyat selalu nyata.
Dan percayalah, rakyat Indonesia bukan sekadar pion yang bisa diarahkan dengan teori konspirasi. Mereka tahu solidaritas, tahu kapan marah, kapan pulang. Yang mereka tidak tahu hanyalah: kapan negara ini benar-benar berpihak pada mereka.
Satirnya: kalau chaos memang skenario politik, rakyat hanyalah figuran. Tapi jika chaos lahir dari akumulasi kekecewaan, maka elite-lah yang sedang main sinetron murahan —sementara rakyat menanggung deritanya.
Walhasil, ketika Prabowo menyebut ada pihak yang ingin menciptakan chaos, publik bisa mengangguk. Betul, ada aktor politik yang berkepentingan. Tapi jangan lupa: chaos juga tumbuh alami dari luka sosial yang lama diabaikan.
Solidaritas ojol bukanlah operasi intelijen. Itu lahir dari empati. Namun bila aparat tetap brutal, luka itu akan jadi bahan bakar bagi siapa pun yang ingin menyalakan api lebih besar. Di titik ini, sebuah gerakan besar bisa segera terjadi, tinggal tunggu momentum tepat.
Pertanyaan pentingnya bukan hanya “siapa dalang chaos?” tetapi juga “kenapa negara terus-menerus menyiapkan bensin bagi api itu?” Elite politik boleh saja bermain skenario, tapi badai rakyat —kalau sudah lepas kendali— tak pernah bisa disutradarai.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 30/8/2025