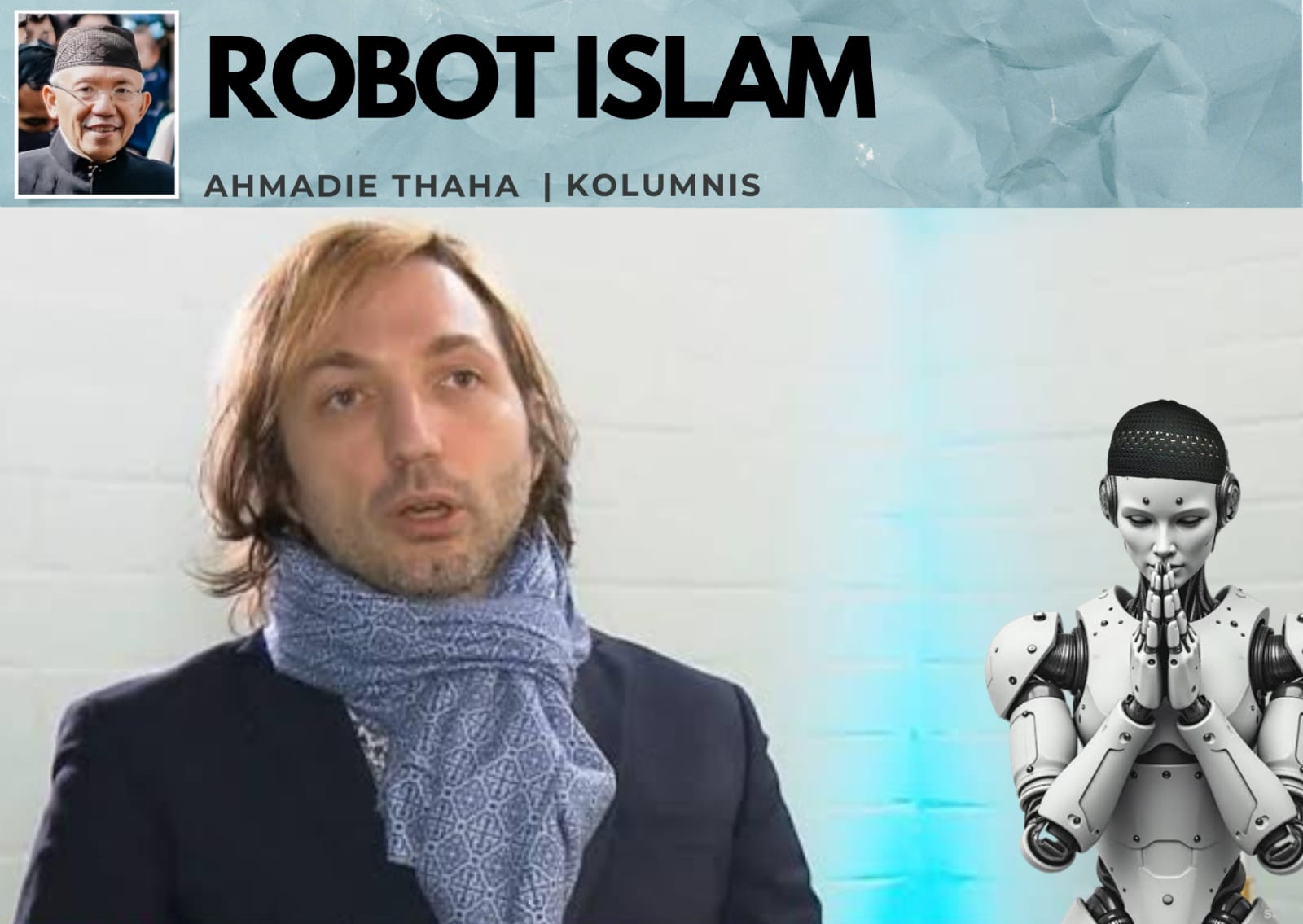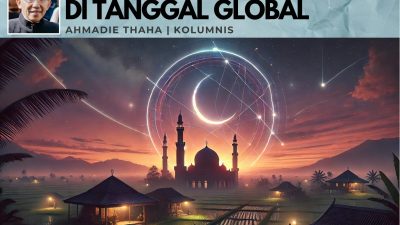Catatan Cak AT
Pertemuan itu benar-benar tak terduga. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saya berhadapan dengan Gabriele Trovato, seorang guru besar robotika —ilmu yang terasa begitu jauh dari keseharian kita. Kehadirannya seolah mimpi yang datang dari langit.
Selama ini saya hanya beberapa kali menyaksikan siswa Madrasah TeknoNatura berkreasi dengan robot. Tetapi baru kali ini saya bertemu langsung dengan seorang profesor di bidang langka itu. Entah, adakah di negeri ini seorang profesor robotika yang setara dengannya?
Tubuhnya jangkung, langkahnya tenang, dan cara bicaranya pelan tapi tegas. Dari raut wajahnya, saya bisa menangkap kombinasi antara ilmuwan yang serius dan seniman yang penuh imajinasi. Matanya sesekali menerawang, menatap ornamen ruang kantor MUI Pusat.
Tampak wajahnya seperti sedang membayangkan sirkuit elektronik dan doa-doa yang terhubung dalam satu motherboard. Didampingi peneliti BRIN, Gabriele kemudian memperkenalkan diri dalam Bahasa Inggris dengan logat Italia yang kental, namun dengan kerendahan hati.
Suara dan sikapnya membuat saya —yang biasanya gampang sinis— justru merasa segan. “Maaf, saya orang Katolik,” ujarnya dalam percakapan, dengan senyum tipis yang lebih mirip permohonan maaf ketimbang pernyataan identitas.
Saya mendengar kalimat itu seperti disclaimer awal sebuah presentasi: bahwa ia tidak berniat mengajarkan Islam, apalagi merebut otoritas ulama. Ia datang ke MUI membawa surat berkop BRIN untuk berkonsultasi tentang inovasi terkait Islam.
Ia datang ke MUI hanya ingin menawarkan medium baru —robot— sebagai perantara. Robot Islam, katanya, bisa menjadi teman kecil bagi anak-anak, penolong bagi orang tua, dan penghibur bagi para pekerja migran Muslim di Jepang yang rindu sentuhan rohani.
Di negeri ini, biasanya kita ribut soal politik, harga cabai, atau siapa yang layak jadi calon presiden. Tapi kemarin saya mendengar, itu tadi, sesuatu yang lebih segar: robot Islam. Ya, Anda tidak salah baca. Ide ini datang langsung dari Gabriele yang kini bermukim di Tokyo.
Dia bukan orang sembarangan. Namanya mendunia gara-gara menciptakan SanTO —robot Katolik berbentuk ikon sakral yang bisa menemani orang berdoa, membacakan Alkitab, dan memberi nasehat. Robot itu sudah mejeng permanen di museum sains di Warsawa.
Itu bukan mainan, melainkan proyek serius lintas iman, lintas teknologi, dan —mau tak mau— lintas kontroversi. Nah, kali ini Gabriele membawa proposal resmi: bagaimana kalau eksperimen serupa dibuat dalam versi Islam?
Dia meniatkan robot ini bukan untuk menggantikan ustadz, melainkan menemani umat, khususnya para pekerja migran di Jepang yang kesulitan mencari guru ngaji. Menurut data yang diperolehnya, di Negeri Sakura terdapat sekitar 200 ribu warga Indonesia beragama Islam.
Mari kita mundur sedikit. Tahun 2017, Gabriele meluncurkan SanTO _(Sanctified Theomorphic Operator)_ di Peru. Bentuknya mirip ikon dengan patung kudus dalam altar, yang dirancangnya sebagai hasil studi literatur, lengkap dengan software pengenal suara.
Orang bicara pada mic kecil yang dipasang tersembunyi, robot lalu menjawab dengan ayat Kitab Suci atau kisah para santo. Idenya sederhana: jika umat Katolik terbiasa berdoa di depan ikon, mengapa tidak membuat ikon itu bisa “membalas” doa?
Tentu saja, sebagian orang terperangah dan merasa aneh. Ada yang khusyuk, ada yang geli, ada pula yang marah-marah. Tetapi toh robot itu mendapat tempat di museum, diakui media, dan dijadikan bahan diskusi serius tentang masa depan iman dalam dunia digital.
Kini giliran Islam. Bedanya, umat Muslim tak punya tradisi patung atau ikon. Maka, Gabriele dengan rendah hati membuka PowerPoint: desain kubah, kaligrafi, masjid mini. “Soal penilaian atas desain, dan apa saja isinya, saya tak mau sembarangan. Biarlah MUI yang bicara,” akunya.
Jangan salah, ini bukan pertama kalinya agama dan robot saling bersalaman. Sebelumnya sudah ada Mindar, robot biksu di kuil Kodaiji, Kyoto, yang berkhotbah tentang ajaran Buddha, lengkap dengan gerakan tangan ala manusia.
Jamaah datang, sebagian serius, sebagian selfie depan robot. Selain itu, ada BlessU-2, robot pendeta di Jerman (2017), diciptakan untuk memperingati 500 tahun Reformasi. Robot ini bisa memberkati jemaat dengan tangan mekaniknya, dalam lima bahasa pula.
Di Amerika, ada eksperimen AI yang bisa membuat doa dan khutbah berbasis algoritma. Karena masih tahap uji-coba, tentu belum sempat dipakai di gereja, kuil, atau masjid, tapi sudah cukup bikin teolog garuk-garuk kepala.
Dengan kata lain, Gabriele tak sendirian. Dunia memang sedang menguji: mungkinkah “iman digital” lahir di era kecerdasan buatan Di ruang pertemuan MUI Pusat itu, saya melihat ekspresi campur aduk: kagum, penasaran, sekaligus was-was. Pertanyaan pun bermunculan.
Apakah robot bisa jadi guru agama? Tidak, tentu saja, begitu jawaban kita. Ustadz bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga teladan akhlak. Robot boleh pintar menjawab fiqih wudhu, tapi bisakah ia menenangkan hati jamaah yang berduka?
Apakah robot akan menggantikan fungsi masjid atau majelis taklim?
Rasanya juga tidak. Tetapi, seperti halnya TV dakwah, kaset ceramah, atau YouTube Ustadz, robot hanyalah medium. Pertanyaannya: apakah medium ini sesuai, atau justru menimbulkan distorsi?
Apakah umat siap? Ini pertanyaan paling penting. Jika salah kelola, robot bisa menjadi bahan lelucon, bahkan fitnah. Tapi jika benar dikelola, ia sepertinya bisa membantu anak-anak TKI belajar mengaji tanpa harus antre _video call_ dengan ustadz di tanah air.
Jujur, mendengar gagasan ini saya ingin tertawa sekaligus merenung. Tertawa karena membayangkan jamaah shalat tarawih diimami robot dengan suara Google Translate. Merenung karena sadar: kebutuhan spiritual umat di rantau nyata adanya.
Jika teknologi bisa membantu, mengapa tidak? Namun, tentu syaratnya jelas: robot jangan sampai menggantikan otoritas agama, melainkan menjadi alat bantu edukasi. Kontennya harus diverifikasi, tampilannya harus sensitif budaya.
Dan satu lagi —ini yang paling sulit— ia harus bebas dari politisasi. Bayangkan jika robot tiba-tiba disponsori partai politik, bukankah jadinya mubazir sekaligus menggelikan? Apalagi nanti ia disuruh kampanye dengan memanfaatkan agama, jangan deh.
Walhasil, Prof. Gabriele, dengan segala kerendahan hatinya, datang ke Indonesia bukan untuk menggurui, melainkan mencari legitimasi. Ia sadar, konten Islam bukan wilayahnya. Ia hanya membawa kerangka teknologi; isinya harus ditentukan oleh umat.
Pertanyaannya, sekali lagi: apakah kita siap? Atau jangan-jangan kita masih terlalu sibuk berdebat soal boleh-tidaknya pengeras suara masjid, apakah qunut itu harus, dan banyak lagi pertanyaan kontroversial yang sebetulnya hanya bagian cabang dari ajaran?
Kalau umat Katolik sudah punya SanTO, umat Buddha punya Mindar, umat Protestan punya BlessU-2, maka umat Islam kini dihadapkan pada tantangan baru: apakah kita siap punya “Robot Islam”? Pertanyaan yang menggelayut di benak kita.
Jawabannya belum tentu ada di laboratorium robotika Tokyo. Tapi, itu pasti ada di hati umat yang mau berpikir jernih, tanpa alergi teknologi, tanpa takut kehilangan ruh, dan tanpa lupa bahwa agama bukan sekadar teks, melainkan juga cinta, empati, dan teladan.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 29/8/2025