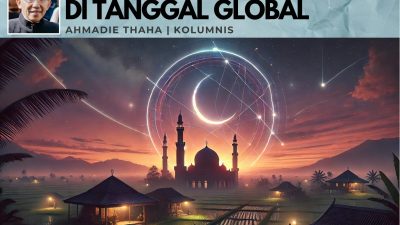Catatan Cak AT
Hukum di Indonesia kadang terasa seperti pertunjukan sirkus keliling. Ada ring master di tengah panggung. Dalam kasus ini, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra—yang menjelaskan ke penonton bahwa semua trik yang ditampilkan “sesuai aturan main” dan “berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta UU Darurat No. 11/1954.”
Bahasa hukumnya rapi, seperti pengacara yang menghafal teks upacara, tapi selalu mampu menjawab pertanyaan paling penting dari penonton: “Lho, ini maksudnya toh?”
Biar jelas, kita mundur sedikit. Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, dijerat kasus dugaan korupsi impor gula 2015–2016, dengan hitungan kerugian negara versi BPKP. Hasto Kristiyanto, politisi kawakan PDIP, punya kasus politik yang aromanya lebih mirip intrik kekuasaan ketimbang buku teks hukum pidana.
Presiden Prabowo memutuskan memberikan abolisi untuk Tom —artinya semua penuntutan terhadapnya dihapus— dan amnesti untuk Hasto— artinya semua akibat hukum dari perkaranya lenyap seperti asap sate di angin sore. Secara teori, keduanya sekarang bisa pulang, istirahat, dan menulis memoar.
Tapi yang terjadi justru _plot twist_. Tom, yang katanya ingin _move on,_ malah mampir ke Ombudsman, melaporkan dugaan maladministrasi dalam audit BPKP yang menjadi dasar kasusnya.
Ia bahkan meminta publik jangan merundung auditor muda yang ikut menghitung kerugian negara —sambil tetap melaporkan seluruh tim auditnya.
Hasto? Lebih senyap, tapi tetap jadi simbol bahwa di negeri ini, satu tanda tangan Presiden bisa menghapus dosa politik lebih cepat daripada hakim mengetuk palu.
Di sini lah letak pamungkasnya. Yusril menjelaskan, “Kalau sudah dapat abolisi dan amnesti, semua proses hukum otomatis gugur. Tidak perlu banding.”
Tapi kenapa publik mendengar ini seperti mendengar beliau bilang, “Semua sudah beres,” padahal di belakang panggung, para kru masih berantem rebutan kabel mikrofon.
Kalau prosedur sudah sempurna, kenapa Tom masih harus melapor? Dan kalau asas keadilan sudah dijunjung, kenapa hakim, auditor, dan penegak hukum yang salah prosedur tidak ikut dipanggil ke panggung untuk diberi pelajaran?
Inilah masalah klasik birokrasi hukum kita: ketika ada cacat proses, yang diselamatkan adalah hasil akhirnya, bukan sistemnya. Seperti dokter yang mengoperasi pasien tanpa cuci tangan, tapi menganggap tidak apa-apa karena pasiennya kebetulan sembuh.
Yusril berdiri di garis resmi, sudah seharusnya menjaga citra bahwa negara berjalan di koridor hukum, sementara Tom menunjukkan bahwa koridornya berlubang, licin, dan penuh jebakan.
Publik pun belajar, abolisi dan amnesti memang bisa menyelamatkan individu, tapi tidak otomatis menyelamatkan kewarasan sistem. Dan selama pejabat hukum kita lebih sibuk menjaga _“good corporate governance”_ versi pidato, ketimbang memastikan proses di lapangan bersih, kita akan terus mengulang sirkus ini dengan pemain berbeda.
Jadi, kalau Tom bilang mau _move on_, mungkin maksudnya _move on_ dari status terdakwa, bukan _move on_ dari keinginan memberi pelajaran kepada para “wasit” dan “panitia pertandingan” yang seenaknya mengubah aturan main.
Dan kalau Hasto memilih diam, bisa jadi itu strategi —karena di negeri ini, kadang yang banyak bicara kalah cepat dari yang tahu kapan harus diam.
Akhirnya, kita harus akui satu hal: di republik ini, hukum memang bisa dihapus dengan selembar keputusan presiden. Itu patut disyukuri terutama bagi mereka yang bebas.
Tapi rasa tidak adil? Itu tidak bisa dihapus begitu saja. Ia akan tetap nongkrong di benak publik, mengingatkan bahwa meski sirkus sudah bubar, gajahnya tetap meninggalkan jejak di tengah kota.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 13/8/2025