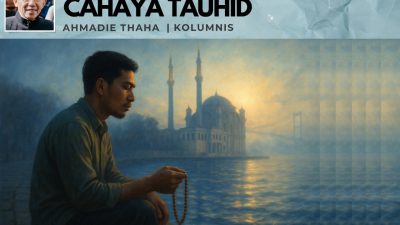Catatan Cak AT
Saya paham betul kalau Bung Denny JA bicara soal energi dari ceruk sumur dan batu, karena ya memang beliau kini duduk di kursi komisaris Pertamina Hulu Energi. Utama, lagi. Jadi kalau pikirannya bergetar ke arah “hulu”, itu bukan salah dia. Namanya juga pejabat, ya harus loyal pada diksi tempatnya bertugas.
Itu tupoksi, kata orang. Tapi kalau sampai semua energi dipahami lewat kaca mata “hulu–hilir”, saya kok jadi curiga: jangan-jangan Bung Denny ini sedang terjebak dalam dunia yang jalannya cuma satu arah, dari ladang ke pipa, dari bor ke bak penampung.
Padahal zaman sekarang, energi tak melulu harus lewat jalan panjang seperti sinetron Indosiar —yang dari episode ke episode masih juga belum sampai ke pernikahan. Listrik dari matahari misalnya, cukup pasang panel di atap rumah, lalu jreng! colok rice cooker, hidup.
Dengan energi terbarukan, kita tak perlu ngebor sampai ke sumur kenangan. Tak ada perlu “hulu” dan “hilir” dalam pengertian klasik. Panel surya itu kayak cinta yang langsung nyambung —tak perlu PDKT panjang. Matahari bersinar, panel bekerja, listrik menyala.
Begitu pula tenaga air: tinggal alirkan sungai ke turbin, lalu sambungkan ke kabel. Tak ada embel-embel penyulingan, pengolahan, atau pemurnian. Uap panas bumi juga begitu.
Bahkan angin pun tak rewel: asal ada turbin yang siap diputar, dia akan menari dan menghasilkan listrik, tanpa minta kompensasi angin malam.
Nah, energi model begini mungkin tak cocok kalau dibawa ke dalam logika “hulu-hilir” yang dibanggakan. Sebab energi terbarukan itu seperti makanan dari dapur ibu: langsung jadi, langsung kenyang, tanpa harus lewat dapur industri.
Tak ada minyak mentah yang harus diolah jadi bensin, solar, atau avtur. Tak perlu dilewatkan ke kilang, tangki timbun, lalu masuk pom bensin. Energi terbarukan itu singkat, padat, dan nikmat.
Tapi karena terlalu sederhana, mungkin kurang seksi bagi mereka yang terbiasa bermain dalam rantai industri panjang yang sarat fee dan proyek.
Makanya saya bisa mengerti mengapa Bro Denny lebih tertarik pada kisah shale oil Amerika —kisah cinta lama yang direkayasa agar tetap hidup, meski ongkosnya mahal dan hasilnya tak seberapa. Si George Mitchell itu, konon, butuh berpuluh tahun untuk bisa bikin batu serpih bicara.
Itu semacam kisah LDR energi yang luar biasa sabar: berpuluh tahun naksir, baru bisa memeluk. Tapi setelah berhasil, Amerika jadi mandiri energi, katanya. Walau ya, di balik itu semua, ada kerusakan lingkungan, pencemaran air tanah, dan debat global tentang _fracking_ yang tak kalah gaduh dari rapat anggaran DPR.
Lalu, mengapa negara seperti Arab Saudi atau Iran tidak ikut-ikutan menggali serpih? Ya karena mereka punya ladang minyak yang melimpah ruah, mengalir deras tanpa perlu ditekan paksa. Kalau punya sumur zam-zam, buat apa susah-susah menyuling embun dari genteng?
Sementara Indonesia? Kita punya potensi minyak serpih juga, katanya. Tapi izinkan saya tertawa pelan. Negara ini sering merasa punya segala, tapi untuk menggali satu proyek saja bisa habis waktu dua periode presiden. Kita ini lebih jago membuat peta potensi daripada mewujudkannya.
Panel surya bisa dipasang di jutaan atap rumah, tapi yang terjadi malah subsidi listrik untuk PLTU batu bara diperpanjang. Katanya kita hendak menuju “net zero emission“, tapi jalannya tetap lewat batubara yang hitam legam.
Dan saya tahu, Bung Denny tentu tidak sedang anti terhadap energi terbarukan. Tak usah diragukan. Ratusan bait puisi esai Bro DJA penuh dengan pemihakan pada energi terbarukan.
Tapi kalau dalam tulisannya kali ini energi seperti matahari dan angin nyaris tak disebut, itu karena mungkin memang tidak sempat nongol dalam pikiran karena sibuk rapat komisaris.
Atau jangan-jangan, karena energi terbarukan tak cocok dimasukkan ke dalam folder “hulu”. Nah, kalau sudah begitu, paradigma berpikir BUMN energi perlu dibongkar.
Karena apa? Karena kita sedang memasuki era baru: era di mana “hulu” dan “hilir” tak lagi relevan. Energi kini bisa lahir langsung di tempat orang tinggal.
Panel surya di atap rumah Anda, itu sudah sekaligus “pembangkit” dan “konsumen”. Tidak ada jarak. Tidak ada jaringan distribusi panjang. Energi langsung nyala, langsung pakai. Seperti senter cinta di malam gelap.
Coba bayangkan: sebuah desa di NTT, tak pernah teraliri listrik PLN. Tapi dengan panel surya, mereka bisa mengisi HP, menonton TV, bahkan bikin usaha kecil.
Di mana “hulunya”? Di mana “hilirnya”? Semuanya terjadi di tempat yang sama. Energi terbarukan adalah demokratisasi listrik. Ia tak perlu izin tambang. Tak butuh tender pengadaan rig. Ia cuma butuh kemauan, dan sinar matahari.
Tapi ya, saya maklum juga kalau di benak para teknokrat dan komisaris, semua itu belum “industri”. Energi yang tak bisa digali, dijual, dan dinegosiasikan dalam blok migas, dianggap belum layak dibanggakan. Mungkin karena itu pula, dalam banyak kebijakan, energi terbarukan masih seperti anak tiri: disayang di pidato, tapi dilupakan di anggaran.
Padahal, Bung, kalau kita sungguh-sungguh mau, negeri ini bisa menyalakan seluruh kampung dengan tenaga surya, menyejukkan sekolah dengan turbin angin, dan menghidupi industri dengan panas bumi.
Kita punya semua modalnya: cahaya, angin, air, uap. Yang kurang cuma satu: keberanian untuk melepaskan diri dari romantisme hulu–hilir yang terlalu panjang dan mahal.
Jadi, Bung Denny, mari sesekali menulis dari atap rumah, bukan dari sumur bor. Cobalah merayakan energi yang langsung jadi, yang tak harus dibungkus dalam istilah teknokratik. Sebab masa depan, Bung, barangkali bukan di dalam tanah —melainkan justru di langit terbuka.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 7/8/2025