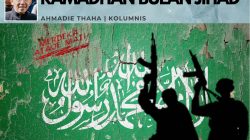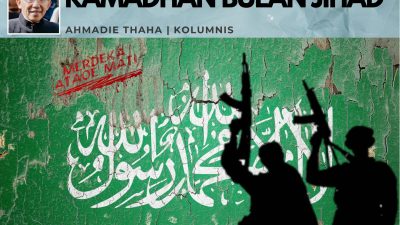Catatan Cak AT
Negeri ini katanya negeri beragama. Adzan lima waktu bersahut-sahutan, masjid megah berdiri di setiap blok, dan khutbah Jumat seringkali terdengar lebih panjang daripada rapat DPR yang gagal kuorum. Tapi entah mengapa, angka korupsi kita tetap saja melesat seperti harga cabai saat Lebaran.
Saya tidak mengatakan agama tak berguna. Tapi seperti SIM—agama itu ada yang asli, ada pula yang “nembak”. Banyak warga negeri ini yang tampaknya hanya lulus “tes fikih”, tapi tak pernah menyentuh pelajaran “akhlak lanjutan”.
Seperti kata Profesor Mahmud Erol Kilic dari Turki, dalam suatu diskusi di Jakarta belum lama ini, agama yang diajarkan di negeri-negeri Muslim terlalu fokus pada syariat teknis: shalat, puasa, zakat.
Soal larangan mencuri uang rakyat? Jarang disentuh, apalagi dikhutbahkan. Seolah-olah selama sujudnya mendalam dan sedekahnya mengalir deras, maka rekening siluman pun dianggap halal.
Ajaibnya, kadang uang hasil rampokan berjamaah justru dijadikan modal mendekati surga. Bangun masjid pakai dana haram, lalu bangganya setengah mati: “Biar uang saya dulu gelap, sekarang sudah dibersihkan lewat program wakaf.” Maaf, Pak, itu bukan dibersihkan, tapi dicuci—dan dalam hukum, itu disebut _money laundering._
Survei Pew Research 2024 menobatkan Indonesia sebagai negara paling religius. Saya tidak kaget. Soal jumlah masjid, hafalan doa, dan peziarah kuburan wali, kita mungkin memang nomor satu.
Tapi mari bandingkan dengan CPI _(Corruption Perception Index)_ dari Transparency International: tahun 2024, Indonesia ada di peringkat 99 dari 180. Syukurlah, naik dari posisi 115. Berarti masih banyak ruang untuk turun lagi.
Tapi ini sungguh ironi bertingkat: kita menjadi negara yang paling rajin berdoa, tapi juga paling rajin mengambil uang yang bukan haknya. Kita percaya pada hari Kiamat, tapi seringkali lebih takut audit BPK daripada azab Tuhan. Kita takut makan babi, tapi santai makan uang bansos.
Mari kita jujur: korupsi kita bukan cuma soal sistem. Ini soal etos —atau lebih tepatnya, kehilangan etos. Kalau ibadah dijadikan jubah untuk menutupi kejahatan, maka religiusitas bukan lagi alat penyucian diri, tapi kosmetik sosial.
Kita berdoa, tapi sambil mencurangi pajak. Kita menangis dalam zikir, lalu bersorak saat memenangkan tender fiktif.
Kadang saya heran, mungkin di neraka ada jalur khusus untuk para koruptor religius: antrean panjang lengkap dengan peci dan gamis, masing-masing bawa tasbih dan daftar proyek siluman. Lalu malaikat bertanya: “Ini pahala dari sedekah, atau hasil dari markup paving block kantor desa?”
Kita tidak kekurangan ustadz, kiyai, atau penceramah motivasional. Tapi kita kekurangan pemuka yang berani bicara korupsi sebagai kejahatan akhlak, bukan sekadar dosa ringan yang bisa dimaafkan dengan umrah VIP.
Kita butuh ulama yang membahas soal _ghulul_ (penggelapan harta umat) lebih dari sekadar hukum potong tangan pencuri sandal.
Bayangkan, kalau setiap khutbah Jumat di negeri ini menyelipkan ayat tentang kejujuran, ancaman neraka bagi pengkhianat amanah, dan larangan keras menilep dana bansos, mungkin negeri ini akan lebih cepat beres daripada harus nunggu reshuffle kabinet.
Agama adalah cahaya, begitu kata para sufi. Tapi kalau lampu itu dicolokkan ke kabel korup, maka cahayanya cuma ilusi. Kita tak bisa terus membanggakan religiusitas jika akhlak kolektif kita macet di simpang etik.
Mungkin, negeri ini bukan kekurangan agama, tapi kelebihan dalih. Kita terlalu sering mencari pembenaran, bukan pertobatan. Dan sampai kita mengakui bahwa korupsi itu bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan iman, maka negeri religius ini akan terus jadi ironi — tempat surga dijanjikan, tapi neraka yang dibangun.
Maaf, catatan ini bukan untuk mereka yang jujur dan diam-diam bekerja tanpa pamrih. Ini untuk yang merasa dirinya “wakil Tuhan”, tapi ternyata hanya wakil dari rekening gelap.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 29/7/2025