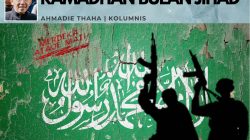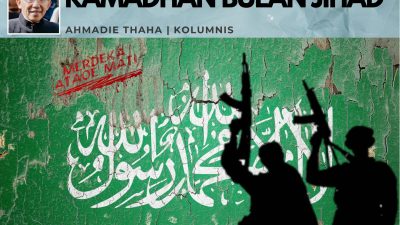Catatan Cak AT
Pernah dengar kisah Walisongo membubarkan pengajian? Tidak? Ya, tentu saja tidak. Sebab para wali itu bukan geng preman. Mereka bukan laskar dadakan yang nongkrong menunggu aba-aba untuk “sikat pengajian.” Mereka adalah pencerah zaman, bukan pemicu kerusuhan.
Namun zaman memang sudah bergeser. Kini, ada yang menamakan diri pewaris perjuangan Walisongo di Indonesia lengkap dengan embel-embel laskar. Mereka seolah hendak menabalkan diri sebagai penerus garis keras —eh, garis dakwah para wali.
Tapi anehnya, yang mereka tampilkan justru bukan kelembutan dan kebijaksanaan para wali, melainkan seragam, yel-yel, dan kerumunan massa yang siap menerkam siapa saja yang tidak cocok tafsirnya. Jika para wali yang sembilan bangun dari kubur, mereka mungkin menangis.
Perkumpulan laskar itu belum lama berdiri, dan untuk pertama kalinya menggelar musyawarah kerja nasional. Semangatnya: memberantas radikalisme, menyelamatkan NKRI, dan mengusir paham-paham transnasional. Sah-sah saja mereka bikin mukernas.
Tapi setelah itu, alih-alih memproduksi buku dakwah atau menyusun program literasi masjid, mereka malah tampak lebih sibuk membentuk “laskar-laskaran” lengkap dengan jargon nasionalisme rasa milisi. Apakah ini transformasi ormas ke ormas bersenjata niat?
Yang lebih menggelikan: mereka mengklaim sebagai penjaga ajaran Walisongo sambil menolak secara frontal nasab habaib Ba ‘Alawi. Mereka pun mencatat nama-nama habib yang mereka identifikasi punya nasab demikian. Silakan punya pendapat atau bikin catatan.
Tapi kalau ujungnya adalah mengerahkan massa untuk membubarkan pengajian, itu bukan diskusi ilmiah. Itu penyerbuan. Dan para wali, di negeri ini dan di dunia, sejauh sejarah mencatat, tidak pernah menyerbu majelis zikir. Mereka menyalakan lilin, bukan meniupnya.
Tragedi Pemalang menjadi puncak kekacauan itu: sebuah tabligh akbar damai yang menghadirkan Habib Rizieq Shihab, seorang habib yang diidentifikasi keturunan Alawi, tiba-tiba disambut bukan oleh hujan doa, tapi lemparan tangan kosong dan teriakan takbir dari massa laskar.
Dari mana laskar ini muncul, jelas sekali asal-muasalnya. Dari rekaman video yang menampilkan kesiapan “perang” yang mereka lakukan, jelas tindakan mereka tidak mencerminkan ajaran sembilan wali. Bahkan mungkin tak mencerminkan akhlak awam sekalipun.
Pertanyaannya sederhana: Apa yang mendorong sekelompok orang mengklaim dakwah tapi bersikap seperti garda kekerasan? Apakah karena ketakutan ideologis? Atau karena gagal memahami bahwa dakwah tak bisa dipaksakan dengan ancaman?
Negara ini punya hukum. Punya mekanisme peradilan. Jika ada ceramah yang menyimpang, laporkan. Bukan malah membentuk pasukan swadaya berbekal semangat “main hakim sendiri.” Itu bukan dakwah. Itu _ngawuriyah fi sabilil emosi._
Mengklaim sebagai pewaris Walisongo bukanlah dengan mencetak stiker, membentuk laskar, lalu menyerang pengajian. Walisongo dengan kesembilan walinya bukan organisasi yang bisa didaftarkan di Kemenkumham. Mereka adalah arsitek ruhani bangsa ini.
Walisongo menanamkan dakwah sejuk, penuh cinta dari pesisir hingga pedalaman, tanpa laskar. Sunan Kalijaga berdakwah lewat budaya. Sunan Bonang lewat gamelan. Sunan Giri mendirikan madrasah. Tak satu pun dari mereka yang mengumpulkan pasukan untuk mengusir ulama lain hanya karena berbeda tafsir atau berbeda jalur sanad.
Maka, tak aneh jika banyak pernyataan keras mengkritik mereka: ini bukan lagi perdebatan tafsir, ini adalah penghinaan terhadap hukum. Tindakan kekerasan terhadap acara keagamaan yang sah dan damai adalah bentuk terorisme sipil —dan negara tidak boleh tutup mata.
Jika hari ini negara diam, maka esok kita tak tahu siapa lagi yang akan dibubarkan. Mungkin majelis yasin di kampung. Mungkin pengajian ibu-ibu. Mungkin sekolah-sekolah. Kita hidup dalam negara hukum, bukan negara ormas siapa cepat dia berkuasa.
Rakyat perlu tahu: sejarah tak pernah memihak penindas. Jejak kekerasan oleh kelompok yang mengklaim suci selalu berakhir di pinggir sejarah. Tidak ada satu pun kekuatan moral yang bertahan jika dibangun di atas kepalan tangan dan makian.
Yang bertahan adalah cinta. Dakwah. Dan ilmu. Seperti yang dilakukan Walisongo —yang sesungguhnya. Jika kumpulan laskar tersebut benar ingin menjaga warisan Walisongo, maka mari kita ajak mereka membuka kembali kitab sejarah.
Seharusnya mereka mau duduk, berdiskusi, berdebat dengan data dan dalil, bukan dengan tinju dan tendang. Sebab yang waras tak akan membubarkan pengajian. Yang benar tak akan takut pada ceramah. Dan pewaris Walisongo seharusnya tak perlu membentuk laskar.
Catatan ini saya buat tidak sedang menyerang siapa pun, tapi sedang menertawakan betapa mudahnya label “Wali” disematkan tanpa warisan ilmu dan akhlak. Jika merasa tersinggung, boleh jadi itu karena masih merasa berhak memukul orang lain atas nama dakwah.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Jakarta, 27/7/2025