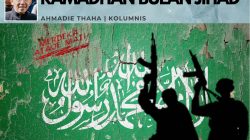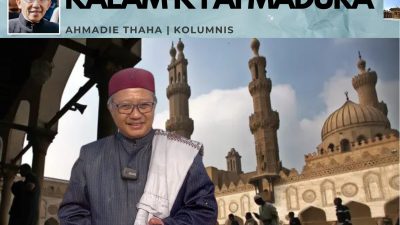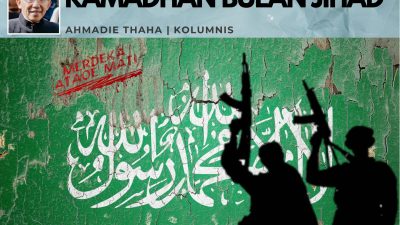Catatan Cak AT
Ketika sepotong roti tak bisa dibagi, solidaritas pun roboh. Filiu mencatat bukan hanya rumah yang hancur, tapi juga jalinan keluarga, martabat, dan peradaban yang dicabut perlahan.
Ada tragedi yang lebih senyap dari ledakan bom. Ia tidak terekam kamera, tidak mengundang headline, dan tak pernah diumumkan oleh juru bicara militer. Tragedi itu bernama keruntuhan ikatan sosial.
Di Gaza, Prof. Jean-Pierre Filiu menyaksikan sendiri bagaimana satu demi satu fondasi kebersamaan rakyat Palestina ambruk, bukan karena mereka menyerah, tetapi karena segala sesuatu yang menopang hidup mereka—pangan, listrik, air, tempat aman, bahkan harapan—dicabut hingga habis.
“Bahkan mereka yang ingin berbagi makanan tak lagi bisa melakukannya,” tulis Filiu. “Bukan karena tidak mau, tetapi karena seluruh keluarganya sendiri juga sedang kelaparan.”
Gaza dulunya dikenal dengan solidaritas sosialnya yang luar biasa. Ikatan kekerabatan, jaringan kerabat jauh, sistem gotong royong—semua itu menjadi pelindung tak resmi masyarakat dari krisis.
Tapi kini, menurut Filiu, semua itu mengerut menjadi lingkaran keluarga terkecil. Dulu, para paman, bibi, dan sepupu sangat dekat satu sama lain. Sekarang, semua orang hanya fokus menyelamatkan anak dan istri mereka sendiri.
Ini bukan keegoisan. Ini adalah mekanisme bertahan hidup terakhir. Ketika setiap butir nasi menjadi taruhan hidup, bahkan sekadar menawarkan bantuan menjadi kemewahan moral yang tak mampu dilakukan siapa pun.
Namun di tengah kehancuran dan kelaparan itu, ada serpihan kemanusiaan yang membuat mata Filiu berkaca. Ia menceritakan anak-anak kecil yang berbagi remah roti mereka dengan kucing-kucing liar yang sama laparnya.
Ketika ditanya mengapa mereka melakukannya, jawaban mereka sederhana dan menghantam jantung: “Kami tahu rasanya lapar. Kami tidak ingin kucing-kucing itu merasakannya juga.”
Lalu ada penyintas yang membersihkan tenda di tengah reruntuhan, membuang sampah seperti hendak menjaga harga diri rumah yang sudah tak ada.
Ada juga keluarga yang menggantung pakaian mereka di balkon bangunan yang nyaris roboh, seolah berkata bahwa mereka masih hidup, masih manusia._ Dan ada tenda-tenda warna-warni yang memantulkan cahaya di atas lanskap abu-abu—seperti _doa visual untuk tetap eksis.
Di Gaza, orang mati tidak lagi bisa dikubur layak. Pemakaman dihancurkan. Rumah sakit menolak mayat. Dan orang-orang, dalam putus asa, mulai menulis nama-nama orang mati di reruntuhan rumah sebagai peringatan terakhir.
“Berkabung sudah beku, tidak pernah utuh,” kata Filiu. Jika korban adalah anak-anak, sering kali disertai gambar kecil di samping namanya: sepatu kecil, boneka, atau simbol sederhana sebagai tanda cinta yang tak sempat diungkapkan.
Filiu menggambarkan realitas kebersihan dan sanitasi sebagai “perjuangan untuk bertahan hidup”. Lubang-lubang di pasir menjadi toilet yang ditutupi kanvas.
Air minum didapat dari sumur-sumur yang digali di sudut tenda. Sampah berserakan, belum sempat diangkut karena pengangkutnya pun telah terbunuh. “Setiap kebutuhan dasar manusia di sini adalah pertarungan,” tulisnya.
Penyakit menyebar: diare, infeksi kulit, hepatitis. Perempuan lebih terdampak. Mereka tak punya ruang aman, tak punya sabun, dan tak punya waktu untuk sekadar merasa malu.
Bahkan cuaca menjadi pembunuh. Pada malam Natal, bayi bernama Sila meninggal karena kedinginan di usianya yang baru tiga minggu. Dalam beberapa pekan itu saja, lima anak lain mati karena hal serupa.
Inilah kematian tanpa peluru, tanpa suara ledakan. Tapi hasilnya sama: jiwa yang melayang, keluarga yang hancur.
Namun Gaza tak sepenuhnya sunyi. Ada badut medis yang masih berkeliling rumah sakit, mencoba memancing senyum dari anak-anak yang terluka.
Ada anak perempuan kecil dengan tas sekolah lusuh, muncul dari lorong-lorong sempit menuju madrasah yang disokong oleh Kesultanan Oman.
Mereka bukan simbol perlawanan. Mereka adalah saksi bahwa kehidupan masih mencoba bertahan, bahkan ketika dunia memilih menutup mata.
Yang paling menghancurkan dari laporan Filiu bukan hanya deskripsi kehancuran fisik. Tapi peta psikososial dari satu masyarakat yang pelan-pelan kehilangan sesuatu yang bahkan lebih mendasar dari rumah atau makanan: kehilangan jalinan sesama manusia.
Gaza telah dibuat tak hanya kelaparan, tapi kesepian. Mereka dibiarkan hidup dalam dunia di mana tidak ada yang bisa menolong siapa pun lagi.
Dan itu, menurut Filiu, adalah tujuan tersembunyi dari blokade: membuat rakyat Palestina merasa sendirian, tidak layak ditolong, dan akhirnya kehilangan satu sama lain.
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 19/7/2025