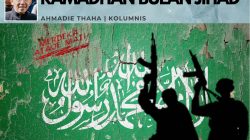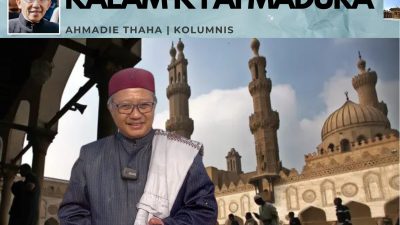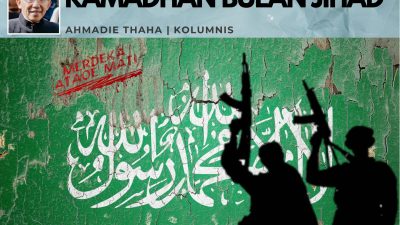Catatan Cak AT
Kita sering mendengar jargon itu: “yang penting halal.” Ya, halal sudah jadi semacam sertifikasi sosial yang melekat di plastik mi instan, sabun muka, bahkan air galon isi ulang.
Asal ada logo halal MUI, kita langsung lega. Tapi sabar dulu. Nabi bukan cuma bilang “halal”, tapi juga thayyib. Ayatnya di al-Baqarah 168: halalan thayyiban tertulis lengkap dalam satu tarikan nafas, eh kalimat.
Dan itu bukan nama kucing Arab atau artis TikTok dari Yaman. Dalam hadis ke-10 di kitab al-Arba’in an-Nawawi, Rasulullah ﷺ bersabda:
> “Sesungguhnya Allah itu Thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib…”
Lalu beliau menceritakan seseorang yang kusut, dekil, menengadah ke langit, berdoa-doa sampai suara seraknya bikin malaikat tutup telinga. Tapi, ya tapi, doanya tak dikabulkan.
Kenapa? Karena “makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram.” Astaga, paket lengkap! Pantesan anak-anak dari keluarga demikian susah banget hidupnya.
Lantas, thayyib itu apa, sih? Ini yang saya singgung dalam kongkow Majelis Masyayikh PUI di rumah asri Pak Kyai Ahmad Heryawan, dekat penjara Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Secara bahasa, “thayyib” artinya baik, suci, bersih, berkualitas, dan layak. Dalam konteks makanan, ia bisa berarti: bergizi, higienis, dan sehat secara medis. Kebetulan, makanan sajian kongkow tadi dari alam langsung.
Maka, kalau kamu makan ayam goreng pinggir jalan yang digoreng ulang pakai oli bekas motor 2-tak —walau ayamnya hasil sembelihan halal— itu belum tentu thayyib! Itu makan oli, namanya.
Halal itu soal hukum: boleh atau tidak.
Thayyib itu soal mutu: baik atau buruk.
Jadi, halal adalah tiket masuk, tapi thayyib adalah standar kualitas. Bayangkan Anda masuk restoran —izin halal sudah ada, tapi ternyata ayamnya disuntik formalin, sayurnya disiram pestisida, minyaknya sudah tiga generasi. Mau?
Allah saja tak mau yang asal-asalan. Allah itu Thayyib, kata Nabi ﷺ. Artinya, Allah Mahasuci, tidak menerima kecuali yang suci pula —dari cara cari duit, cara belanja, sampai cara masak dan menyuap ke mulut.
Ayatnya tegas:
> “Wahai para Rasul, makanlah dari yang thayyibat dan berbuatlah amal saleh.” (QS. al-Mu’minun: 51)
> “Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang thayyib yang Kami berikan.” (QS. al-Baqarah: 172)
Lho, perhatikan ayat di atas, bahkan para rasul pun disuruh makan thayyibat dulu sebelum bisa beramal saleh. Jadi, kalau Anda belum bisa move on dari gorengan plastik dan kopi saset pewarna rasa stroberi, bisa jadi amal saleh Anda masih di bawah standar WHO —eh, maksud saya, standar langit.
Banyak doa tapi gagal terkabul? Mungkin bukan kurang dzikir, tapi kurang thayyib. Lelaki yang disebut Nabi dalam hadis tadi sudah memenuhi “syarat-syarat doa makbul” versi ustaz-ustaz Instagram:
– Safar jauh
– Penampilan lusuh penuh duka
– Menengadah ke langit
– Menyebut “Ya Rabb… Ya Rabb…”
– Tapi tetap gagal.
Kenapa? Karena logistik spiritualnya cacat mutu. Semua isi tubuhnya —dari kalori sampai sel darah merah— disuplai oleh barang haram. Jadi, bagaimana mungkin “sinyal doanya” nyambung ke langit, kalau provider-nya haram?
Hadis ini juga menyindir kaum sufi palsu yang merasa makin dekat ke surga jika makin dekil. Mereka menolak dunia, tak beristri, tapi ngotot nerima pemberian umat. Maaf ya, ini bukan ajaran Nabi ﷺ.
Dalam hadis lain, Nabi ﷺ bahkan bersabda:
> “Aku berpuasa dan berbuka, aku tidur dan salat malam, aku menikah, aku makan daging —siapa yang tidak mau dengan sunnahku, bukan dari golonganku.”
Maka, menjadi saleh bukan berarti anti makan enak, anti gizi, dan doyan hidup kumuh. Makan yang thayyib itu justru syariat.
Namun, ada juga orang yang bilang: “Yang penting niat, bro. Aku ambil uang korupsi ini, terus disedekahin.” Yakin? Maaf, hadis Nabi sangat jelas:
> “Allah tidak menerima sedekah dari harta ghulul (haram).” (HR. Muslim)
Memberi dari harta haram itu ibarat mencuri tas orang lalu menyumbangkan isinya ke panti asuhan, sambil bilang: “Lillahi ta’ala.” Yah, malaikat pencatat amal sampai geleng-geleng kepala.
Tapi thayyib tak cukup hanya disuarakan dari mimbar —harus punya standar nyata. Tentu kita tidak ingin pembahasan soal thayyib hanya berakhir di mimbar-mimbar khotbah atau caption Instagram ustadz-ustadz viral.
Thayyib bukan semata konsep spiritual, ia perlu punya indikator nyata yang bisa dipegang, diuji, dan disepakati bersama.
Di dunia nyata, kita beruntung karena sudah ada badan-badan pengatur yang menyediakan standar untuk menilai apakah suatu produk benar-benar baik dan layak dikonsumsi.
Di Indonesia, ada BPOM yang menguji kandungan makanan, obat, dan kosmetik dari sisi kimia, mikrobiologi, dan toksikologi.
Lalu ada SNI yang menetapkan standar mutu produk, termasuk pangan, tekstil, bahkan air minum dalam kemasan.
Secara internasional, lembaga seperti FDA di Amerika, dan standar Codex Alimentarius dari FAO-WHO menjadi rujukan global bagi keamanan pangan dan obat-obatan.
Bahkan Uni Eropa punya daftar panjang zat aditif yang dilarang meski dianggap aman di negara lain.
Tak hanya soal makanan, prinsip thayyib bisa meluas ke dunia konstruksi dan manufaktur. Sebuah rumah potong hewan misalnya, tidak cukup hanya halal dalam teknis penyembelihannya, tapi juga harus punya sistem sanitasi yang baik, manajemen limbah yang bertanggung jawab, dan perlakuan hewan yang manusiawi.
Di sinilah standar seperti ISO 22000 untuk sistem manajemen keamanan pangan, atau sertifikasi lingkungan seperti LEED dan Green Building Council menjadi penting.
Semuanya berfungsi sebagai pagar teknis agar thayyib tidak hanya indah di ucapan, tapi juga kokoh dalam tindakan.
Contoh praktis bisa dilihat di mana-mana. Produk halal yang dipasarkan dengan klaim religius, tapi ternyata menggunakan pewarna tekstil atau pemanis sintetis yang memicu kanker, jelas bukan thayyib.
Produk makanan rumahan yang dibuat oleh ibu-ibu salehah dengan doa-doa panjang, tapi disimpan di tempat lembap penuh jamur, juga tidak bisa disebut thayyib.
Bahkan mushaf Al-Qur’an yang dicetak murah dengan tinta mengandung timbal berat pun secara teknis menodai prinsip thayyib, meskipun niatnya baik.
Jadi, thayyib bisa —dan seharusnya— dilacak, diuji, dikontrol. Kita memerlukan ulama yang melek laboratorium, insinyur yang paham fiqih, dan regulator yang berintegritas untuk menjembatani langit dan bumi.
Thayyib adalah tempat perjumpaan antara nilai langit dengan verifikasi duniawi.
Walhasil, kalau ingin hidup kita berkah, doa kita terkabul, dan amal kita diterima, mari kita mulai dari hal paling dasar: apa yang masuk ke mulut kita.
Allah itu Thayyib. Jangan sodorkan ke Dia invoice amal yang ditulis dengan tinta dari rezeki yang kotor, buram, dan penuh pengawet.
Jadilah muslim yang bukan hanya halal, tapi juga thayyib: secara hukum ya, secara klinis oke, secara spiritual berkualitas.
Karena surga bukan pasar grosir —yang penting bukan cuma murah dan halal, tapi juga layak masuk langit.
Kalau Anda setuju, mari kita mulai revolusi dari isi piring.
Bukan cuma halal, Bung. Tapi thayyib! 🍽️✅
Cak AT – Ahmadie Thaha
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 4/7/2025